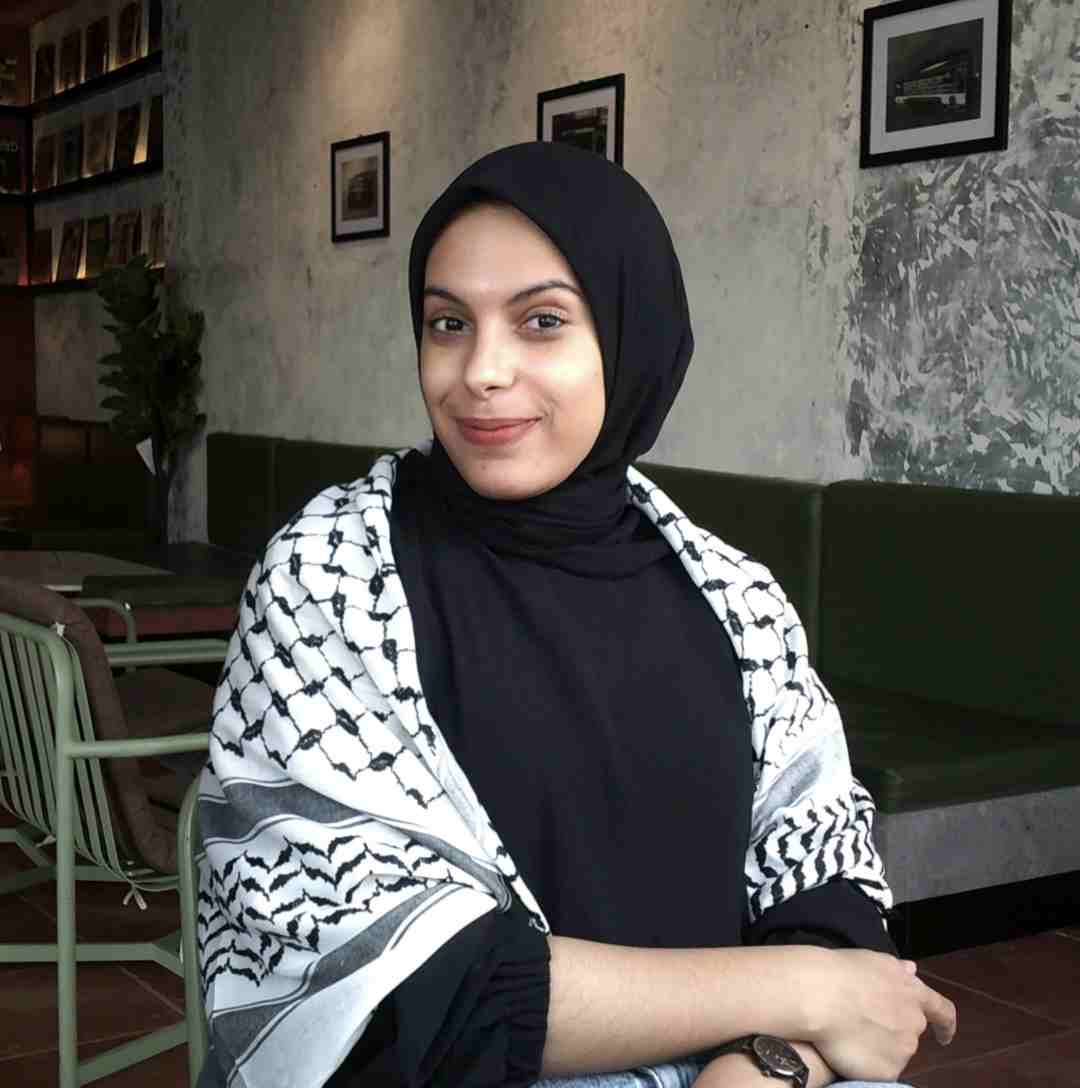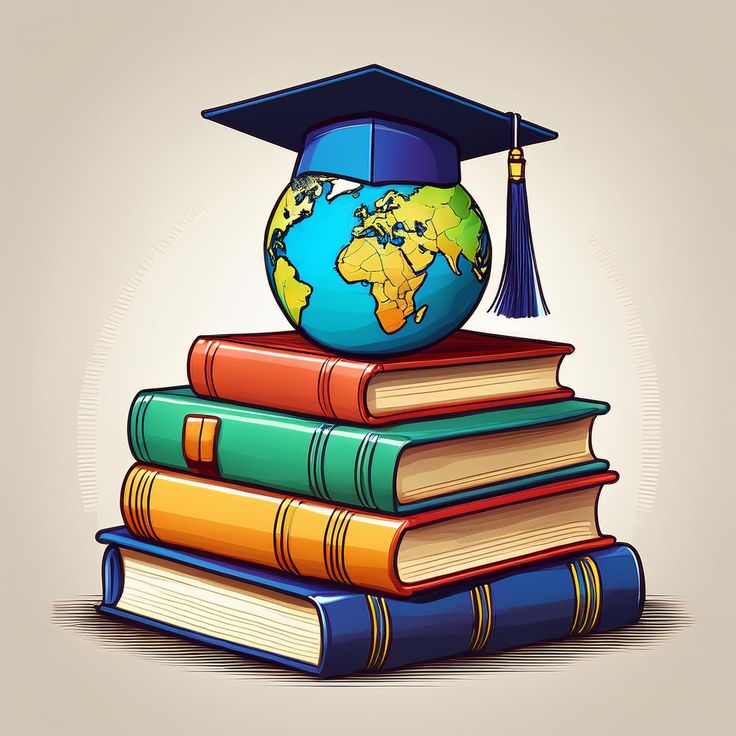Fitur Close Friends: Realitas Panggung Belakang yang Palsu?


Oleh: Faiz Rafdillah *)
SUARAMUDA, SEMARANG – Di era di mana hampir setiap sudut kehidupan bisa menjadi konten, kebutuhan akan ruang privat menjadi semakin mendesak, atau setidaknya, terasa mendesak.
Di antara ruang-ruang yang semakin terbuka dan algoritma yang terus menuntut performa, fitur Close Friends di Instagram hadir sebagai “jalan keluar” yang menjanjikan.
Ia disebut-sebut sebagai ruang aman, ruang jujur, tempat di mana seseorang bisa tampil tanpa topeng, tanpa sensor, tanpa tekanan performatif.
Namun, seperti halnya banyak ilusi di dunia digital, kehadiran fitur ini justru menimbulkan pertanyaan: apakah kita benar-benar sedang berada di ruang belakang?
Ataukah ini hanyalah bentuk baru dari panggung yang lebih eksklusif, lebih subtil, dan lebih personal, tapi tetap penuh kalkulasi?
Fenomena ini membuka diskusi menarik tentang identitas digital, strategi sosial, dan dramaturgi diri di era media baru.
Dalam teori dramaturgi yang diperkenalkan Erving Goffman, kehidupan sosial dibagi menjadi dua wilayah: front stage, di mana individu menampilkan versi terbaiknya di depan audiens, dan back stage, ruang privat untuk menjadi diri sendiri tanpa penghakiman.
Tapi di era media sosial, batas antara panggung dan belakang panggung tak lagi jelas. Bahkan ruang yang katanya tertutup, sering kali tetap dipoles demi impresi.
Close Friends bisa jadi terlihat seperti backstage, tapi siapa yang memilih siapa yang bisa masuk ke dalamnya? Apa motif dari konten yang dibagikan? Mengapa masih terasa seperti perlu tampil, walau hanya di depan segelintir orang?
Di ruang ini, keintiman bukan hanya soal kedekatan, tetapi bisa jadi adalah bentuk lain dari performa yang lebih eksklusif.
Kita tidak sedang jujur, kita hanya sedang menampilkan versi “rapuh” yang terkontrol, versi “receh” yang lucu untuk dinikmati bersama, atau bahkan versi “emosional” yang sengaja dibagikan untuk membangun koneksi sosial. Kita tetap bermain peran, hanya dengan kostum dan naskah yang lebih kasual.
Tulisan ini akan menelusuri bagaimana fitur Close Friends telah menciptakan realitas yang ambigu, antara keaslian dan performa, antara keintiman dan eksklusivitas, antara ekspresi dan strategi.
Di bawah sorotan teori dramaturgi, kita akan mengkaji apakah ruang yang kita anggap paling “jujur” di media sosial sebenarnya adalah panggung yang paling diam-diam penuh peran.
Close Friends Sebagai “Ruang Belakang” Baru
Ketika media sosial menjadi panggung yang terbuka lebar bagi siapa saja, kebutuhan akan ruang untuk “melepaskan peran” semakin terasa.
Di sinilah fitur seperti Close Friends mendapatkan momentumnya, ia hadir menawarkan sesuatu yang langka di dunia digital: ruang terbatas. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat, hanya audiens terpilih yang bisa mengakses sisi diri yang tidak diperlihatkan kepada publik.
Di mata banyak pengguna, Close Friends menjadi simbol kepercayaan, keintiman, dan kebebasan. Namun dalam praktiknya, “ruang belakang” yang ditawarkan oleh fitur ini tidak sesederhana itu. Keputusan siapa yang masuk ke dalam daftar Close Friends pun adalah proses kurasi sosial.
Kita memilih orang-orang yang dianggap cukup dekat, cukup bisa dipercaya, tapi juga cukup bisa “mengerti citra” yang ingin kita tampilkan di ruang tersebut.
Artinya, bahkan dalam ruang yang diklaim privat ini, kita tetap menyusun audiens. Kita tidak sedang “melepaskan topeng”, kita hanya mengganti topengnya dengan yang tampak lebih kasual, lebih jujur, padahal tetap terkontrol.
Ada ironi halus di balik fitur ini. Alih-alih menjadi ruang untuk diam, untuk jujur tanpa naskah, Close Friends sering kali berubah menjadi panggung kecil yang bersuasana lebih akrab, tapi tetap panggung.
Kita masih memikirkan bagaimana unggahan akan diterima, apakah akan dianggap lucu, relatable, atau “sarkas yang elegan”. Kita tetap menciptakan narasi, hanya saja dengan penonton yang lebih terseleksi.
Di sinilah batas antara backstage dan front stage menjadi kabur. Ruang yang katanya privat, ternyata tidak bebas dari strategi. Keputusan untuk berbagi pun bukan sekadar bentuk ekspresi spontan, melainkan bagian dari performa sosial yang lebih personal namun tetap politis.
Kita tetap memanajemen kesan, bukan untuk publik luas, tetapi untuk audiens yang kita anggap penting. Close Friends pada akhirnya bukan ruang di luar panggung.
Ia justru bisa menjadi bentuk baru dari pertunjukan yang lebih tenang, lebih personal, tapi tetap penuh kalkulasi. Ia bukan tempat kita berhenti tampil. Ia hanya membuat kita merasa lebih nyaman saat tampil.
Dramaturgi Digital: Saat Backstage Pun Jadi Panggung
Erving Goffman dalam teori dramaturginya membagi dunia sosial ke dalam dua ruang utama: panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage).
Di panggung depan, kita tampil untuk publik, menyusun impresi dan memainkan peran sesuai ekspektasi sosial. Sementara di belakang panggung, kita seharusnya bisa bersikap lebih lepas, jujur, dan tidak dibatasi oleh norma-norma performatif.
Di sanalah seharusnya keotentikan bertahan. Namun di era media sosial, batas itu tak lagi sejelas dulu. Bahkan ruang yang tampaknya bersifat “pribadi”, seperti Close Friends, telah mengalami pergeseran.
Backstage kini bukan lagi tempat di mana kita berhenti bermain peran, tetapi justru tempat di mana kita memainkan peran yang berbeda. Lebih subtil, lebih santai, tapi tetap dikalkulasi.
Di sinilah muncul konsep yang bisa disebut sebagai “dramaturgi digital”, di mana semua ruang, bahkan yang paling personal di dunia maya, adalah bagian dari ekosistem performatif.
Kita mungkin tidak sedang bermain untuk ribuan audiens, tapi kita tetap bermain untuk “penonton pilihan”.
Dan terkadang, panggung kecil ini justru lebih membuat kita berhati-hati. Karena kedekatan menciptakan tekanan sosial baru: untuk tampil apa adanya, tapi tetap bisa dikomentari dan dinilai.
Bahkan kejujuran pun, di ruang ini, bisa jadi performa. Kita “tampil rapuh” dengan caption yang cerdas. Kita “curhat” dengan tone sarkas yang terukur. Kita menampilkan lelah, tapi tetap estetik.
Dalam dramaturgi digital, semua emosi bisa menjadi materi performatif, semua ekspresi bisa diolah agar tetap sesuai dengan karakter yang kita bangun, entah itu versi realis, ironis, atau tragis yang estetik.
Alih-alih melahirkan keotentikan, fitur-fitur semi-privat seperti Close Friends justru berisiko menciptakan lapisan identitas digital yang makin berlapis-lapis.
Kita bukan lagi satu tokoh dengan dua sisi, tapi banyak versi dari satu diri, masing-masing tampil di panggung yang berbeda, tapi tetap dalam logika pertunjukan.
Dan saat semua ruang menjadi panggung, muncul pertanyaan mendalam: apakah kita masih tahu seperti apa kita sebenarnya, ketika tidak sedang tampil untuk siapa-siapa?
Performa Keintiman: Ketulusan Atau Strategi?
Di dunia yang serba bisa dibagikan, bahkan keintiman tak luput dari kemungkinan dipertontonkan.
Close Friends, yang awalnya diposisikan sebagai ruang kejujuran dan kenyamanan, kini bertransformasi menjadi ruang pertunjukan mikro, tempat di mana kerentanan bisa tampil, tapi tetap dalam bingkai yang disengaja.
Kita bisa “curhat”, tapi dengan caption yang witty. Kita bisa menunjukkan kelelahan, tapi tetap dengan tone visual yang pas. Kita bisa mengunggah isi kepala yang gelap, tetapi dalam format yang relatable dan tetap mengundang like dari segelintir teman terpilih.
Apakah ini bentuk ekspresi yang tulus? Atau strategi sosial untuk menjaga citra “autentik” versi versi yang dikurasi? Di balik kesan santai dan tidak formal, banyak dari konten Close Friends justru mengandung niat tertentu.
Bukan niat buruk, tapi tetap niat yang penuh perhitungan. Siapa yang boleh melihat unggahan itu? Apa reaksi yang ingin dibangun? Apakah kita berharap orang-orang mengirim respon? Atau kita ingin mereka diam dan mengamati, agar tahu bahwa kita “tidak sekuat kelihatannya”?
Dalam kondisi ini, keintiman menjadi performa baru. Kita tidak lagi hanya memainkan peran untuk dilihat, tetapi untuk “didekati”. Kita ingin dianggap dekat, jujur, dan terbuka, tapi tetap dalam kendali. Ironisnya, justru di ruang yang paling sempit itulah, kontrol terhadap kesan menjadi lebih ketat.
Karena kita tahu, penonton yang sedikit itu lebih berarti. Penonton di Close Friends bukan massa anonim, mereka adalah orang-orang yang kita kenal, yang opini dan responsnya punya bobot secara emosional dan sosial.
Kita pun mulai terbiasa: curhat yang dibagikan bukan hanya soal pelampiasan, tapi bisa jadi cara membentuk bonding. Unggahan raw bukan hanya tentang jujur, tapi juga tentang membangun persona “berani tampil apa adanya.”
Bahkan luka, lelah, dan kekacauan pun bisa dikemas, dalam gaya bahasa yang populer, dalam estetika yang menarik, dalam timing yang tepat.
Di titik ini, kita perlu bertanya: apakah keintiman yang dibagikan secara sengaja masih bisa disebut kejujuran? Atau ia hanyalah cara baru untuk membangun citra, hanya saja dengan sentuhan emosi yang lebih halus dan tampak manusiawi?
Konsekuensi Sosial dan Emosional
Saat ruang yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru berubah menjadi panggung kecil yang tetap menuntut performa, ada dampak yang muncul, baik secara sosial maupun emosional.
Close Friends yang awalnya dianggap sebagai ruang kejujuran, perlahan membentuk pola interaksi dan persepsi diri yang baru: lebih tersembunyi, lebih eksklusif, namun tidak kalah menuntut.
Salah satu konsekuensinya adalah munculnya tekanan untuk tampil “autentik dengan cara yang benar”. Keautentikan pun kini punya formatnya sendiri. Harus terlihat jujur, tapi tidak berlebihan.
Harus personal, tapi tetap bisa dikonsumsi. Harus berani curhat, tapi tetap dikemas dalam gaya yang bisa diterima secara sosial.
Hal ini menciptakan standar baru yang lebih licin dan sulit dibaca, karena kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang memenuhi ekspektasi tersebut.
Di sisi lain, ruang semi-privat seperti Close Friends menciptakan dinamika inclusion dan exclusion. Siapa yang masuk dalam daftar “teman dekat” dan siapa yang tidak, menjadi isu sosial tersendiri.
Rasa FOMO (fear of missing out) muncul bukan hanya karena tidak melihat unggahan seseorang, tapi juga karena tidak dianggap cukup dekat untuk melihatnya.
Hubungan digital yang seharusnya cair justru menciptakan garis batas yang lebih tipis tapi tajam. Bahkan rasa cemburu atau kecewa bisa muncul hanya karena “tidak dimasukkan” dalam circle itu.
Lebih jauh lagi, bagi si pembuat konten, terjebak dalam performa keintiman bisa melahirkan kelelahan sosial. Ketika bahkan ekspresi paling pribadi pun harus dikemas dan dikontrol, ruang untuk menjadi diri sendiri perlahan menghilang.
Kita terus-menerus bermain dalam berbagai versi diri, tanpa benar-benar tahu versi mana yang paling kita rasakan sebagai “diri sendiri”. Efek psikologisnya tidak selalu terasa langsung, tapi menumpuk.
Kita mulai merasa cemas saat tidak mengunggah. Kita merasa bersalah kalau tidak membalas reaksi di Close Friends. Kita merasa tidak cukup “menarik secara emosional” jika unggahan personal kita tidak memicu respons. Semua ini membentuk pola hubungan yang rumit antara identitas digital dan kesehatan emosional.
Dan di balik itu semua, ada pertanyaan yang semakin lama semakin sulit dijawab: apakah kita benar-benar sedang terhubung, atau hanya sedang mempertahankan ilusi keintiman yang bisa ditonton?
Perlu Ruang yang Benar-benar Sunyi
Di tengah segala pertunjukan digital, kita lupa bahwa manusia tidak diciptakan untuk terus-menerus tampil. Bahkan aktor terbaik pun butuh ruang ganti, butuh duduk sendiri di ruang hening, tanpa sorot lampu, tanpa tepuk tangan, tanpa ekspektasi.
Begitu pula dengan kita, yang kini, tanpa sadar, memainkan begitu banyak versi diri dihadapan begitu banyak audiens, bahkan di ruang yang katanya paling personal.
Close Friends bisa jadi memberikan ilusi ruang aman, tapi ia tetap ruang yang terhubung. Masih ada mata yang melihat, masih ada ekspektasi yang bermain, masih ada tekanan untuk “menjadi sesuatu”, meskipun lebih halus.
Maka yang benar-benar kita butuhkan mungkin bukan hanya ruang kecil yang terseleksi, tetapi ruang yang benar-benar sunyi, yang tidak bisa diakses siapa pun, bahkan algoritma.
Di era media sosial, diam adalah bentuk keberanian. Tidak mengunggah bukan berarti tidak punya cerita. Tidak membagikan bukan berarti tidak penting. Justru kadang, kejujuran paling dalam hanya bisa tumbuh di ruang yang tidak perlu disaksikan.
Ketika kita berhenti tampil, mungkin di sanalah kita benar-benar hadir sebagai diri sendiri. Menolak tampil bukan berarti menghilang.
Kadang, itu adalah upaya paling tulus untuk kembali mendengarkan diri, tanpa suara luar, tanpa panggung. Karena di dunia di mana semuanya bisa dipertontonkan, menyimpan sesuatu untuk diri sendiri bisa jadi tindakan yang paling radikal. (Red)
*) Faiz Rafdillah, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta