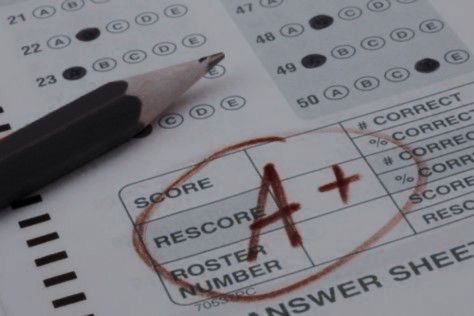Politisi Seleb, Demokrasi Jadi Konten: Rakyat Cuma Penonton
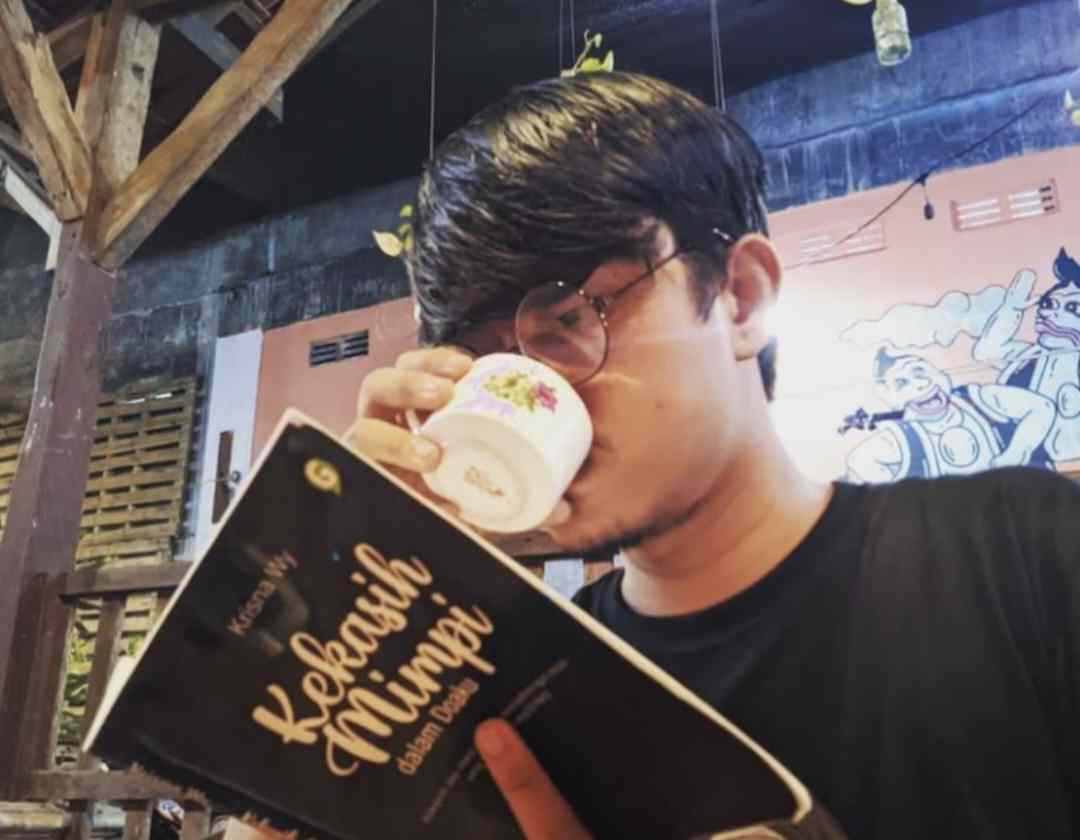

Oleh: Krisna Wahyu Yanuar*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Dulu, para politisi dikenal berkat pemikirannya. Sekarang, mereka terkenal karena aksi-aksi menarik. Dulu, masyarakat memilih berdasarkan visi yang ada. Saat ini, mereka memilih berdasarkan kesan yang dirasakan.
Kita hidup di zaman di mana demokrasi yang tidak lagi ditentukan dalam debat, tetapi di layar ponsel. Saat konten lebih diprioritaskan dibandingkan konstitusi.
Berdasarkan Tren Konten Politisi Indonesia 2024, studi yang dilakukan oleh Lembaga Media Watch merilis bahwa 78% isi media sosial para politisi terfokus pada kegiatan sehari-hari seperti makan, berwisata, dan hobi.
Hanya 12% yang mengupas tentang kebijakan atau program kerja, sedangkan 10% sisanya, dalam bentuk kampanye simbolis (bantuan sosial seremonial).
Di mana politisi lebih fokus membangun citra di Instagram daripada merancang rencana pembangunan. Demokrasi kini telah bertransformasi menjadi tontonan, dan sayangnya—masyarakat hanya berperan sebagai penonton.
Politisi atau Selebgram?
Mungkin kita sudah tidak asing dengan politisi yang suka membuat vlog di dapur, mereview makanan kaki lima, atau menari di TikTok saat kampanye. Dibalut senyum menawan dan filter terkini, mereka muncul seperti bintang—bukan pemimpin.
Bukan berarti politisi tidak boleh dekat dengan rakyat, tetapi jika semua cara komunikasi hanya mengedepankan citra, kita perlu bertanya: bagaimana dengan substansinya?
Menjadi terkenal bukanlah masalah. Namun, kepopuleran saat ini lebih banyak ditentukan oleh kualitas gagasan, melainkan oleh algoritma media sosial.
Mereka yang lucu, unik, dramatis, atau sensasional-lah yang muncul di beranda. Bukan yang punya rencana jelas untuk mengurangi angka kemiskinan atau memperbaiki sistem pendidikan.
Ini bukan tuduhan sembarangan. Cobalah perhatikan bagaimana kampanye politik saat ini lebih menyerupai promosi produk kecantikan.
Menggunakan kamera profesional, caption penuh bahasa indah, komentar yang diawasi, dan dukungan dari influencer. Semua itu demi satu tujuan: membentuk pandangan masyarakat.
Konten Mengalahkan Konteks
Masalah utama ketika politik berubah menjadi konten adalah hilangnya konteks. Dalam video selama 30 detik, tidak ada kesempatan untuk menjelaskan kompleksitas masalah energi nasional, apalagi rencana jangka panjang untuk mengurangi utang negara.
Namun, itulah yang terjadi: gagasan besar dikemas menjadi klip singkat yang mudah viral. Contohnya seorang Dedi Mulyadi di media sosial telah menimbulkan julukan “gubernur konten” dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.
Dedi menanggapi julukan tersebut dengan menyatakan bahwa aktivitasnya di media sosial membantu menurunkan anggaran iklan Pemprov Jabar dari Rp50 miliar menjadi Rp3 miliar, sambil tetap menjaga visibilitas program pemerintah.
Kita terbuai oleh narasi “dekat dengan rakyat”, namun melupakan untuk bertanya: apa sebenarnya yang ia perjuangkan? Demokrasi telah berubah menjadi tayangan realitas, dan masyarakat hanya sibuk menekan tombol ‘like’ tanpa menyadari bahwa mereka sedang disajikan ilusi politik.
Rakyat Disulap Jadi Penonton
Hal yang paling menyedihkan dari perubahan ini adalah semakin pasifnya masyarakat. Alih-alih menjadi subjek dalam politik, kita malah diposisikan sebagai penonton.
Tugas kita hanya melihat, memberikan komentar, lalu memilih berdasarkan kesan visual, bukan dari pemikiran kritis.
Seharusnya, demokrasi mengharuskan partisipasi aktif dari rakyat. Tidak hanya di kotak suara setiap lima tahun, tetapi juga dalam mengawasi, menuntut pertanggungjawaban, serta berdialog dengan para pembuat kebijakan.
Namun, bagaimana lagi partisipasi itu dapat berkembang jika saluran komunikasi dipenuhi dengan konten-konten yang dangkal?
Politisi mengunggah video saat makan nasi bungkus, sementara rakyat asyik mengomentari cara makannya.
Politisi membuat konten tentang membersihkan sungai, sedangkan rakyat hanya terpesona tanpa bertanya: di mana anggaran pengelolaan lingkungan yang transparan?
Politik yang seharusnya menjadi alat untuk perubahan, kini malah menjadi sarana hiburan.
Media Sosial dan Ilusi Kedekatan
Media sosial memiliki pengaruh yang luar biasa. Ia menciptakan ilusi kedekatan. Melihat politisi menyapa dari balik layar ponsel membuat kita merasa diperhatikan.
Namun, itu semua hanya ilusi. Yang kita saksikan adalah versi terbaik dari mereka, versi yang telah disunting, versi yang ingin mereka tunjukkan.
Hubungan antara masyarakat dan wakilnya seharusnya dibangun berdasarkan tanggung jawab, bukan hanya untuk meningkatkan engagement rate.
Namun, dengan algoritma yang seringkali mengedepankan sensasi, para politisi terdorong untuk terus berfokus pada popularitas daripada kinerja nyata.
Lebih buruk lagi, media sosial dapat menekan suara kritik. Algoritma cenderung hanya menunjukkan hal-hal yang kita suka.
Jika kita menyukai seorang politisi, kita hanya akan dikelilingi oleh konten yang memujinya. Suara kontra akan terabaikan. Narasi yang berbeda akan hilang. Kita terperangkap dalam ruang echo chamber yang membuat kita percaya bahwa semuanya baik-baik saja.
Demokrasi Bukan Konten: Ia Butuh Isi
Demokrasi adalah sistem yang memerlukan diskusi yang mendalam—perdebatan ide, perbedaan pandangan, dan argumen yang logis. Ketika demokrasi disederhanakan menjadi konten viral, substansi ide akan tergerus.
Kita tidak lagi membahas rencana pembangunan untuk lima tahun ke depan, tetapi lebih sibuk menilai siapa yang lebih luwes saat berjoget.
Ini bukanlah seruan untuk menolak media sosial. Platform digital memiliki potensi besar untuk menjembatani wakil dan masyarakat.
Namun, jika penggunaannya hanya ditujukan untuk menarik perhatian tanpa membangun transparansi dan dialog yang berarti, maka ia bisa menjadi masalah.
Kita memerlukan politisi yang mampu membuat konten, tetapi kita juga harus memastikan bahwa konten tersebut memiliki nilai substansial.
Bukan sekadar tentang ‘branding’, melainkan juga ‘brain’. Kita perlu menciptakan budaya politik yang menghargai argumen daripada sekadar tampilan.
Pendidikan Politik: Masih Jauh di Belakang
Salah satu penyebab maraknya politik yang berfokus pada pencitraan adalah kurangnya pendidikan politik di kalangan masyarakat.
Banyak orang belum terbiasa dalam menganalisis program, mengevaluasi janji kampanye, atau meminta pertanggungjawaban.
Akibatnya, citra menjadi satu-satunya panduan. Kita harus menyadari bahwa sistem pendidikan kita belum memberikan cukup tempat untuk literasi politik.
Diskusi mengenai konstitusi, sistem pemerintahan, dan hak-hak warga negara masih dianggap sebagai tambahan, bukan menjadi inti. Akibatnya, saat menghadapi banjir konten politik di media sosial, masyarakat tidak memiliki alat kritis untuk menilai.
Solusinya bukan dengan melarang politisi membuat konten, tetapi dengan memperkuat kemampuan publik dalam menilai isi konten tersebut.
Pendidikan politik harus menjadi agenda yang serius bagi pemerintah. Ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga melalui komunitas, media massa, dan saluran informal lainnya.
Konten Politik Seharusnya Mencerahkan
Ada juga politisi yang berhasil memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan ide-ide mereka.
Mereka membuat konten yang mendidik, membahas isu-isu kebijakan publik, menjelaskan proses legislasi, atau membuka sesi tanya-jawab secara terbuka. Ini sangat patut untuk dipuji.
Namun, sayangnya, mereka tidak mampu bersaing dalam hal viralitas. Mereka kalah dari politisi yang membuat konten yang menghibur, tantangan konyol, atau drama pribadi.
Sekali lagi, algoritma tidak memperhatikan kedalaman. Jika masyarakat tidak dilatih untuk mencari sesuatu yang lebih bermakna, maka hal-hal yang lucu akan selalu lebih unggul.
Ini adalah tantangan besar bagi kita: membangun sistem informasi politik yang seimbang. Yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkaya pengetahuan. Yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga mempengaruhi hati dan pikiran.
Kembalikan Politik ke Tempatnya
Politik sebenarnya bukanlah panggung pertunjukan. Ia adalah ruang serius yang mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Oleh karena itu, politisi bukanlah selebriti.
Mereka adalah pelayan publik, pembuat kebijakan, dan pengelola negara. Saat para politisi lebih fokus mengejar ketenaran, pelayanan publik pun akan terabaikan.
Kita perlu kembali menuntut agar politisi bersikap sebagai negarawan. Bukan hanya melalui janji, tetapi juga melalui jejak rekam dan komitmen mereka.
Kita harus berani menyatakan bahwa tidak semua yang viral layak dijadikan pilihan. Kita harus menyadari bahwa meskipun gaya mungkin menarik, gagasan tetaplah yang paling utama. (Red)
*) Krisna Wahyu Yanuar, Editor Urupedia.id dan Mahasiswa Sosiologi Agama UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung