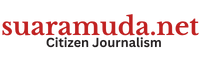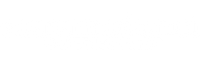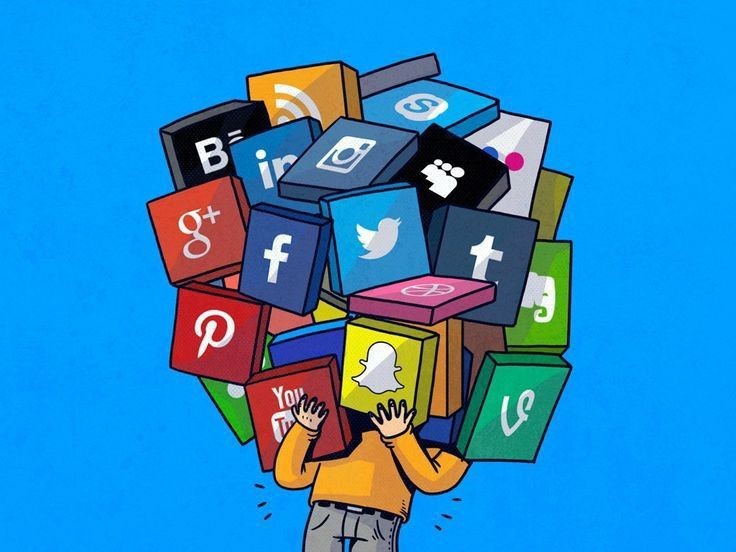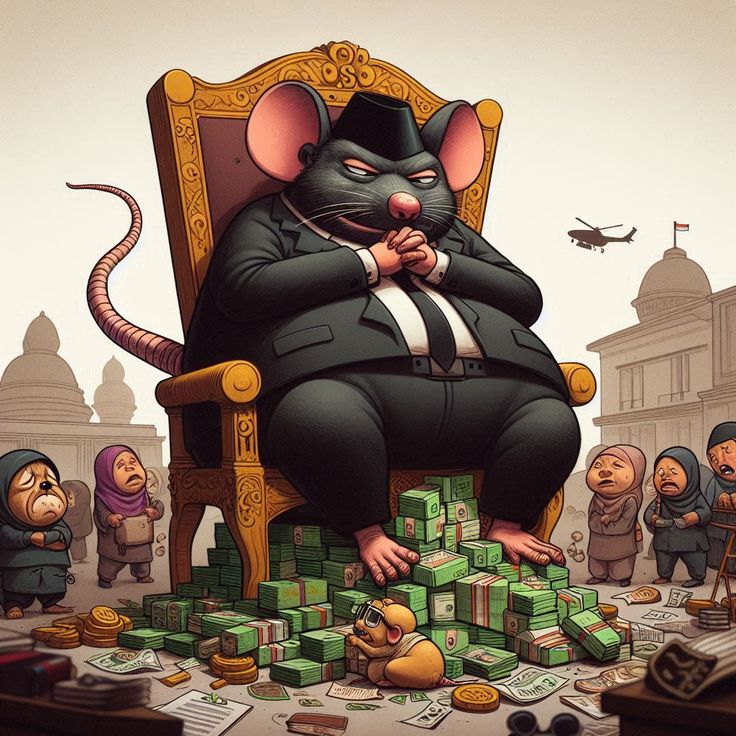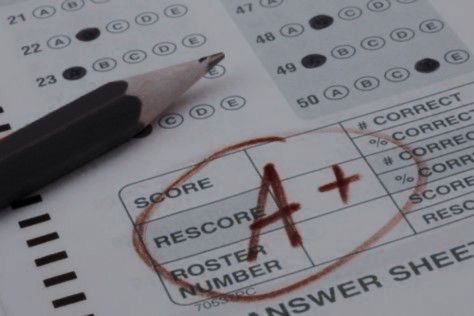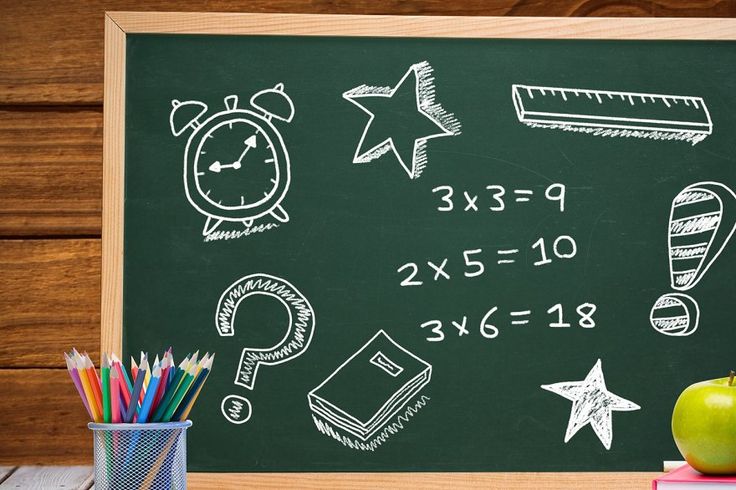Menjemput Kedaulatan Tambang Aceh di Era PP 39 Tahun 2025


Oleh: Delky Nofrizal Qutni*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Kekhususan Aceh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), lahir dari semangat rekonsiliasi dan keadilan historis.
UUPA bukan sekadar instrumen politik, tetapi manifestasi hak rakyat Aceh untuk mengatur diri sendiri, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.
Namun setelah hampir dua dekade berjalan, kekhususan itu tampak semakin kabur, terutama di sektor pertambangan rakyat yang justru menjadi sumber kehidupan masyarakat pedesaan di banyak kabupaten.
Hingga kini Aceh belum memiliki Qanun khusus tentang Pertambangan Rakyat dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bagi BUMD.
Akibat kekosongan hukum ini, pemerintah Aceh mau tak mau terpaksa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri ESDM, yang sejatinya disusun untuk sistem nasional, bukan sistem khusus Aceh.
Kondisi ini menempatkan Aceh dalam posisi dilematis, di satu sisi memiliki hak istimewa, namun di sisi lain masih tergantung pada regulasi pusat.
Instruksi Gubernur Aceh yang meminta kabupaten/kota segera mengusulkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sejatinya langkah visioner.
Namun tanpa didukung data geologi, dokumen teknis, dan peta administrasi yang sahih, wacana itu berpotensi menjadi simulakra kebijakan yang menampakkan citra keberpihakan pada rakyat, namun tanpa substansi nyata dalam implementasi.
Jika pemerintah Aceh ingin menegakkan marwah kekhususannya, maka pembenahan dimulai dari aspek regulasi dan teknis. WPR bukan sekadar dokumen peta, tetapi bentuk konkret dari kedaulatan rakyat atas tanah dan mineral yang selama ini mereka gali tanpa perlindungan hukum.
Regulasi, Kewenangan, dan Bayang-Bayang Sentralisasi
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas PP 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Regulasi ini membawa misi positif dengan menertibkan tata kelola, mendorong hilirisasi, serta memberikan prioritas WIUP dan WIUPK kepada koperasi, ormas keagamaan, BUMD, dan UMKM.
Namun dalam konteks Aceh, penerapan pasal-pasalnya tidak bisa dilakukan secara mentah tanpa menabrak prinsip lex specialis yang dimiliki UUPA.
Dalam struktur hukum nasional, UUPA adalah lex specialis yang mengesampingkan aturan umum selama menyangkut kekhususan Aceh.
Di sektor pertambangan, Pasal 156 hingga 160 UUPA secara eksplisit memberi kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk menetapkan wilayah pertambangan (WP), termasuk WPR, dan menerbitkan izin pertambangan rakyat (IPR).
Ketentuan ini diperkuat oleh PP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Aceh, yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral di darat berada dalam kewenangan Pemerintah Aceh, sepanjang luas wilayahnya tidak melebihi 5.000 hektare.
Artinya, untuk WPR atau WIUP dengan luas ≤5.000 hektare, Aceh memiliki hak penuh untuk menetapkannya secara mandiri tanpa menunggu persetujuan formal dari Menteri ESDM.
Peran kementerian hanya sebatas fasilitatif dan koordinatif dalam sistem nasional. Dengan kekhususan ini, Gubernur Aceh sebenarnya dapat mengeluarkan keputusan penetapan WPR yang diintegrasikan ke dalam basis data nasional sebagai bentuk harmonisasi administratif, bukan subordinasi hukum.
Sayangnya, kekhususan ini nyaris tak dioptimalkan. Banyak pejabat teknis di tingkat provinsi dan kabupaten yang masih berasumsi bahwa seluruh keputusan harus mendapat restu pusat, padahal secara hukum Aceh punya otonomi khusus yang diakui oleh Pemerintah Pusat.
Di sinilah letak persoalan mendasarnya, Aceh kehilangan keberanian politik hukum untuk menegakkan kekhususan yang dijamin undang-undang.
Jika pemerintah Aceh menunggu terus instruksi dari kementerian, maka kedaulatan pengelolaan tambang rakyat akan terus tertunda. Rakyat tetap menambang tanpa izin, lingkungan tetap rusak, dan potensi pajak serta retribusi daerah terus hilang.
Sementara itu, perusahaan-perusahaan besar dengan izin resmi akan leluasa menguasai lahan yang seharusnya menjadi wilayah pertambangan rakyat.
Secara filosofis, kekhususan Aceh bukanlah ruang untuk berjarak dari negara, melainkan mekanisme untuk menyesuaikan kebijakan nasional dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat Aceh.
Dalam konteks pertambangan, kekhususan itu seharusnya menjadi jalan tengah antara efisiensi regulasi nasional dan kearifan lokal berbasis partisipasi rakyat.
Oleh karena itu, Qanun Pertambangan Rakyat Aceh harus segera disusun sebagai bentuk aktualisasi kekhususan tersebut. Qanun ini perlu menetapkan tata cara penetapan WPR, mekanisme pemberian IPR, dan kemitraan antara BUMD, koperasi, serta universitas lokal.
Dokumen pengelolaan WPR disahkan oleh Gubernur Aceh, sementara pengakuan dari Menteri ESDM hanya bersifat formal notification untuk integrasi data nasional.
Langkah ini tidak bertentangan dengan PP 39 tahun 2025, melainkan menempatkan Aceh sebagai mitra otonom dalam sistem tata kelola sumber daya nasional. Inilah bentuk asymmetric decentralization yang sesungguhnya, berbeda tapi tetap terintegrasi.
Selain aspek regulasi, pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas teknis. Banyak daerah penghasil emas di Aceh seperti Aceh Selatan, Aceh Barat Nagan Raya, Pidie, dan Aceh Jaya belum memiliki peta geologi dan data mineralisasi untuk penetapan WPR.
Padahal, tanpa data tersebut, penetapan WPR akan selalu dipandang lemah oleh pemerintah pusat. Di sinilah peran penting universitas dan asosiasi penambang rakyat untuk berkolaborasi mendampingi penyusunan dokumen teknis dan studi kelayakan.
Sementara itu, BUMD kabupaten di Aceh juga harus mengambil peran nyata sebagai pengelola WIUP dan mitra koperasi rakyat.
Dengan dukungan teknologi pengolahan emas ramah lingkungan seperti sistem gravitasi dan metode leaching dengan reagen ramah lingkungan misalkan Inichem Dressin Agent (IDA) atau Jinchan sebagai pengganti sianida(Cn), maka Aceh dapat menjadi model pengelolaan tambang rakyat berkelanjutan di Indonesia.
Namun semua itu hanya mungkin jika ada keberanian politik dan konsistensi birokrasi. Pemerintah Aceh tidak boleh sekadar menjadi pelaksana kebijakan pusat. Ia harus berdiri sebagai pelaku utama yang menafsirkan regulasi nasional dalam bingkai kekhususan UUPA.
Karena pada akhirnya, marwah otonomi tidak diukur dari banyaknya peraturan yang dibuat, tetapi dari seberapa besar kebijakan itu mampu mengubah nasib rakyat.
Mengembalikan Arti Kekhususan
Menegakkan kekhususan Aceh dalam bayang-bayang PP 39 tahum 2025 bukanlah perlawanan, melainkan penegasan identitas hukum dan politik yang telah dijamin undang-undang.
Otonomi khusus tidak akan berarti apa-apa jika Aceh sendiri tidak berani menggunakan kewenangan yang dimilikinya.
Jika wilayah tambang seluas 5.000 hektare saja masih menunggu tanda tangan kementerian, maka kekhususan tinggal nama.
Sebaliknya, jika pemerintah Aceh mampu menggunakan kewenangan itu dengan cerdas, transparan, dan terintegrasi dengan sistem nasional, maka Aceh bukan hanya menjadi contoh keberhasilan otonomi asimetris, tetapi juga pionir keadilan sumber daya di Indonesia.
Kekhususan sejati bukan soal privilese, tetapi tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan bahwa tanah dan mineral Aceh benar-benar menjadi milik rakyat Aceh. (Red)