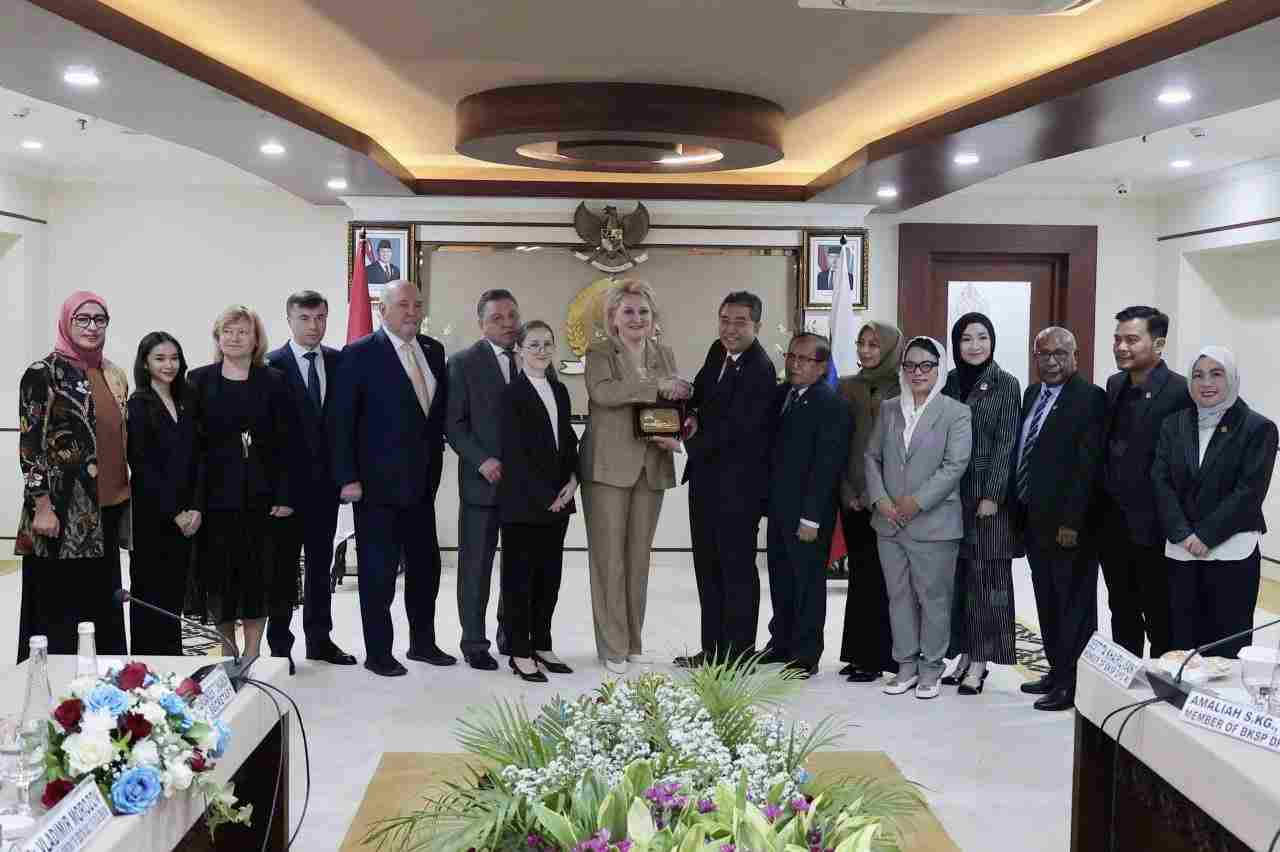Aceh Harus Menemukan Jalan Tengah, antara Hukum dan Perut Rakyat


SUARAMUDA.NET, BANDA ACEH — Pemerhati intelijen, Sri Radjasa, MBA, menilai kebijakan Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) untuk menghentikan seluruh aktivitas tambang ilegal merupakan langkah strategis dan berani, namun belum diikuti dengan strategi transisi yang matang bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor tambang rakyat.
Ia menegaskan, dalam konteks keamanan sosial dan ekonomi, keputusan itu seharusnya tidak berhenti pada penegakan hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan solusi legalisasi dan pembinaan agar tidak menimbulkan gejolak sosial baru.
Menurut Sri Radjasa, kebijakan yang dilatarbelakangi keinginan mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi kerusakan lingkungan adalah langkah yang tepat secara hukum dan ekologis.
Namun, di sisi lain, penghentian tambang ilegal tanpa adanya mekanisme transisi yang jelas justru memunculkan dampak sosial yang signifikan.
Berdasarkan laporan pemantauan lapangan di sejumlah kabupaten seperti Aceh Selatan, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Pidie Jaya, ribuan penambang rakyat kini terhenti aktivitasnya.
Kondisi ini memicu peningkatan pengangguran, penurunan daya beli, hingga munculnya potensi ketegangan sosial di daerah-daerah yang perekonomiannya bergantung pada tambang rakyat.
“Mereka bukan kriminal, mereka hanya belum diberi jalur yang legal untuk bekerja. Jika tidak segera ada solusi, maka yang terjadi bukan ketertiban, melainkan keresahan,” ujarnya, Minggu 5 Oktober 2025.
Kata Sri Radjasa, kebijakan yang bersifat represif tanpa dibarengi pendekatan pemberdayaan berpotensi menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia menilai bahwa penertiban tambang ilegal memang menunjukkan ketegasan pemerintah, tetapi ketegasan itu harus diimbangi dengan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
“Kebijakan seperti ini bisa menjadi bumerang jika tidak diikuti dengan kebijakan transisi. Pemerintah tidak boleh berhenti di sisi hukum, tapi juga harus hadir di sisi kemanusiaan,” katanya.
Dia mencontohkan keberhasilan beberapa daerah di Kalimantan Barat seperti Sintang dan Kapuas Hulu yang mampu menata tambang rakyat secara legal tanpa menimbulkan konflik sosial.
Pemerintah daerah di sana menggandeng Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) untuk mendampingi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan memberikan pelatihan teknologi pengolahan emas tanpa merkuri.
“Model seperti itu harus ditiru Aceh. Mereka tidak menutup tambang, tapi menatanya dengan pendekatan partisipatif. Hasilnya, lingkungan pulih, PAD meningkat, dan masyarakat merasa dilibatkan,” ujarnya.
Sri Radjasa menyoroti bahwa hingga kini Aceh belum memiliki satu pun WPR yang ditetapkan secara resmi, meski payung hukumnya sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba serta Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020.
Padahal, data Dinas ESDM Aceh menunjukkan lebih dari 3.000 penambang rakyat masih beroperasi tanpa izin, dengan perkiraan cadangan emas mencapai lebih dari 20 ton.
“Kita menghadapi situasi ironis, sumber daya besar dibiarkan tanpa tata kelola, sementara rakyat yang hidup dari situ justru dikriminalisasi karena ketiadaan payung hukum,” katanya.
Ia mendorong Pemerintah Aceh segera menyusun Qanun Pertambangan Rakyat Aceh sebagai solusi struktural untuk menata tambang rakyat. Menurutnya, qanun itu bisa menjadi jalan tengah antara kepentingan hukum, lingkungan, dan kesejahteraan.
“Qanun ini penting untuk melahirkan mekanisme legal yang memungkinkan rakyat tetap bekerja dengan aman dan ramah lingkungan. Tanpa itu, Aceh akan terus berputar dalam lingkaran tambang ilegal, penindakan, dan kemiskinan,” ujarnya.
Ia juga menilai keterlibatan organisasi Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) sangat penting karena lembaga tersebut telah berpengalaman dalam pendampingan teknis dan sosial di banyak daerah di Indonesia.
Sri Radjasa menilai rencana pembangunan laboratorium dan pusat pelatihan pengolahan emas ramah lingkungan yang pernah didiskusikannya dengan DPC APRI Aceh Selatan dapat dijadikan sebagai langkah progresif.
Ia menilai fasilitas itu bisa menjadi pilot project bagi Aceh dalam membangun sistem tambang rakyat yang legal dan berkelanjutan.
“Aceh Selatan misalkan, bisa dijadikan roll model untuk itu. Teknologi alternatif seperti leaching IDA dan sistem gravitasi terbukti lebih aman dan bebas merkuri. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Minamata yang menargetkan bebas merkuri pada 2025,” katanya.
Sri Radjasa juga mengingatkan bahwa waktu menuju target bebas merkuri tinggal dua tahun. Jika pemerintah tidak segera menyediakan teknologi pengganti, masyarakat pasti akan kembali menggunakan merkuri secara sembunyi-sembunyi.
Karena itu, ia mengusulkan agar Pemerintah Aceh meluncurkan program “Aceh Bebas Merkuri 2025” yang mencakup edukasi bahaya merkuri, penerapan teknologi alternatif, serta pemberian insentif bagi kelompok penambang yang beralih ke metode ramah lingkungan.
“Pendekatan edukatif lebih efektif dari sekadar larangan. Di banyak negara penandatangan Konvensi Minamata, hasilnya terbukti,” ujarnya.
Sebagai pemerhati intelijen, Sri Radjasa juga menekankan pentingnya pembentukan tim terpadu pengelolaan pertambangan rakyat Aceh yang melibatkan unsur pemerintah, ESDM, lingkungan hidup, akademisi, APRI, dan tokoh masyarakat.
Menurutnya, pendekatan multidisipliner menjadi kunci agar kebijakan tambang rakyat tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.
“Tambang rakyat adalah ekosistem sosial. Ia tidak bisa dikelola dengan logika pidana semata,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Sri Radjasa menilai kebijakan Gubernur Mualem menghentikan tambang ilegal tetap patut diapresiasi karena berpihak pada penegakan hukum dan kelestarian alam. Namun, katanya, hukum tanpa keadilan sosial akan kehilangan makna.
“Negara harus menjadi jembatan antara hukum dan perut rakyat, bukan tembok di antara keduanya. Penertiban tambang ilegal memang perlu, tapi yang lebih penting adalah memberi rakyat jalan yang legal untuk hidup,” pungkas penulis buku berjudul “Intel Juga Manusia” tersebut. (Red)