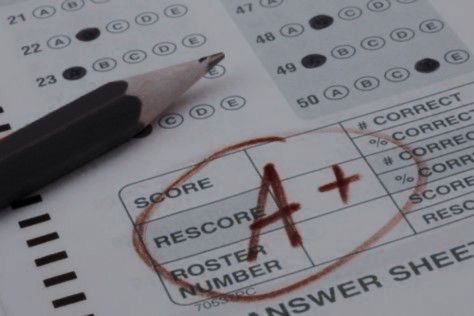Tindakan Diskriminasi Terhadap Orang Tionghoa di Hindia Belanda


Oleh: Nouval Murzita *)
SUARAMUDA, SEMARANG – Pada tahun 1900, jumlah orang Tionghoa yang tinggal di Hindia Belanda telah mencapai 537,316 jiwa, lebih dari 277,000 jiwa di antaranya bertempat tinggal di pulau Jawa dan Madura.
Kebanyakan kaum Tionghoa di Hindia Belanda adalah rakyat dari golongan kelas bawahan.
Akibat penindasan dan kemiskinan yang mereka hadapi di kampung halaman membuatnya terpaksa pergi ke luar negeri bekerja mencari nafkah untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik.
Tetapi saat tiba di Hindia Belanda pemerintah kolonial Belanda yang berkuasa juga menghina, menindas dan menghisap para perantau tersebut.
Orang Tionghoa memulai usahanya dengan darah dan air mata, mereka dapat bertahan di dalam perjuangan untuk mencari nafkah yang sangat berat ini karena menyadari bahwa nasib keluarga dikampung halaman sangat erat berkaitan dengan status ekonomi mereka di luar negeri.
Menjalani kehidupan di luar negeri yang penuh dengan pahit getir dalam mencari nafkah membuat para perantau Tionghoa memiliki perasaan yang mendalam terhadap tanah air Tiongkok.
Mereka, walau sudah beberapa generasi menetap di Hindia Belanda tetapi di dalam hati kecilnya tetap menginginkan memiliki tanah air yang kuat, yang bisa setiap saat membantu jika mereka menghadapi kesulitan dan bisa menjaga agar tidak dipandang rendah atau dengan mudah dianiaya oleh bangsa lain.
Nasionalisme Tiongkok
Pergerakan nasionalisme Tiongkok di Hindia Belanda pertama kali berkembang di bawah kepemimpinan kaum Tionghoa Jawa.
Penindasan, perbudakan, dan eksploitasi yang dilakukan penguasa kolonial Belanda terhadap orang Tionghoa menjadi pemicu utama kebangkitan gerakan perlawanan yang dilakukan oleh mereka.
Sejak abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-20 pemerintah colonial Belanda membatasi kebebasan bergerak orang Tionghoa.
Menurut undang-undang yang mengatur masalah izin tinggal bagi orang asing dan peraturan kependudukan, orang Tionghoa hanya diizinkan tinggal di wilayah khusus orang Tionghoa (pecinan atau kampung Tionghoa).
Pada daerah-daerah tertentu khususnya di pulau Jawa orang Tionghoa tidak diizinkan bergerak atau pergi ke lokasi lain diluar tempat mereka bermukim jika belum memperoleh izin dari penguasa setempat.
Pada malam hari mulai pukul 6.30 sampai dengan pukul 5.30 pagi hari sebelum fajar menyingsing, setiap orang Tionghoa yang ingin pergi bepergian keluar rumah harus membawa obor atau lampu minyak sebagai penanda agar mudah untuk diawasi.
Peraturan seperti ini tidak saja membatasi hubungan sosial diantara orang Tionghoa dengan penduduk bumiputera tetapi juga membatasi aktifitas perdagangan orang Tionghoa sampai batas-batas tertentu, terutama pada saat pengangkutan barang-barang dagangan ke daerah pedalaman.
Selain membatasi perjalanan pada malam hari, saat siang hari pemerintah kolonial Belanda juga membatasi kebebasan orang Tionghoa untuk melakukan perjalanan.
Sebagai contoh jika ada orang Tionghoa yang ingin mengunjungi kerabat atau rekan sejawatnya yang tinggal di daerah lain maka dirinya harus mengajukan izin untuk melakukan perjalanan kepada pemerintah dan membawa surat izin untuk melakukan perjalanan yang dikeluarkan oleh kapiten atau letnan Tionghoa di wilayah tempat ia berdomisili.
Orang Tionghoa tersebut harus membawa kedua surat izin saat melakukan perjalanan menuju tempat yang dituju.
Saat mengurus surat izin orang Tionghoa tersebut harus menyebutkan nama tempat yang dituju, lama waktu perjalanan dan lama waktu tinggal di daerah tujuan.
Setelah tiba di tempat yang dituju, jika ia tidak kembali tepat pada waktu seperti yang sudah diajukan sebelumnya, maka yang bersangkutan harus melapor ke pemerintah daerah setempat dalam waktu 1×24 jam dan jika tidak melapor orang tersebut akan dikenai hukuman.
Setelah menyelesaikan urusannya di tempat tujuan pada saat ingin kembali ke daerah asal, orang tersebut harus mendapat surat jalan untuk kembali yang dikeluarkan oleh pemerintah dari daerah yang dikunjunginya.
Aturan Perjalanan Bagi Warga Tionghoa
Selain membatasi pergerakan orang Tionghoa, pemerintah Hindia Belanda juga mengeluarkan aturan pada beberapa kota di pulau Jawa seperti Solo, Jogjakarta, Malang dan Kediri tidak boleh dikunjungi oleh orang Tionghoa pendatang baru.
Aturan pembatasan perjalanan ini tidak hanya mempengaruhi aktivitas ekonomi orang Tionghoa tetapi juga membawa ketidaknyamanan pada hubungan sosial diantara kerabat dan rekan sejawat.
Izin perjalanan dan sistem permukiman (passenen wijkenstelsel) ini dicabut pada tahun 1918 karena merugikan importir dan eksportir Belanda yang dalam melakukan perdagangan bergantung kepada pedagang Tionghoa yang menjual barang-barang impor ke daerah pedalaman dan pedagang Tionghoa yang mengumpulkan hasil perkebunan rakyat yang akan di ekspor ke luar negeri.
Setelah dicabutnya aturan perjalanan dan sistem pemukiman yang diberlakukan kepada orang Tionghoa yang tinggal di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat dan lain-lainnya maka mereka yang sebelumnya hanya boleh tinggal di daerah pecinan dengan segera pergi ke daerah pedalaman untuk melakukan perdagangan dan usaha pertanian.
Korban Produk Hukum
Setelah Indonesia merdeka pada umumnya orang Tionghoa ini bekerja menjadi pedagang eceran, pedagang keliling, membuka usaha toko kelontong dan bertani di daerah pedesaan dan kota-kota kecil.
Mereka inilah yang kemudian menjadi korban pengusiran akibat diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1959.
Pemerintah kolonial Belanda juga mengeluarkan aturan yang ketat untuk membatasi orang Tionghoa asal Tiongkok yang ingin berkunjung ke wilayah Hindia Belanda.
Orang Tionghoa yang berasal dari Tiongkok jika ingin berlibur atau menetap di Hindia Belanda, harus mendapat jaminan dari orang Tionghoa atau Peranakan yang sudah menjadi penduduk tetap.
Para penjamin harus datang untuk menjemput orang asal Tiongkok tersebut ke kantor imigrasi pelabuhan.
Karena banyaknya pendatang baru yang tiba dari Tiongkok petugas imigrasi mewajibkan mereka untuk tinggal di fasilitas karantina selama satu atau dua malam.
Dalam proses karantina ini tanpa alasan yang jelas banyak diantara mereka sering dipukuli atau dimarahi oleh petugas imigrasi. Mereka juga diperas dengan dimintai uang pelicin agar proses karantina berjalan lancar.
Diskriminasi dalam Kependudukan
Dalam status kependudukan orang Tionghoa di Hindia Belanda mengalami berbagai diskriminasi.
Menurut peraturan yang dimuat dalam Staatsblad No.2.Jo.1. Pasal 131 Jo.61 Wet op de staats inrichting van Nederlands Indie atau Indische Staats regeling (IS) tahun 1855:
Penduduk Hindia Belanda dibagi-bagi menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama kelompok orang Eropa termasuk didalamnya orang-orang Indo Eropa. Yang kedua kelompok Vreemde Oosterlingen atau orang timur asing yang terdiri dari orang Tionghoa, arab dan asia lainnya. Yang ketiga kelompok inlander atau bumiputera.
Pada tahun 1906 pemerintah Hindia Belanda melakukan revisi konstitusi dengan menerbitkan Indische Staatsregeling (IS), yaitu undang-undang dasar yang mengatur tata negara dan pemerintahan Hindia Belanda.
Menurut Pasal 163 penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi tiga golongan dihadapan hukum, yaitu (1). Golongan I (golongan eropa), (2). Golongan II (golongan oriental atau timur asing, termasuk didalamnya orang India, Tionghoa dan negara-negara arab), (3). Golongan III (golongan rakyat bumiputera).
Dapat dilihat pada dua perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda status hukum orang Tionghoa dan penduduk bumiputera berada pada golongan sosial yang berbeda.
Ketiga golongan ini tunduk kepada sejumlah buku undang-undang yang berbeda dan diadili di pengadilan yang berbeda pula.
Dalam kehidupan keseharian pemerintah Hindia Belanda melakukan pemisahan terhadap ketiga golongan masyarakat ini, sebagai contoh dalam penggunaan transportasi kereta api, gerbong penumpang dibagi menjadi tiga kelas, orang Eropa, Amerika, dan Jepang menggunakan gerbong kelas satu dengan tempat duduk dan fasilitas sanitasi yang sangat baik.
Orang Tionghoa, Arab dan orang asia lainnya hanya dapat menggunakan gerbong kelas dua. Penduduk bumiputera hanya diperbolehkan duduk pada gerbong pada kelas tiga.
Diskriminasi Rasial
Diskriminasi dalam melihat warna kulit dan asal bangsa juga terjadi pada fasilitas umum lainnya seperti pada sinema dan tempat olahraga seperti stadion sepakbola.
Tempat duduk di sinema dan stadion sepakbola ditentukan berdasarkan golongan dalam masyarakat seperti diatur dalam pasal 163.
Kebijakan untuk membagi-bagi masyarakat dalam golongan ini mencerminkan kebijakan diskriminasi rasial penguasa kolonial Belanda dan merupakan satu bentuk pengewejantahan dari politik devide et impera atau politik adu domba.
Pembagian golongan berdasarkan suku bangsa ini sengaja dilakukan agar menimbulkan kecemburuan sosial dari penduduk bumiputera kepada bangsa asing khususnya kepada bangsa Tionghoa.
Kontradiksi pokok yang semakin meruncing akibat penindasan kejam yang dilakukan oleh penguasa kolonial terhadap penduduk bumiputera dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam periode tertentu dapat bermutasi dengan cara menimbulkan kebencian rasial yang dipropagandakan lewat sentimen identitas dan dibalut dengan perbedaan kelas sosial.
Sehingga, seolah-olah yang menjadi musuh utama kaum bumiputera adalah masyarakat Tionghoa bukan pemerintah kolonial Belanda.
Kebijakan diskriminasi rasial dalam bentuk yang berbeda-beda dilaksanakan oleh pemerintah kerajaan Belanda pada seluruh daerah koloni yang mereka kuasai seperti Hindia Belanda, Guinea Belanda (Ghana), Nugini Belanda (Papua), Benggala Belanda, Malaka Belanda, Suriname, Mauritius Belanda, koloni Tanjung (Afrika Selatan) dan lain-lainnya.
Di Hindia Belanda pemerintah kolonial melarang orang Tionghoa berbicara menggunakan bahasa Belanda dalam kehidupan sehari-harinya.
Orang Tionghoa dalam percakapan hanya diizinkan menggunakan bahasa melayu pasar, mandarin atau bahasa dialek suku Tionghoa.
Anak-anak orang Belanda sering dengan sembarangan memanggil orang Tionghoa dengan sebutan “babi”.
Mereka sering melakukan kekerasan fisik kepada orang Tionghoa dengan sesuka hati tanpa disertai alasan yang jelas. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang Belanda tidak pernah dikenai hukuman.
Diskriminasi di Bidang Pendidikan
Diskriminasi dalam bidang pendidikan juga terjadi. Pada umumnya, anak-anak orang Tionghoa dilarang untuk belajar di sekolah-sekolah Belanda.
Hanya terdapat sejumlah kecil anak-anak orang Tionghoa yang diizinkan untuk belajar di sekolah-sekolah milik Belanda dan mereka yang diizinkan tersebut berasal dari golongan atas masyarakat Tionghoa.
Atas arahan pemerintah kolonial Belanda sekolah-sekolah milik pemerintah yang dibuka untuk penduduk bumiputera juga menolak menerima anak-anak Tionghoa dengan alasan jumlah kursi yang tersedia tidak mencukupi.
Pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Kementerian Pendidikan. Beberapa orang pimpinan terkemuka masyarakat Tionghoa saat itu menulis dan menandatangani sebuah surat yang isinya meminta agar anak-anak orang Tionghoa dapat diizinkan masuk untuk belajar di sekolah-sekolah yang dibuka untuk anak-anak bumiputera.
Sayangnya, permintaan tersebut ditolak oleh pemerintah dengan alasan pendidikan bagi anak-anak orang Tionghoa tidak menjadi bagian dari program pemerintah untuk membuka sekolah-sekolah yang diperuntukan bagi anak-anak kaum bumiputera. (Red)
*) Nouval Murzita (林隆发), Pemerhati Sejarah Tionghoa Indonesia, Alumnus Zhejiang Normal University, Jinhua, Tiongkok