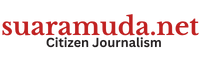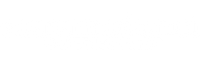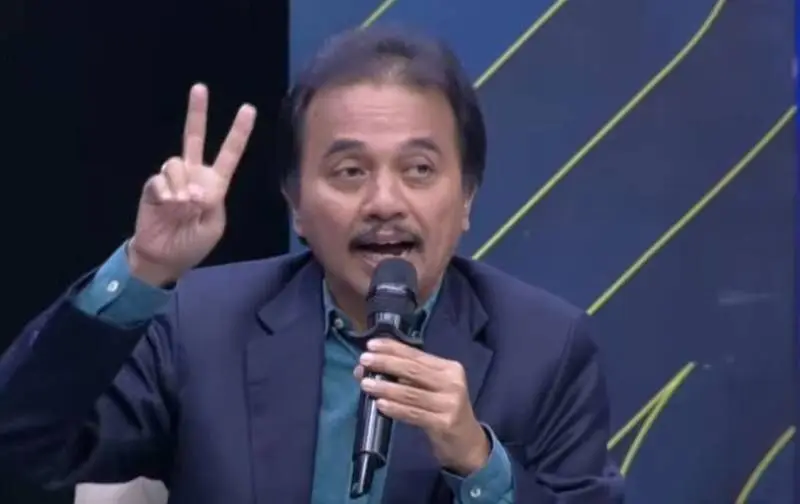Mengurai Akar Masalah TBC: Tantangan Politik hingga Budaya di Daerah Terpencil
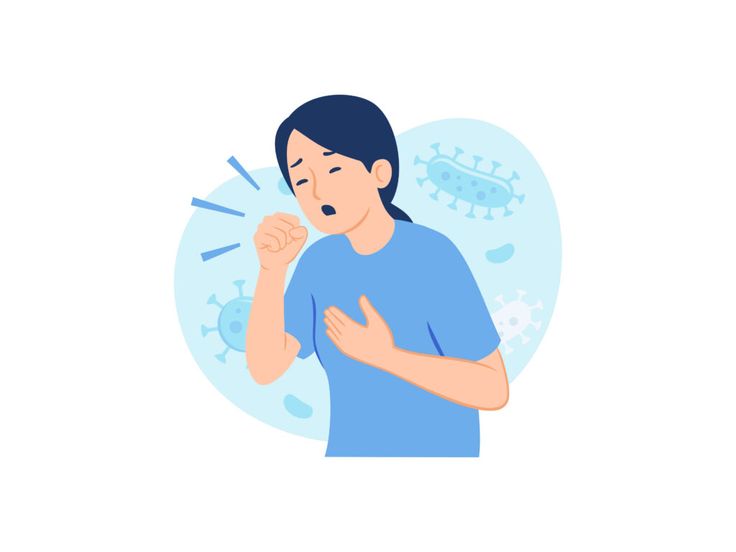

Oleh: Yohanes Soares*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Pemberantasan TBC di Indonesia tidak hanya menghadapi persoalan medis, tetapi juga tantangan politik yang mendalam. Salah satu hambatan terbesar adalah rendahnya prioritas politik terhadap isu TBC.
Karena tidak memiliki nilai elektoral yang memadai, para kepala daerah cenderung tidak menempatkan TBC sebagai program unggulan, sehingga intervensi sering terlambat, dukungan politik minim, dan akuntabilitas lemah.
Desentralisasi layanan kesehatan, meskipun secara konsep memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah, tidak diiringi dengan pengawalan teknis yang memadai.
Variasi kapasitas birokrasi menyebabkan implementasi kebijakan nasional tidak merata. Banyak daerah gagal menerjemahkan strategi nasional menjadi layanan efektif di lapangan.
Selain itu, anggaran kesehatan sering kali terserap pada proyek infrastruktur yang mudah terlihat, renovasi gedung atau pembangunan sarana fisik sementara kebutuhan mendesak seperti deteksi dini, logistik obat, tracing, dan insentif petugas lapangan justru terabaikan.
Siklus politik jangka pendek juga menjadi masalah. Program eliminasi TBC membutuhkan kesinambungan selama 5–10 tahun, namun kebijakan daerah sering terikat pada siklus pemerintahan 4–5 tahun, menghambat keberlanjutan program.
Tanpa kepemimpinan politik yang berkomitmen dan mekanisme akuntabilitas yang kuat, pemberantasan TBC akan bergantung pada donor dan inisiatif sporadis, sebuah kondisi yang tidak stabil dan tidak berkelanjutan.
Secara Sosial dan Stigma: Ketika Penyakit Menjadi Label, Bukan Sekadar Kondisi Medis
Secara sosial, TBC masih dibungkus stigma yang kental. Banyak masyarakat memandang TBC sebagai penyakit kotor atau akibat perilaku buruk, sehingga pasien enggan memeriksakan diri karena takut dicap atau kehilangan peluang kerja, hubungan sosial, dan pernikahan.
Stigma ini memutus mata rantai layanan, dari diagnosis hingga penyelesaian terapi. Jaringan sosial yang rapuh terutama di daerah dengan tingkat migrasi tinggi atau keluarga terfragmentasi, menyebabkan pasien tidak memiliki dukungan memadai untuk menjalani pengobatan enam bulan penuh.
Faktor gender juga memperburuk situasi. Perempuan dan anak sering diprioritaskan terakhir dalam akses kesehatan akibat beban domestik dan ketergantungan ekonomi, sedangkan laki-laki menghadapi tekanan sosial, seperti perilaku merokok dan pencari nafkah utama, yang menghambat deteksi dini.
Lebih jauh, minimnya organisasi masyarakat sipil yang fokus pada advokasi TBC di tingkat lokal membuat proses penurunan stigma tidak berjalan optimal. Semua dinamika ini memperlambat upaya eliminasi TBC dan membuat strategi medis menjadi kurang efektif.
Ekonomi dan Akses Finansial: Ketika Kemiskinan Menentukan Pilihan Sehat atau Makan
Dari perspektif ekonomi, pemberantasan TBC terkunci oleh kemiskinan struktural yang memaksa masyarakat memilih antara kesehatan dan kebutuhan dasar. Walaupun obat TBC disediakan secara gratis, biaya non-medis seperti transportasi, kehilangan upah harian, kebutuhan nutrisi, dan akomodasi menjadi beban berat bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Bagi pekerja informal yang bergantung pada pendapatan harian, berobat sama artinya dengan tidak makan pada hari itu. Kondisi pekerjaan yang tidak fleksibel membuat pasien mustahil untuk hadir ke fasilitas kesehatan sesuai jadwal.
Di sisi lain, program TBC jarang menyediakan insentif atau kompensasi finansial yang cukup, sehingga tingkat kepatuhan rendah dan kasus putus obat meningkat. Ketergantungan pada dana donor di beberapa daerah juga menciptakan ketidakpastian keberlanjutan program.
Tanpa intervensi ekonomi yang terstruktur seperti subsidi transport atau dukungan nutrisi pasien tetap terjebak dalam dilema antara perut kenyang atau pengobatan yang konsisten.
Medis dan Sistem Layanan Kesehatan: Ketika Kapasitas Sistem Tidak Mengejar Beban Penyakit
Secara medis, tantangan pemberantasan TBC terlihat dalam setiap tahap layanan mulai dari deteksi, diagnosis, pengobatan, hingga tindak lanjut. Deteksi dini masih rendah, terutama di wilayah terpencil yang jarang mendapat skrining aktif.
Kasus sering terdeteksi pada tahap menular, memperbesar risiko penyebaran komunitas. Fasilitas diagnostik yang memadai seperti GeneXpert dan rontgen digital tidak tersedia di banyak puskesmas, sehingga sampel harus dikirim jauh ke fasilitas rujukan mengakibatkan penundaan hasil.
Kekurangan SDM terlatih menambah kerumitan: petugas puskesmas belum mampu melakukan tracing intensif atau pendampingan pasien secara konsisten. Rantai pasokan obat sering terganggu, terutama di daerah pedalaman, membuat pasien rentan putus obat.
Kompleksitas bertambah dengan isu TBC resisten obat (MDR-TB) dan komorbiditas seperti HIV, malnutrisi, dan diabetes. Semua ini memperburuk outcome pengobatan dan membuat pencapaian eliminasi TBC semakin jauh dari target.
Budaya, Adat Istiadat, dan Habitus: Ketika Praktik Tradisi Menentukan Respons Kesehatan
Budaya lokal berperan besar dalam respons masyarakat terhadap TBC. Di beberapa komunitas, batuk berkepanjangan ditafsirkan sebagai akibat gangguan roh atau angin sehingga pasien lebih memilih dukun atau pengobatan tradisional sebelum ke fasilitas medis.
Norma menjaga nama baik keluarga menyebabkan kasus TBC cenderung disembunyikan. Ritual adat dan kebiasaan sosial yang melibatkan kerumunan tanpa protokol kesehatan juga mempercepat penularan.
Selain itu, habitus ekonomi yang menempatkan kebutuhan harian sebagai prioritas utama membentuk pola pikir bahwa kesehatan preventif adalah kemewahan.
Bahasa juga menjadi kendala: materi kampanye dalam bahasa teknis sering tidak dipahami masyarakat adat. Intervensi kesehatan yang tidak sensitif budaya mudah ditolak atau diabaikan, sehingga adaptasi kultural menjadi kunci keberhasilan program.
Infrastruktur dan Geografi: Ketika Fasilitas Kesehatan Ada, tetapi Mustahil Dijangkau
Geografi dan infrastruktur yang buruk membuat pemberantasan TBC di daerah terpencil sangat sulit. Jalan rusak, lintasan sungai tanpa jembatan, dan jarak jauh ke fasilitas kesehatan membuat kunjungan berkala mustahil bagi pasien.
Banyak puskesmas tidak memiliki tenaga laboratorium atau rontgen, sehingga tidak mampu memberi layanan komprehensif. Teknologi seperti telemedicine masih minim, dan sistem data surveilans tidak real-time, membuat monitoring kepatuhan pasien sulit dilakukan.
Hambatan fisik ini memperbesar risiko pasien putus obat dan memperburuk penularan komunitas.
Pendidikan Kesehatan dan Literasi: Ketika Informasi Tidak Menjadi Pengetahuan
Rendahnya literasi kesehatan membuat masyarakat tidak memahami mekanisme penularan, gejala, dan pentingnya menjalani pengobatan hingga tuntas. Kampanye kesehatan sering bersifat generik dan tidak mempertimbangkan konteks budaya maupun bahasa lokal.
Pendekatan yang digunakan lebih bersifat informatif daripada mengubah perilaku, sehingga dampaknya jarang signifikan. Padahal tokoh agama dan sekolah dapat menjadi saluran edukasi efektif jika dilibatkan secara sistematis. Rendahnya literasi akhirnya memperpanjang masa sakit dan meningkatkan penularan.
Etika dan Hak Asasi: Ketika Pasien Berjuang Sendiri
Dari aspek etika dan HAM, banyak pasien TBC kehilangan hak atas privasi dan perawatan layak. Ketakutan identitas terungkap saat kunjungan rumah (DOTS) membuat pasien enggan melanjutkan pengobatan.
Sebagian masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan pada dasarnya kehilangan hak fundamental atas kesehatan, karena jarak dan biaya menjadi penghalang utama. Kegagalan negara menjamin akses setara memperdalam ketidakadilan struktural yang sudah dialami kelompok miskin di daerah terpencil.
Kesimpulan: Menghapus TBC adalah Mengoreksi Struktur
Pemberantasan TBC tidak dapat dipandang semata sebagai urusan medis, ini adalah persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan struktural.
Daerah terpencil membutuhkan pendekatan multisektoral: komitmen politik yang kuat, dukungan ekonomi untuk pasien, sistem kesehatan yang adaptif, intervensi berbasis budaya, serta perlindungan hak-hak pasien.
Tanpa transformasi struktural ini, upaya klinis terbaik sekalipun akan tetap terkekang oleh realitas sosial-ekonomi yang membatasi masyarakat dalam mengejar kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar mereka. (Red)
*) Yohanes Soares, aktivis sosial dan mahasiswa S3 Universitas Dr. Soetomo Surabaya