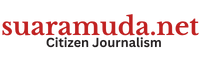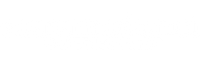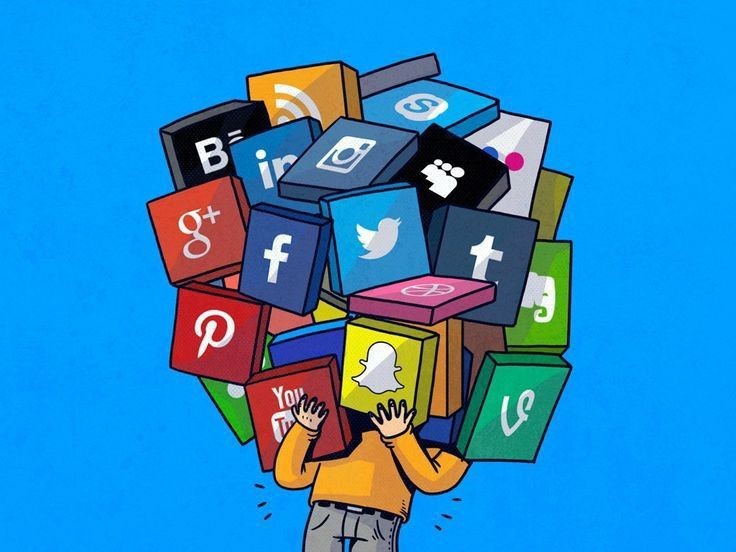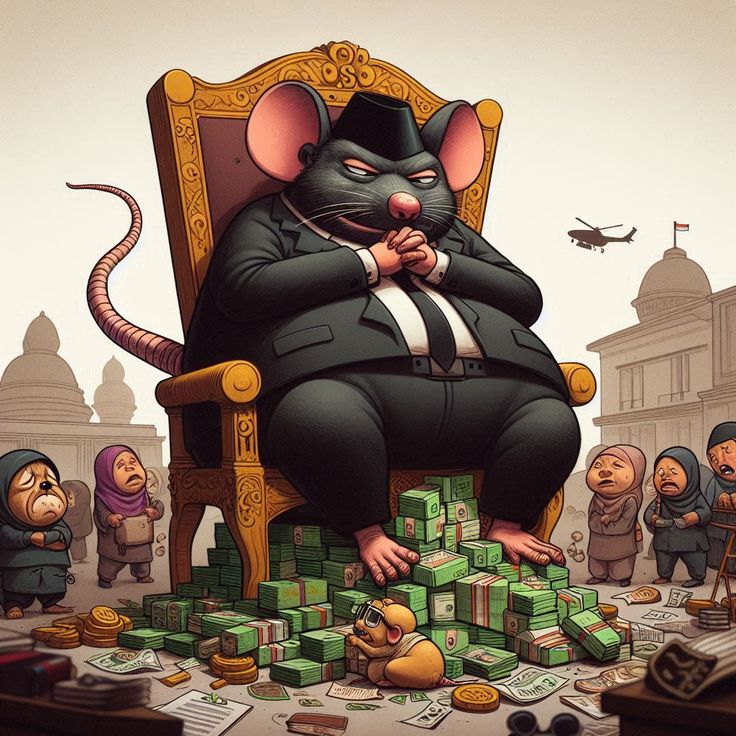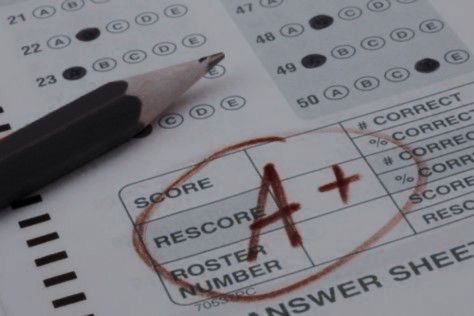Hari Pangan Sedunia: Menjaga Rasa, Tradisi, dan Kearifan Lokal (Studi pada Daerah NTT dan Sulawesi Utara)


Oleh: Yohanes Soares*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Hari Pangan Sedunia seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan atau sekadar momentum berbagi foto makanan di media sosial.
Lebih dari itu, hari ini mestinya menjadi ajakan untuk merenung dan menakar ulang makna pangan dalam kehidupan kita, bukan sekadar soal kenyang, tetapi juga tentang identitas, kedaulatan, dan keberlanjutan.
Dalam konteks daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara, dua wilayah yang kaya dengan budaya pangan dan ragam sumber daya lokal, peringatan ini membuka ruang untuk menggali kembali kearifan lokal sebagai pondasi ketahanan pangan yang sejati.
Di banyak komunitas di kedua daerah ini, pangan bukan hanya persoalan konsumsi, tetapi juga cerminan hubungan manusia dengan alam, adat, dan sejarah. Setiap bahan makanan memiliki kisahnya sendiri.
Di NTT, masyarakat mengenal jagung titi, ubi nuabosi, dan sorgum yang ditanam dengan sistem rotasi lahan untuk menjaga kesuburan tanah dan ketersediaan pangan di musim kering.
Sementara di Sulawesi Utara, ada sinonggi, tinutuan, dan rica-rica yang tidak sekadar menu harian, tetapi ekspresi budaya dan adaptasi ekologi yang menakjubkan. Pola tanam, teknik pengolahan, hingga ritual berbagi hasil panen menggambarkan sistem sosial yang memelihara keseimbangan antara manusia dan lingkungannya.
Namun, kearifan itu kini berhadapan dengan arus modernisasi yang menggulung tanpa henti. Pola konsumsi masyarakat kian seragam, didominasi beras, terigu, dan makanan instan.
Sistem pangan global yang menekankan efisiensi dan keuntungan ekonomi telah meminggirkan pangan lokal yang sesungguhnya lebih tahan terhadap perubahan iklim dan lebih beragam secara gizi.

Perlahan-lahan, varietas jagung lokal tergantikan oleh benih hibrida, teknik pengawetan tradisional dilupakan, dan cita rasa asli tergeser oleh selera pasar. Ketika pangan berubah menjadi sekadar komoditas ekonomi, kita kehilangan nilai budaya dan filosofi yang terkandung di dalamnya.
Ironisnya, kebijakan pemerintah sering kali memperkuat homogenisasi itu. Program ketahanan pangan lebih banyak diukur dari produksi beras dan kestabilan harga, bukan dari keberagaman pangan, keadilan akses, atau pelestarian sumber daya lokal.
Padahal, ketahanan pangan sejati tidak lahir dari satu jenis bahan makanan yang ditanam massal, melainkan dari sistem pangan yang beragam, inklusif, dan berbasis komunitas. Di sinilah pentingnya mengembalikan peran masyarakat lokal sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program.
Kita bisa belajar dari kearifan yang masih bertahan di desa-desa. Di banyak tempat, gotong royong masih menjadi sistem distribusi yang efektif. Ketika satu keluarga gagal panen, keluarga lain membantu, ketika hasil laut melimpah, masyarakat berbagi.
Jaringan sosial seperti ini jauh lebih tangguh dibanding mekanisme pasar modern yang rapuh terhadap fluktuasi harga dan krisis pasokan. Perempuan, khususnya, berperan penting sebagai penjaga pengetahuan pengolahan pangan dan benih lokal.
Mereka bukan hanya koki, tetapi ilmuwan rumah tangga yang menjaga keberlanjutan sumber pangan keluarga dan komunitasnya.
Untuk membangun ketahanan pangan berbasis kearifan lokal, kita perlu langkah konkret dan sistematis. Pertama, mendokumentasikan pengetahuan tradisional tentang pangan dari teknik pengolahan hingga jenis tanaman lokal agar tidak hilang bersama generasi tua.
Kedua, membangun bank benih komunitas yang menjaga keanekaragaman varietas lokal. Ketiga, memperkuat peran perempuan dan kelompok muda dalam rantai nilai pangan lokal melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan modal mikro.
Keempat, menyediakan infrastruktur kecil seperti tempat pengeringan dan penyimpanan pangan yang dapat memperpanjang umur simpan hasil panen tanpa kehilangan nilai gizinya. Kelima, mengembangkan pariwisata kuliner berbasis etika yang melibatkan masyarakat lokal secara langsung, bukan menjadikan budaya mereka sekadar pajangan.
Selain itu, dunia akademik, LSM, dan pemerintah daerah harus berkolaborasi secara transdisipliner. Peneliti pertanian, antropolog, dan ekonom perlu bekerja bersama untuk merancang kebijakan dan inovasi yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga menghormati nilai budaya dan konteks sosial-ekologis setempat.
Ketahanan pangan tidak bisa dibangun dari laboratorium atau ruang rapat saja, tetapi dari dialog sejajar antara pengetahuan ilmiah dan kearifan tradisional.
Namun, tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah atau lembaga tertentu. Setiap individu memiliki peran. Pilihan konsumsi sehari-hari adalah bentuk sikap politik terhadap pangan.
Dengan membeli dan mengonsumsi produk lokal, kita ikut menjaga ekosistem ekonomi yang adil dan lestari. Dengan menulis, mendokumentasikan, atau sekadar mengajarkan resep keluarga kepada anak cucu, kita memperpanjang usia budaya pangan kita sendiri.
Maka, mengenang Hari Pangan Sedunia seharusnya tidak berhenti pada slogan atau acara simbolik. Ini adalah panggilan untuk kembali merasakan hubungan yang lebih dalam antara rasa dan tradisi antara tubuh, tanah, dan budaya.
NTT dan Sulawesi Utara telah membuktikan bahwa di tengah keterbatasan sumber daya, mereka memiliki kekayaan rasa dan kearifan yang luar biasa. Tugas kita adalah menjaganya agar tidak menjadi sekadar cerita masa lalu, melainkan sumber kekuatan untuk menghadapi masa depan.
Sebab, ketahanan pangan sejati bukan hanya tentang seberapa banyak kita menanam dan memanen, tetapi seberapa kuat kita menjaga nilai, rasa, dan kearifan yang tumbuh bersama tanah dan waktu.
Hari Pangan Sedunia harus menjadi pengingat bahwa setiap butir jagung, setiap umbi, setiap ikan, dan setiap bumbu tradisional adalah bagian dari sejarah panjang perjuangan manusia mempertahankan hidup dengan rasa, dengan martabat, dan dengan cinta pada bumi tempat kita berpijak. (Red)
*) Yohanes Soares, Aktivis Sosial dan Peneliti Kebijakan Pendidikan dan Masyarakat Daerah Tertinggal; mahasiswa S3 Universitas Dr. Soetomo Surabaya