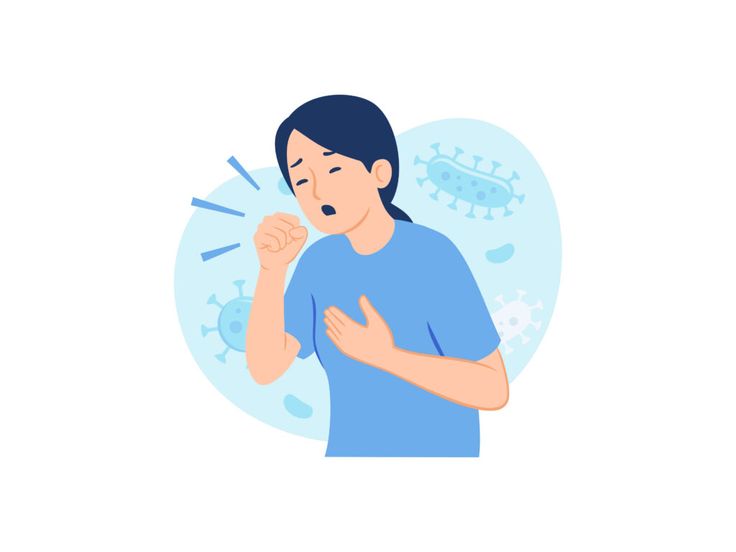Tanah Suci dengan Keindahannya: Perempuan Arab dan Tren Perempuan Indonesia


Oleh: Faiz Rafdillah*)
SUARAMUDA. NET., SEMARANG —Selama hampir 40 hari menjalani ibadah haji di Tanah Suci, saya mengalami banyak momen yang menggetarkan hati. Namun di balik spiritualitas yang begitu pekat, ada pula realitas sosial-budaya yang menyelinap diam-diam ke dalam kesadaran saya.
Salah satunya adalah bagaimana perempuan di berbagai negara, khususnya dari kawasan Timur Tengah, menampilkan dirinya di ruang publik, bukan dalam arti pamer, tapi sebagai bentuk ekspresi diri yang utuh dan alami.
Sepanjang berada di Mekkah dan Madinah, saya banyak menyaksikan perempuan dari latar Arab, Turki, Iran, hingga kawasan Teluk, tampil dengan percaya diri. Mereka hadir dengan bentuk tubuh yang beragam termasuk dengan tubuh yang berisi, semok, bahkan besar, namun tetap terlihat nyaman dan tak canggung berada di tengah keramaian.
Tak ada tekanan untuk tampak langsing atau mengikuti standar tubuh yang dipuja-puji oleh media. Mereka hadir begitu saja, membawa dirinya tanpa rasa salah. Dari situlah saya mulai berpikir, mungkinkah standar kecantikan memang dibentuk oleh bentang budaya yang berbeda-beda?
Konteks ini terasa kontras jika dibandingkan dengan tren perempuan Indonesia, baik di media konvensional maupun media sosial, yang sebagian besar masih terpaku pada citra tubuh yang langsing, putih, dan muda sebagai tolak ukur kecantikan.
Tak jarang, obsesi pada tubuh ideal justru berakar pada warisan kolonial, kapitalisme produk kecantikan, dan algoritma digital yang menyuguhkan satu tipe tubuh sebagai norma.
Pertemuan antara dua dunia ini, antara perempuan Arab yang nyaman dengan bentuk tubuh natural mereka dan perempuan Indonesia yang dibentuk oleh budaya ‘harus ideal’, menjadi refleksi penting yang layak dibicarakan lebih jauh.
Standar Kecantikan di Timur Tengah: Antara Warisan Tradisi dan Kepercayaan Diri
Di banyak negara Timur Tengah, kecantikan perempuan tidak melulu didefinisikan oleh angka timbangan atau siluet tubuh sempit seperti yang kerap dipromosikan dalam budaya Barat atau di sebagian media Asia.
Di Arab Saudi, Yordania, Lebanon, hingga kawasan Teluk, bentuk tubuh yang berisi kerap kali dianggap sebagai simbol kecantikan, kemakmuran, dan bahkan status sosial. Ini bukan semata-mata persoalan ukuran, tapi juga bagaimana tubuh dibingkai oleh nilai budaya, agama, dan persepsi kolektif.
Tidak seperti tren global yang dipengaruhi oleh standar ‘zero-size’ ala Hollywood atau K-pop yang identik dengan tubuh mungil, masyarakat Timur Tengah memiliki narasi sendiri.
Dalam banyak konteks budaya Arab, tubuh perempuan tidak dituntut untuk “kecil”, melainkan untuk tampil kuat, sehat, dan padat. Penampilan tidak selalu diarahkan untuk konsumsi publik, tapi lebih sebagai bentuk penghormatan pada diri sendiri dan keluarga. Ini bisa kita lihat dalam keseharian, baik dalam cara perempuan berpakaian, berjalan, hingga berinteraksi sosial.
Namun, tentu saja standar ini tidak muncul begitu saja. Ia adalah produk dari sejarah panjang budaya patriarki, pengaruh agama, sistem keluarga yang kolektif, dan resistensi terhadap dominasi budaya Barat.
Di satu sisi, hal ini bisa dilihat sebagai bentuk otonomi budaya atas tubuh perempuan. Tapi di sisi lain, bukan berarti perempuan Timur Tengah bebas sepenuhnya dari tekanan. Banyak dari mereka yang justru menghadapi dualitas antara tuntutan domestik yang konservatif dengan ekspektasi sosial yang berubah akibat globalisasi dan media digital.
Fenomena ini menjadi semakin menarik ketika kita lihat dalam konteks kontemporer. Di TikTok, Instagram, atau YouTube, mulai bermunculan influencer perempuan Arab yang merayakan bentuk tubuh mereka yang berisi, menolak stigma diet ketat, dan menantang narasi kecantikan universal.
Sosok seperti Danae Mercer, jurnalis asal Timur Tengah, dan sejumlah influencer lokal dari UAE atau Mesir, mulai mempopulerkan body positivity sebagai bentuk perlawanan simbolik. Mereka tidak hanya menjadi simbol tren, tetapi juga aktor kultural dalam pergeseran makna tubuh di wilayah yang dulunya sangat tertutup.
Dengan kata lain, standar kecantikan di Timur Tengah tidak bisa disamakan dengan satu wajah atau satu ukuran tubuh. Ia adalah ladang tafsir yang kompleks, berisi negosiasi antara tradisi, modernitas, dan kemunculan media sosial sebagai panggung baru.
Panggung Digital dan Perempuan Arab: Negosiasi Identitas di Tengah Algoritma
Media sosial hari ini bukan lagi sekadar ruang berbagi, melainkan arena pertunjukan identitas yang terus-menerus dinegosiasikan. Bagi banyak perempuan Arab, platform seperti Instagram, TikTok, dan Snapchat bukan hanya menjadi kanal ekspresi diri, tapi juga ladang tarik-menarik antara nilai-nilai budaya, tuntutan agama, dan arus globalisasi digital.
Di balik jilbab yang mereka kenakan atau pakaian longgar yang menghormati norma syariat, banyak perempuan Arab justru menunjukkan keberanian baru dalam menampilkan tubuh, kecantikan, dan gaya hidup mereka di ranah daring. Tapi keberanian ini bukan tanpa risiko.
Di banyak kasus, mereka dihadapkan pada komentar bernuansa misoginis, tekanan sosial dari keluarga, atau bahkan ancaman hukum di beberapa negara dengan regulasi ketat terhadap aktivitas perempuan di dunia maya.
Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi alat yang memperluas ruang agensi perempuan. Influencer seperti Salma El-Wardany, Noor Tagouri, dan banyak perempuan muda dari Arab Saudi atau Mesir memanfaatkan TikTok dan Instagram untuk mendobrak batasan, membicarakan topik tubuh, kesehatan mental, peran gender, hingga seksualitas dengan cara yang lembut tapi provokatif.
Konten mereka tidak hanya dikonsumsi di lingkup regional, tetapi juga menarik perhatian global yang menciptakan dialog antara Timur dan Barat tentang tubuh, norma, dan otonomi perempuan. Uniknya, algoritma media sosial yang mempromosikan apa yang dianggap “trending” dan layak masuk For You Page justru sering kali menciptakan bias.
Tren yang viral cenderung mendikte perempuan untuk tetap berada dalam estetika yang visual, menarik, dan mengikuti gaya global, bahkan ketika nilai-nilai lokal mereka berbeda. Maka tak heran jika muncul benturan antara konten berani dengan komentar pengguna lokal yang menuntut kesopanan.
Di sinilah panggung digital berubah menjadi arena dilema: mengikuti arus algoritma atau mempertahankan nilai komunitas. Perempuan Arab hari ini berjalan di antara batas-batas ini.
Mereka merayakan tubuhnya, mendefinisikan kecantikannya sendiri, tapi juga harus berhadapan dengan suara-suara konservatif yang masih kuat. Dan di sinilah keunikan mereka: tampil bukan hanya sebagai objek yang dinilai, tetapi sebagai subjek yang memilih.
Kurus Itu Menarik? Cermin Budaya Tubuh di Indonesia yang Belum Selesai
Berbeda dari perempuan Timur Tengah yang cenderung lebih nyaman dan percaya diri dengan tubuh berisi atau padat, perempuan Indonesia masih terperangkap dalam mitos tubuh ideal yang harus langsing, putih, berambut lurus, dan bermata besar.
Narasi ini begitu dominan, diwariskan oleh warisan kolonialisme, diperkuat oleh media konvensional, dan kemudian direplikasi berulang kali oleh media sosial. Di lini masa Instagram hingga TikTok Indonesia, tubuh kurus bukan sekadar preferensi estetika, tapi menjadi simbol kesuksesan, kontrol diri, bahkan nilai moral.
Banyak influencer perempuan yang dengan bangga membagikan tips diet ekstrem, olahraga berlebihan, atau bahkan prosedur kecantikan sebagai bagian dari pencapaian personal. Alih-alih membebaskan, tubuh di sini justru dijadikan medan kompetisi yang membungkam banyak perempuan dari keberagaman bentuk tubuh mereka yang alami.
Narasi ini didorong oleh kapitalisme visual dengan narasi semakin langsing, semakin estetik, semakin layak tampil. Ini membuat banyak perempuan Indonesia merasa tidak cukup hanya dengan menjadi sehat.
Mereka harus terlihat seperti yang “trending”, harus pantas masuk ke kamera, harus memenuhi selera algoritma. Di sinilah tubuh menjadi panggung, bukan tempat tinggal diri, tapi properti yang harus dipoles untuk dipamerkan.
Bandingkan ini dengan perempuan Arab yang dalam pengamatan saya selama haji, tampak lebih tenang dan apa adanya dengan bentuk tubuh mereka. Mereka bisa tampil anggun tanpa tekanan untuk terlihat langsing.
Bahkan dalam balutan abaya atau hijab panjang, rasa percaya diri mereka terasa utuh, bukan karena tubuhnya kecil, tetapi karena mereka tidak mengukur harga diri dari kecil atau besarnya tubuh. Perbedaan ini bukan soal siapa yang lebih baik, tapi tentang bagaimana budaya membentuk persepsi diri dan tekanan sosial.
Di Indonesia, kebutuhan untuk diterima oleh masyarakat atau untuk tampil sesuai “standar kecantikan” sering kali membuat perempuan merasa asing dengan tubuh mereka sendiri. Di sinilah pentingnya refleksi: mengapa kita, sebagai bangsa yang majemuk dan kaya budaya, masih terpaku pada standar yang sempit?
Tubuh Bukan Sekadar Bentuk, Tapi Jejak Perjalanan Diri
Tubuh perempuan selalu menjadi pusat perdebatan, baik dalam wacana budaya, agama, maupun media. Namun, setelah 40 hari menyaksikan beragam wajah, langkah, dan diam-diam merasakan atmosfer kesalehan serta kompleksitas manusia di Tanah Suci, saya mulai menyadari sesuatu yang mungkin terlupa, tubuh bukan sekadar tampilan, tapi ingatan hidup.
Ia menyimpan jejak perjalanan, luka, kemenangan, dan kerentanan. Di tengah jutaan manusia dari seluruh dunia, aku melihat bagaimana perempuan membawa tubuhnya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berjalan tertatih, ada yang melangkah gagah, ada yang menggandeng ibu atau anaknya dengan kelembutan yang tak bisa dijelaskan.
Dalam balutan kain ihram, semua bentuk tubuh seakan larut dalam kesetaraan spiritual. Di sana aku melihat makna tubuh yang sejati: sebagai kendaraan menuju pengabdian, bukan sekadar objek untuk dipandang.
Tapi ketika kembali menatap layar media sosial kita, kontras itu begitu tajam. Tubuh kembali dipersempit menjadi “konten”, dilihat dari sudut kamera terbaik, dengan filter paling halus, dan narasi self-love yang seringkali paradoks, mencintai diri, tapi terus mengoreksi yang dianggap kurang.
Kita lupa bahwa tubuh bukan hanya soal bagaimana ia terlihat, tapi bagaimana ia dihuni. Tubuh adalah rumah bagi pengalaman manusia. Ia tidak sempurna, dan tak seharusnya sempurna.
Tapi ia menyimpan semua cerita: tentang perjuangan, pencarian makna, dan proses menjadi diri sendiri. Jika perempuan Timur Tengah bisa percaya diri dengan bentuk tubuhnya tanpa perlu menjelaskan, mengapa perempuan Indonesia harus terus merasa bersalah atas tubuhnya sendiri?
Mungkin kita butuh sudut pandang baru. Bukan untuk meniru budaya lain, tetapi untuk memulihkan relasi kita sendiri dengan tubuh. Bahwa tubuh bukan panggung performatif, melainkan ruang spiritual dan sosial yang layak dihargai, bukan dikoreksi tanpa henti.
Menjadi Perempuan yang Merdeka atas Tubuhnya Sendiri
Dari lorong Masjidil Haram hingga jalanan Madinah, dari kerumunan wukuf hingga suasana hotel tempat para jemaah beristirahat, aku menyaksikan bagaimana tubuh perempuan Arab dan sekitarnya berjalan bebas dari kecemasan akan standar kecantikan modern yang sering kali menindas.
Mereka mungkin tak kurus, tak selalu mengikuti tren global soal “body goals”, tapi kehadiran mereka yang penuh percaya diri dan tenang dalam balutan busana yang panjang dan lebar, mengajarkan satu hal penting, tubuh bukan untuk dilihat, tapi untuk dijalani.
Sementara di tanah air, perempuan Indonesia masih berjuang dalam tekanan algoritma: tuntutan untuk kurus, untuk tampil sempurna di FYP, untuk terus memoles citra diri demi eksistensi digital. Kita telah sampai di zaman ketika tubuh bukan hanya dilihat oleh orang lain, tapi juga terus dikritik oleh diri sendiri.
Dan dalam kondisi itu, cinta diri menjadi ilusi, bukan solusi. Namun, semestinya tubuh bukan kompetisi. Ia adalah ekspresi individual yang tak bisa dipaksa menyatu dalam satu ukuran. Tubuh perempuan Indonesia layak diterima apa adanya, bukan atas dasar bagaimana ia tampil di layar, tapi bagaimana ia menjadi tempat yang utuh bagi kehidupan.
Di hari-hari terakhir saya di Tanah Suci, saya teringat bahwa 1 Juni adalah hari kelahiran Pancasila. Dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila kedua yang sering kita ucapkan, namun jarang benar-benar direnungkan dalam konteks tubuh.
Bukankah mencintai tubuh sendiri, menghargai keberagaman bentuk tubuh orang lain, dan menolak standar kecantikan yang menyakitkan juga bagian dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
Mungkin kini saatnya kita, bangsa yang besar ini, memberi ruang lebih luas bagi narasi tubuh yang beragam. Agar para perempuan tidak hanya bebas mengekspresikan diri, tapi juga merdeka atas tubuhnya sendiri yang tanpa beban, tanpa malu, tanpa harus menyesuaikan diri dengan ukuran yang bukan miliknya.
*) Faiz Rafdillah, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta