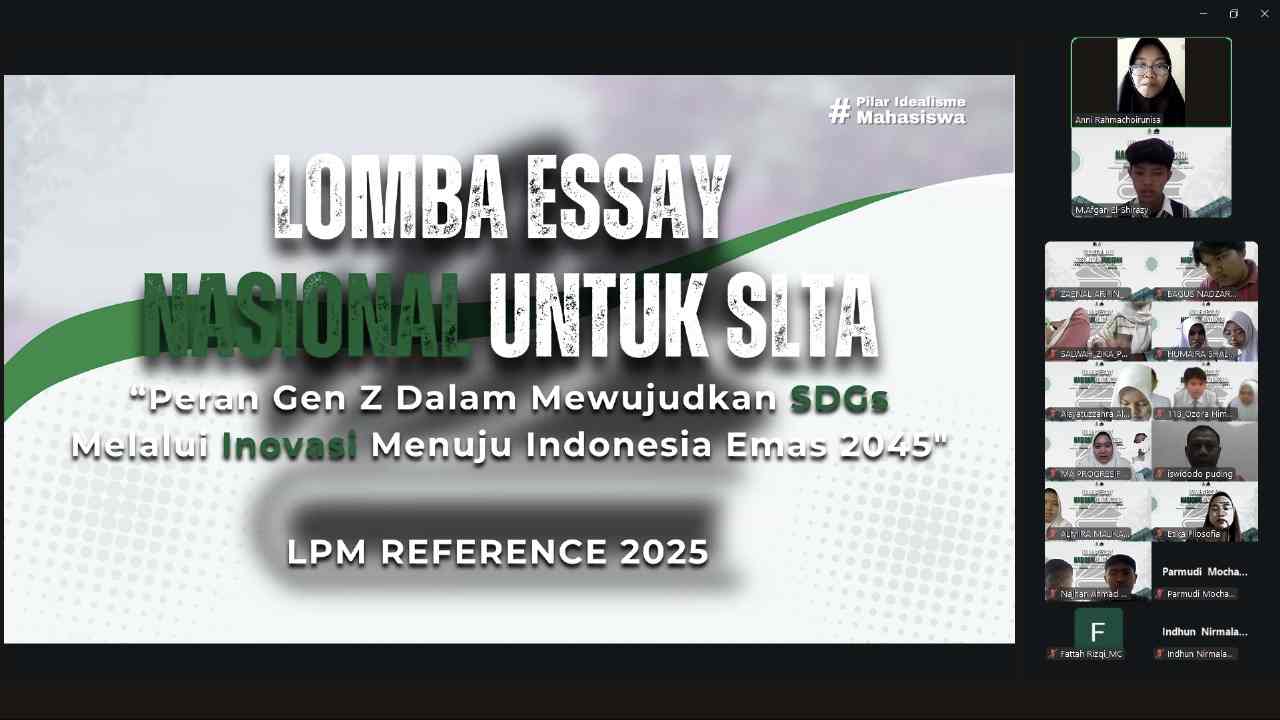Santri dan Diplomasi dari Timur: Direktur Sino-Nusantara Institute Bedah Peluang Islam Tiongkok di Kuliah Tamu UB


SUARAMUDA.NET, MALANG — Dunia diplomasi kini tak lagi sekaku meja perundingan antarnegara. Kadang, peluang diplomasi justru lahir dari ruang-ruang akademik yang hangat, penuh ide segar, dan diwarnai semangat muda.
Seperti yang dilakukan Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya (UB), Kamis malam (6/11/2025).
Melalui kuliah tamu bertajuk “Rekonfigurasi Identitas Muslim di Tiongkok: Tantangan Globalisasi dan Peluang Diplomasi Santri Indonesia”, para mahasiswa diajak memahami bagaimana Islam hidup di tengah politik, ekonomi, dan budaya Tiongkok—sekaligus melihat peluang baru bagi diplomasi berbasis nilai-nilai santri.
Acara ini digelar secara daring lewat Zoom Meeting pukul 19.30–21.30 WIB, menghadirkan Ahmad Syaifuddin Zuhri, Direktur Sino-Nusantara Institute, yang dikenal sebagai pengamat hubungan internasional, khususnya hubungan Indonesia–Tiongkok.

Islam di Negeri Komunis?
Dalam paparannya, Zuhri, yang juga dosen FISIP UIN Walisongo Semarang itu membuka diskusi dengan menggambarkan realitas unik Tiongkok.
“Secara ideologi politik, Tiongkok memang komunis. Tapi praktik ekonominya justru sosialis— atau kapitalisme negara, meskipun pemerintahnya secara resmi menganut paham sosialis, “jelasnya.
“Model ekonomi ini memadukan elemen kapitalisme pasar, seperti kepemilikan swasta dan persaingan internasional, dengan kontrol dan campur tangan negara yang kuat melalui kepemilikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peran strategis dari Partai Komunis. Atau mereka menyebut secara resmi Sosialisme dengan karakteristik China, “imbuhnya.
Zuhri menambahkan, bahwa semua kebijakan negeri Tirai Bambu berpijak pada ideologi resmi negara, sebagaimana Indonesia punya Pancasila
Maka, baik urusan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri, semuanya dirancang berdasarkan kerangka ideologi tersebut—termasuk dalam mengatur posisi agama-agama, seperti Islam dan Kristen dan lainnya.
Jejak Panjang Islam di Tiongkok
Zuhri kemudian mengajak peserta “menyusuri waktu”, menelusuri bagaimana Islam masuk ke Tiongkok sekitar abad ke-7— yang dibuktikan dengan berdirinya masjid pertama di Tiongkok, Masjid Huaisheng Guangzhou di era Dinasti Tang.
Menurutnya, penyebaran Islam di Tiongkok banyak dianut oleh etnis Hui dan Uighur, dua kelompok yang selama ini identik dengan identitas Muslim di negeri itu. Saat ini ada kurang lebih 30-40 juta penganut muslim di Tiongkok.
Meski mereka bukan mayoritas di antara 56 etnis yang ada, kehadiran mereka cukup kuat dalam membangun wajah Islam Tiongkok yang khas.
“Kehidupan warga Muslim Tiongkok sejatinya baik-baik saja. Meski ada kebijakan Sinifikasi Agama di era Xi Jinping, dimana agama harus beradaptasi dan menyerap kearifan lokal,” tutur Zuhri.
Diplomasi Santri: Peluang dari Timur
Bagian paling menarik datang ketika Zuhri menyinggung potensi besar bagi santri Indonesia.
Menurutnya, hampir di setiap kota besar di Tiongkok kini terdapat komunitas Muslim yang cukup adaptif, bahkan membuka ruang interaksi lintas budaya dengan diaspora santri Indonesia di negeri tersebut.

Diplomasi Santri yang dipelopori oleh diaspora Indonesia dari PCINU Tiongkok dan PCIM Tiongkok yang jumlahnya ratusan. Yang sedang belajar maupun bekerja.
“Komunitas Muslim di Tiongkok hidup berdampingan dan terbuka terhadap interaksi global. Di sinilah santri Indonesia punya peluang emas untuk memainkan peran diplomasi kultural—membawa semangat Islam yang rahmatan lil ‘alamin, seperti wajah Islam Nusantara,” ujarnya.
Dalam satu dekade terakhir, santri Indonesia cukup banyak berperan dalam hubungan Indonesia-Tiongkok khususnya di level people-to-people connection.
Dalam konteks diplomasi modern, kehadiran santri bukan sekadar simbol religiusitas, tapi juga representasi nilai moderasi dan kebijaksanaan khas Indonesia.
Bayangkan saja, di tengah citra Islam global yang sering distigmatisasi keras, santri dengan karakter santun, terbuka, dan intelektual bisa menjadi “duta damai” yang menjembatani dunia Islam dan Tiongkok.
Santri: Diplomat Baru Indonesia?
Kegiatan kuliah tamu ini memberi pandangan segar: diplomasi hari ini tak melulu harus lewat Negara melalui Kementerian Luar Negeri atau duta besar. Ada jalur lain—lebih lembut tapi tak kalah strategis—yakni diplomasi berbasis budaya dan agama.

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tradisi santri yang kuat, punya soft power luar biasa untuk memperkuat hubungan antarbangsa.
Dalam konteks Tiongkok, peluang ini bisa diarahkan pada kerja sama pendidikan, dialog antaragama, hingga pertukaran komunitas Muslim.
Zuhri menutup sesinya dengan nada optimistis. “Globalisasi memang membawa tantangan identitas, tapi juga membuka ruang untuk kolaborasi. Dan santri Indonesia, dengan modal keilmuan dan nilai-nilai universalnya, bisa jadi aktor penting dalam diplomasi di Asia Timur.”
Catatan Akhir
Kuliah tamu Prodi HI UB malam itu bukan sekadar kelas daring dua jam. Ia menjadi jendela baru bagi mahasiswa untuk memahami politik identitas, peran Islam, dan pentingnya membangun diplomasi dengan sentuhan humanisme santri.
Di era globalisasi, ketika batas negara makin cair dan identitas makin dinegosiasikan, justru santri Indonesia punya modal paling otentik: kesantunan, keilmuan, dan keikhlasan untuk berdialog.
Dan dari Malang malam itu, lahir optimisme baru—bahwa masa depan diplomasi Indonesia bisa berangkat dari pesantren, bukan hanya dari istana. (Red)