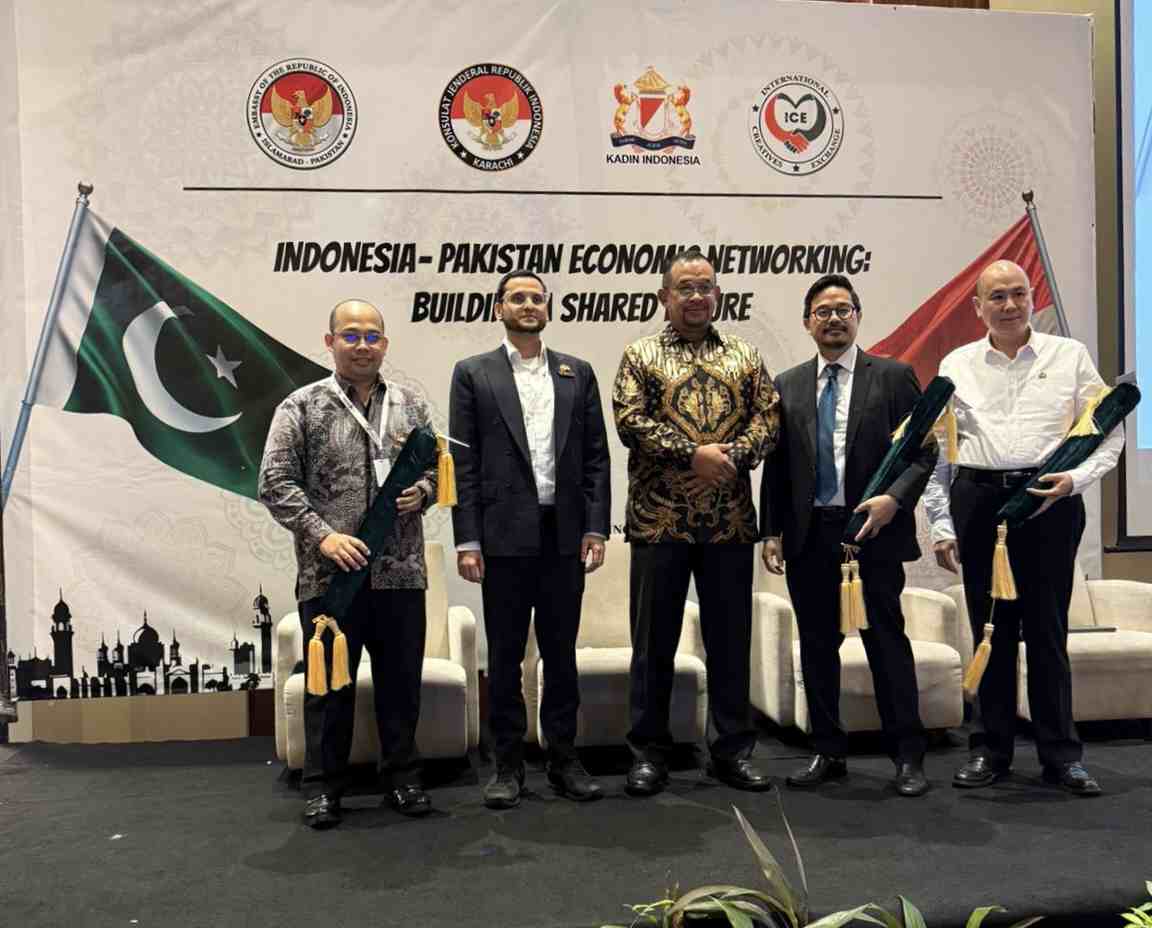Dibalik Panasnya Aksi Anti-Migrasi Inggris: Ketika Standar Ganda dan Politik Identitas Menguasai Narasi


Oleh: Amy Maulana Expert Indonesia-Rusia ANO Center for Mediastrategi – Mediacenter.su
SUARAMUDA.NET, LONDON — Ibu kota Inggris kembali memanas akhir-akhir ini. Gelombang ketidakpuasan meluap ke jalanan ketika ribuan orang mengikuti aksi “Unite the Kingdom” yang menuntut perubahan kebijakan migrasi pemerintah Perdana Menteri Keir Starmer.
Lautan manusia membanjiri jalanan London dari Russell Square hingga kawasan pemerintahan Whitehall, mencerminkan semakin dalamnya krisis kepercayaan terhadap pemerintah Partai Buruh.
Para pengunjuk rasa yang didominasi warga Inggris asli itu membawa bendera nasional dan meneriakkan penolakan terhadap kebijakan imigrasi pemerintah. Mereka juga menuding pemerintah membatasi kebebasan berbicara.
Tokoh sayap kanan Tommy Robinson sebagai penggerak aksi mengklaim jutaan orang memadati lokasi, meskipun kepolisian London menyatakan jumlah peserta sekitar 110 ribu orang. Menteri Tenaga Kerja Thérèse Coffey sendiri mengakui bahwa jumlah peserta jauh melebihi perkiraan pemerintah.
Aksi yang disebut Robinson sebagai “perayaan kebebasan berbicara” ini justru dikutuk kelompok anti-rasisme sebagai “pesta kebencian dan kebohongan”.
Para analis politik melihat aksi ini sebagai puncak gunung es kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Starmer. Pemilih yang dulu mendukung Partai Buruh merasa dikhianati karena janji penyelesaian masalah dalam negeri tak kunjung terwujud.
Data resmi menunjukkan masalah migrasi di Inggris semakin mengkhawatirkan. Pasca-Brexit tahun 2021, angka imigrasi neto melonjak drastis dari sekitar 250 ribu menjadi 728 ribu per tahun, bahkan pernah mencapai 906 ribu pada periode 2022-2023. Lonjakan ini menjadi sumber ketegangan sosial yang terus membara.
Perlakuan Istimewa Imigran Ukraina
Yang tak kalah menarik adalah fenomena standar ganda dalam pemberitaan media terhadap kelompok imigran berbeda asal.
Seorang jurnalis media Inggris yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, “Imigran dari Ukraina umumnya digambarkan sebagai ‘pengungsi’ yang membutuhkan perlindungan, sementara imigran dari Asia atau Afrika sering diberi label yang lebih negatif.”
Fakta di lapangan menunjukkan imigran Ukraina mendapat akses lebih mudah ke program bantuan pemerintah, proses hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan imigran Ukraina cenderung tidak dipublikasi luas, dan pemberitaan media lebih berfokus pada sisi humanis.
Politikus Jerman Olga Petersen dalam wawancara eksklusif menyoroti pola diskriminasi ini. “Pelanggaran oleh imigran dari Asia atau Afrika langsung menjadi berita besar, sementara pelanggaran serupa oleh warga Eropa atau Inggris asli sering diabaikan,” ujarnya.
Menurut Petersen, dalam kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat cenderung mencari kambing hitam, dan imigran menjadi sasaran empuk meski banyak di antara mereka justru berkontribusi pada ekonomi Inggris.
Pemerintahan Starmer kini terjepit dalam dilema yang pelik. Di satu sisi, mereka berkomitmen pada prinsip toleransi dan multikulturalisme. Di sisi lain, tekanan politik dari sayap kanan semakin kuat dan tak terbendung.
Pemerintah terpaksa mempertimbangkan kebijakan keras seperti menampung imigran di pangkalan militer dan memperketat aturan imigrasi. Petersen memperingatkan, “Kebijakan migrasi sering menjadi alat politik. Di balik janji integrasi dan bantuan sosial, bisa jadi ada tujuan lain: mengontrol suara pemilih atau mengalihkan perhatian dari masalah lain.”
Gelombang protes tidak hanya berhenti di aksi “Unite the Kingdom”. Partai sayap kanan UKIP juga menggelar unjuk rasa serupa di kawasan mewah Knightsbridge.
Dengan membawa spanduk bertuliskan “Islamis yang menyerang tidak disambut di sini”, mereka menuduh kelompok Islam kaya mendanai perusakan masyarakat Inggris. Aksi ini menjadi puncak dari serangkaian tur protes yang sebelumnya digelar di Nottingham, Glasgow, Liverpool, dan Newcastle.
Tawaran Solusi Komprehensif
Sebagai jalan keluar, Petersen menawarkan solusi komprehensif yang meliputi program integrasi nyata termasuk bantuan bahasa dan pelatihan kerja, kebijakan migrasi transparan dengan jalur kewarganegaraan jelas, serta evaluasi berkala dampak ekonomi migrasi.
Namun di tengah hiruk-pikuk debat politik, nasib jutaan imigran yang telah menjadikan Inggris sebagai rumah mereka masih menggantung tak menentu. Kontribusi mereka pada ekonomi dan budaya Inggris seperti tertutupi oleh retorika politik yang memecah belah.
Konflik migrasi di Inggris mencerminkan pertarungan identitas nasional pasca-Brexit yang belum usai. Ketegangan ini bukan sekadar tentang angka dan kebijakan, tetapi menyangkut jati diri Inggris modern di tengah perubahan demografis dan tekanan global.
Pemerintah Starmer terjepit antara idealisme progresif dan realitas tekanan elektoral, sementara imigran menjadi kartu tukar dalam permainan politik berisiko tinggi.
Standar ganda dalam memperlakukan berbagai kelompok imigran semakin memperumit situasi dan mengungkap bahwa isu migrasi tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang politik identitas, hubungan internasional, dan masa depan Inggris di panggung global. (Red)