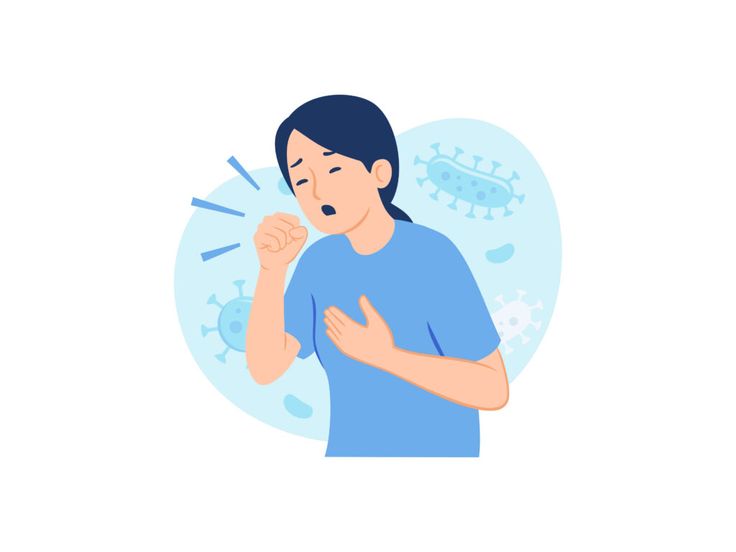

Refleksi Kritis: Ironi Rendahnya Gaji Pendidik dan Merosotnya Peran Negara dalam Pendidikan Tinggi
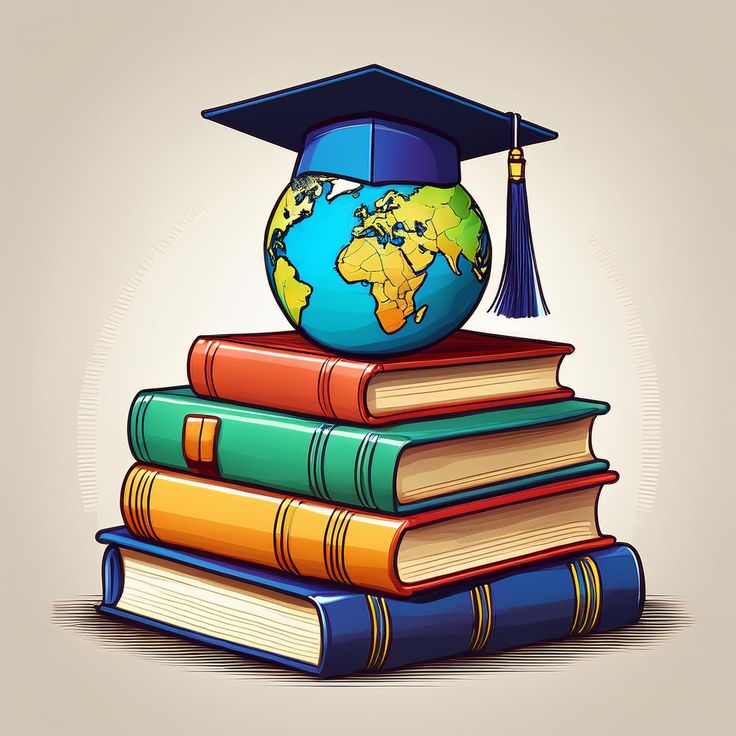

Oleh: Yohanes Soares*)
SUARAMUDA.NET., SEMARANG – Di balik setiap gelar sarjana, master, atau doktor yang kita banggakan, ada figur pendidik yang tak pernah berhenti bekerja bahkan setelah bel kuliah selesai.
Dosen dan pengajar perguruan tinggi memikul beban ganda: sebagai penyampai ilmu sekaligus penuntun moral, peneliti, penulis, pembimbing, pengelola administrasi akademik, dan sering kali juga sebagai “orang tua” bagi mahasiswa perantauan.
Beban ini tak tertulis di kontrak kerja, tetapi melekat dalam setiap interaksi mereka. Namun, penghargaan yang diberikan negara kepada mereka kerap memalukan.
Gaji pokok banyak dosen muda bahkan lebih rendah dari pendapatan sektor informal yang tidak menuntut pendidikan bertahun-tahun.
Tunjangan kinerja yang dijanjikan kerap tersendat, insentif penelitian jauh dari cukup, dan peluang peningkatan kesejahteraan bergantung pada proyek-proyek luar yang sifatnya sporadis.
Di titik inilah, profesi yang seharusnya menjadi puncak kehormatan justru sering dipandang sebagai jalan sunyi yang penuh pengorbanan tanpa jaminan kelayakan hidup.
Beban Tanggung Jawab yang Tak Seimbang
Pendidik di perguruan tinggi tidak sekadar membaca materi di depan kelas. Mereka diminta melahirkan penelitian berkualitas, publikasi internasional, inovasi teknologi, sekaligus menjaga kualitas lulusan yang mampu bersaing di pasar global.
Ironinya, output yang diharapkan adalah “kelas dunia”, sementara input yang mereka terima berupa gaji dan fasilitas sering kali kelas bawah.
Ketidakseimbangan ini menggerus motivasi, memicu kelelahan mental (burnout), dan secara perlahan menurunkan kualitas pendidikan.
Merosotnya Peran Negara
Konstitusi menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental dan kewajiban negara. Namun realitas kebijakan menunjukkan pergeseran: pendidikan tinggi semakin dipandang sebagai investasi pribadi, bukan tanggung jawab publik.
Biaya kuliah terus naik, subsidi dipangkas, dan tenaga pendidik sering terjebak dalam status kontrak yang tidak menentu.
Sementara itu, anggaran pendidikan yang besar sering tersedot untuk program birokratis atau infrastruktur yang tak langsung menyentuh kesejahteraan tenaga pengajar.
Lebih memprihatinkan, narasi “efisiensi anggaran” kerap dijadikan tameng untuk menghindari perbaikan struktural gaji dosen.
Padahal, negara yang mengabaikan kesejahteraan pendidik sedang membangun pondasi rapuh bagi masa depannya sendiri.
Risiko Jangka Panjang
Ketika gaji tak mencukupi, pendidik terpaksa mencari penghasilan tambahan, mengajar di banyak kampus, mengambil proyek non-akademik, atau bahkan beralih ke profesi lain.
Fokus mereka pada riset dan bimbingan mahasiswa pun terkikis. Dalam jangka panjang, kita berisiko kehilangan generasi pendidik berkualitas.
Talenta muda dengan potensi besar memilih jalur karier lain yang lebih menjanjikan, meninggalkan dunia akademik dalam kekosongan regenerasi.
Kita akan menghadapi universitas-universitas yang megah secara fisik, namun miskin isi, dengan dosen yang hadir sekadarnya dan penelitian yang minim kontribusi.
Ini bukan sekadar masalah kesejahteraan profesi, ini adalah masalah keberlanjutan mutu pendidikan nasional.
Mengembalikan Martabat Profesi
Menaikkan gaji pendidik bukanlah bentuk kebaikan hati negara, melainkan pemenuhan kewajiban konstitusional.
Reformasi harus mencakup penetapan standar gaji minimum yang layak, tunjangan riset yang memadai, serta jaminan status kerja yang aman.
Transparansi alokasi anggaran pendidikan perlu ditegakkan, agar tidak ada lagi alasan bahwa “dana tidak cukup” sementara proyek-proyek lain yang kurang mendesak justru melimpah pendanaan.
Pendidikan tinggi adalah salah satu instrumen paling strategis dalam membangun daya saing bangsa.
Mengabaikan kesejahteraan pendidiknya sama dengan membiarkan kapal berlayar dengan nakhoda yang lelah, lapar, dan kehilangan harapan. (Red)
*)Yohanes Soares, aktivis sosial dan peneliti kebijakan pendidikan dan masyarakat daerah tertinggal; mahasiswa S3 Universitas Dr. Soetomo Surabaya

















