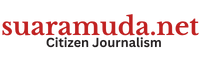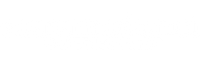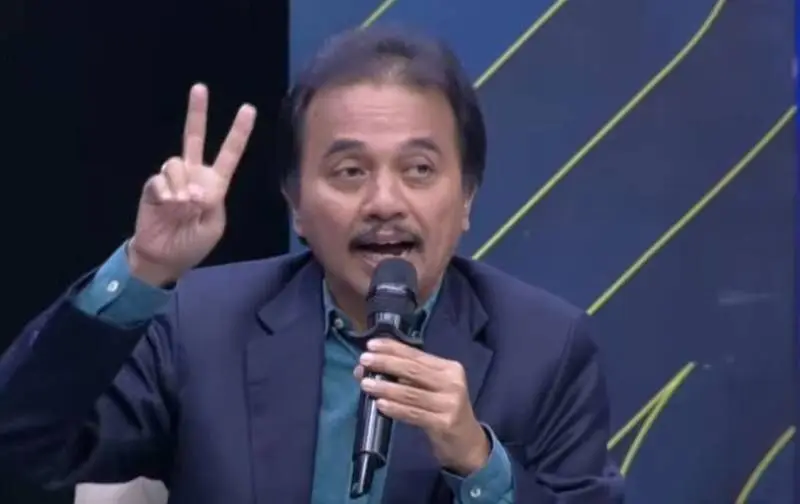Belajar dari SMAN 72 Jakarta, Sekolah Ramah Anak Bukan Hanya Slogan


Oleh: Badat Alauddin*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Tragedi yang mengguncang SMAN 72 Jakarta pada 7 November 2025, dua kali ledakan tepat di masjid sekolah pada saat ibadah Jumat yang melukai puluhan siswa seharusnya menjadi panggilan bangun bagi dunia pendidikan dan masyarakat kita.
Berdasarkan laporan media, korban luka mencapai sekurang-kurangnya 54 orang dalam insiden tersebut. Sementara motif belum sepenuhnya terang, pihak kepolisian secara terbuka menyatakan bahwa salah satu dugaan utama adalah bahwa pelaku adalah seorang siswa yang lama menjadi korban bullying atau perundungan.
Jika dugaan ini benar bahwa seorang siswa yang merasa terus-menerus ditekan, terisolasi, atau dicaci maki kemudian memilih jalan ekstrem sebagai tanggapan, maka kita tidak sedang melihat sekadar tindakan kriminal tunggal, melainkan sebuah kegagalan sistemik: kegagalan sekolah, keluarga, teman sebaya, bahkan masyarakat untuk mengenali, mencegah, dan menanggapi luka psikologis di usia remaja.
Psikolog anak dan remaja, Sani Budiantini Hermawantelah dilansir dari media Indonesia menegaskan hal tersebut: “Ketika anak menjadi korban bully, ia bisa menyimpan emosi yang sangat dalam. Kalau tidak ada tempat aman untuk berdialog … emosi itu bisa meledak dalam bentuk perilaku agresif.”
Sekolah idealnya adalah lingkungan aman dan tempat tumbuh bagi anak-anak, bukan arena di mana rasa sakit dan kemarahan menumpuk hingga akhirnya meletus. Namun laporan menunjukkan bahwa kekerasan di sekolah, baik yang bersifat fisik, verbal maupun sosial, masih merupakan masalah serius di Indonesia.
Di SMAN 72, dugaan pelaku membawa bom rakitan yang hanya dua dari tiga jenisnya meledak, karena menurut satu siswa “saya menduga siswa ini ingin balas dendam dan bunuh diri”.
Bayangkan: seorang pemuda di ruang ibadah sekolah memilih akan melakukan kekerasan besar bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada banyak teman sekelasnya, ini adalah tragedi dalam kegagalan sistem pendidikan.
Lebih jauh, ini memperlihatkan bagaimana bullying tidak hanya berdampak jangka pendek (seperti stress, penurunan prestasi, atau withdrawal sosial) tetapi juga dapat menjadi akar bagi tindakan radikal atau ekstrem.
Ketika seorang siswa merasa tidak punya outlet untuk mengenali dan menyampaikan rasa sakitnya, ketika ia merasa tak punya pendengar baik dari guru, wali kelas, teman atau orang tua, maka rasa sakit itu bisa menular ke dalam bentuk yang jauh lebih destruktif.
Menurut Daniel J. Siegel dan Tina Payne Bryson dalam bukunya “The Whole-Brain Child”, ia berpendapat “Anak yang merasa tidak memiliki dukungan emosional bisa meniru perilaku ekstrem yang dilihatnya di internet.”
Karena itu, tanggung jawab kita sebagai masyarakat bukan hanya mengecam tindakan pelaku, tetapi juga melihat ke belakang, apa yang memungkinkan situasi ini? Apakah sistem sekolah sudah menyediakan jalur aman untuk siswa melapor bullying?
Apakah guru dan staf benar-benar dilatih untuk mendeteksi anak yang terisolasi, yang menjadi target gosip atau sindiran, atau yang mengalami kekerasan halus tiap hari?
Apakah ada dukungan psikologis yang memadai di sekolah dan kerjasama dengan orang tua untuk mendampingi anak-anak ini? Karena seperti yang dikatakan: pelaku bisa jadi korban dari sistem yang gagal.
Dari sisi kebijakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sudah menegaskan bahwa kekerasan di sekolah masih menjadi masalah serius, dan akan dibentuk regulasi untuk lingkungan sekolah yang “aman, ramah, bebas dari kekerasan yang humanis, komprehensif, dan partisipatif” dalam program “sekolah ramah anak” .
Ini adalah langkah penting, tetapi implementasi di lapangan, di setiap ruang kelas, setiap koridor sekolah, setiap ruang makan, yang akan menentukan apakah tragedi seperti ini akan terulang atau tidak.
Perlu juga diperhatikan bahwa penanganan setelah kejadian. Para korban fisik yang dalam insiden ini sejumlah siswa yang masih dirawat, termasuk beberapa di ICU perlu mendapat dukungan psikologis jangka panjang.
Trauma bisa melekat, bahkan bagi yang tidak terluka secara fisik tetapi menyaksikan ledakan dan panik massal. Sekolah harus membuka layanan pemulihan, konseling, sesi kelompok siswa, dan orang tua harus dilibatkan dalam dialog pemulihan.
Media dan publik pun memiliki peran untuk harus selalu berhati-hidup dari spekulasi tanpa fakta karena itu bisa memicu stigma tambahan, baik terhadap korban maupun pelaku.
Namun, kita juga tidak boleh memberi jalan bagi siklus diam yang memperkuat budaya bullying. Transparansi, pelaporan yang aman, dan lingkungan yang memupuk empati harus dimajukan.
Dalam skala lebih luas, peristiwa SMAN 72 adalah peringatan bahwa bullying bukan “masalah anak-anak” biasa yang bisa diabaikan, tetapi bibit dari luka sosial yang bisa meledak.
Jika lingkungan sekolah dan masyarakat terus membiarkan siswa merasa “tidak terdengar”, “terasing”, atau “tak punya ruang aman”, maka kita menciptakan kondisi di mana kemarahan bisa beralih ke kekerasan.
Rekaman ledakan itu menjadi simbol bahwa peristiwa ini bukan hanya ledakan fisik, tapi ledakan dari pemutusan ikatan sosial, dari pengabaian rasa sakit, dari kegagalan sistem untuk hadir.
Kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah menciptakan “sekolah yang mendengar?” Apakah kita sudah memberi anak-anak kita ruang untuk berkata “saya terluka” tanpa takut diejek?
Apakah guru dan staf sekolah benar-benar “teman” bagi murid yang sunyi? Apakah orang tua punya akses untuk berbicara dengan anak mereka, dan mengetahui kalau ada yang salah sebelumnya? Jika jawabannya “belum” maka kita masih jauh dari aman.
Tragedi di SMAN 72 harus menjadi momentum perubahan nyata. Bukan sekadar belasungkawa dan laporan media, tetapi reformasi dalam kultur sekolah, dalam sistem pelaporan bullying, dalam layanan psikologis siswa, dan dalam komitmen seluruh stakeholder, baik guru, siswa, orang tua, pemerintah, maupun media massa untuk menciptakan lingkungan di mana tidak ada anak yang merasa sendiri, tidak ada celah untuk rasa sakit yang akhirnya meledak.
Karena ketika sekolah aman, maka tragedi seperti ini bukan hanya bisa dicegah, bukan hanya dengan pengamanan fisik, tapi dengan pengamanan hati dan hubungan antar-manusia. (Red)
*) Badat Alauddin, Kepala Sekolah MTs Al-Muhsin Yogyakarta