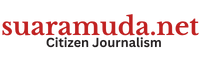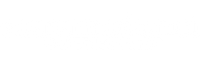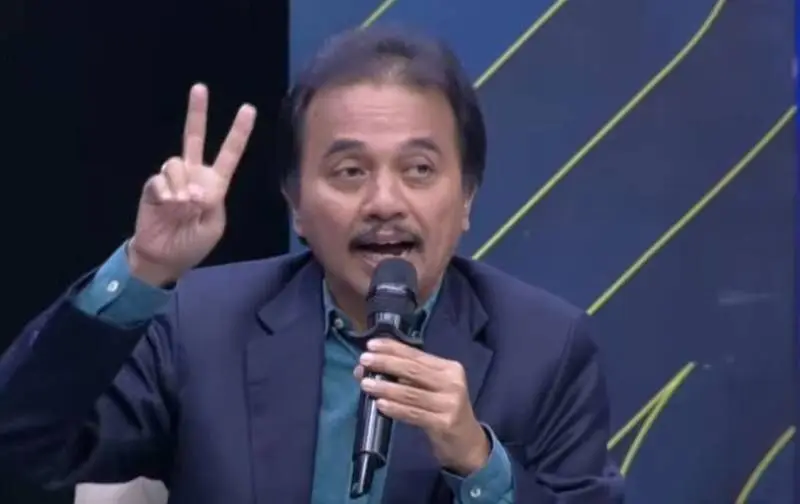Bullying dan Ledakan Sunyi di Sekolah: Ketika Luka Psikologis Berubah Menjadi Api Kekerasan


Oleh: Yohanes Soares*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Di banyak sekolah, bullying sering dianggap bagian dari dinamika remaja. Ejekan ringan, panggilan nama-nama kasar, nama orang tua atau perundungan di media sosial kerap dilewati begitu saja tanpa penanganan serius.
Namun di balik tawa-tawa sinis dan candaan yang dianggap remeh itu, sesungguhnya tersimpan bom waktu psikologis. Luka mental akibat bullying tidak selalu meledak ke luar, ia bisa menumpuk di dalam diri korban, mengendap dalam diam, dan suatu hari meledak bukan hanya melukai dirinya sendiri, tetapi juga orang lain.
Kasus-kasus kekerasan ekstrem di sekolah, termasuk tindakan balas dendam, perusakan fasilitas, bahkan ancaman membom sekolah, sering kali bukan muncul tiba-tiba. Ia adalah akumulasi rasa sakit yang lama diabaikan.
Fenomena ini mengingatkan kita bahwa setiap sistem sosial yang gagal mendengar jeritan individu rapuh sedang menyiapkan ruang bagi lahirnya tragedi baru.
Bullying sebagai Kekerasan Struktural dan Sistemik
Bullying bukan sekadar tindakan antarindividu, ia adalah refleksi dari budaya kekuasaan di lingkungan pendidikan. Ketika seorang siswa menjadi sasaran, ada sistem yang membiarkannya terjadi entah karena abai, takut, atau malah menikmati ketimpangan itu.
Guru yang diam, teman yang tertawa, dan institusi yang tak punya mekanisme perlindungan, semuanya adalah bagian dari struktur yang membiakkan kekerasan.
Secara psikologis, bullying menanamkan tiga benih destruktif: rasa rendah diri, kemarahan terpendam, dan kehilangan makna. Dalam jangka panjang, tiga hal ini dapat berkembang menjadi gangguan mental seperti depresi, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), dan gangguan identitas.
Korban kehilangan rasa percaya pada sistem sosial, lalu mencari cara untuk mendapatkan kembali kendali. Ketika mekanisme adaptif seperti dukungan sosial atau konseling tidak tersedia, kemarahan itu mencari jalan keluar dalam bentuk yang paling ekstrem.
Dalam teori sistem sosial, sekolah adalah miniatur masyarakat. Jika sistemnya hanya menghargai prestasi akademik dan menyingkirkan empati, maka kekerasan akan dianggap normal. Bullying yang dibiarkan adalah indikator bahwa sistem pendidikan kita sedang gagal mengajarkan kemanusiaan.
Dari Trauma Menuju Teror: Paradoks Balas Dendam Sosial
Perilaku ekstrem seperti ancaman membom sekolah atau kekerasan balasan terhadap pelaku bukanlah hasil spontanitas emosional. Ia adalah simbol keputusasaan, bentuk komunikasi terakhir dari seseorang yang tidak pernah didengar.
Dalam psikologi sosial, ini disebut perlawanan patologis, ketika individu yang merasa powerless mencoba mengembalikan kekuasaan melalui kekerasan.
Korban bullying mengalami degradasi identitas, dari subjek menjadi objek ejekan. Dalam kondisi kronis, otak manusia merespons rasa sakit sosial seperti rasa sakit fisik, aktivasi korteks anterior cingulate menunjukkan bahwa ejekan bisa menyakitkan secara biologis.
Jika luka ini tidak disembuhkan, individu akan mencari cara ekstrem untuk menegaskan kembali keberadaannya, bahkan dengan cara destruktif.
Tindakan seperti ancaman bom atau penyerangan terhadap sekolah adalah bentuk simbolik dari pesan yang tidak pernah sempat diucapkan, Lihat aku. Aku juga manusia. Ironisnya, sistem sosial yang mengabaikan tanda-tanda kecil inilah yang tanpa sadar ikut menyiapkan panggung bagi tragedi.
Sekolah dan kegagalan ekologi empati
Kita sering membangun sekolah dengan pagar tinggi, kamera CCTV, dan sistem keamanan yang ketat. Namun kita lupa membangun sistem empati kolektif di dalamnya.
Sekolah yang aman bukanlah sekolah yang diawasi, tetapi sekolah yang membuat setiap siswanya merasa diakui. Oleh karenanya, ketika seorang siswa berulang kali dirundung, dan guru menanggapinya dengan anggap saja bercanda, kita sedang mencabut hak anak untuk merasa aman.
Ketika siswa lain hanya menjadi penonton pasif, kita sedang menanamkan nilai bahwa diam lebih aman daripada benar. Ekosistem ini menciptakan spiral kebisuan di mana setiap jeritan bantuan tenggelam dalam formalitas birokrasi sekolah.
Dalam kacamata socio-ecological model, bullying tidak terjadi dalam ruang hampa. Ada faktor intrapersonal (harga diri rendah, depresi), interpersonal (keluarga disfungsional, peer pressure), komunitas (budaya sekolah yang permisif), hingga kebijakan makro (minimnya layanan kesehatan mental di sekolah). Semua lapisan ini saling menguatkan hingga kekerasan menjadi biasa.
Refleksi: Mendengar Sebelum Terlambat
Di era digital, bullying tidak berhenti di pagar sekolah. Ia mengikuti korban ke rumah, ke ponsel, ke ruang tidur, bahkan ke pikirannya sendiri. Kita hidup dalam dunia di mana kekerasan sosial tak lagi butuh kontak fisik cukup dengan jempol dan sinyal. Dan di dunia seperti itu, satu pesan kebencian bisa menjadi peluru yang lebih tajam dari senjata.
Pertanyaannya: apakah kita masih mau menunggu hingga korban berikutnya mengubah luka menjadi ledakan? Apakah kita akan terus menambal krisis dengan seminar dan poster, tanpa menata ulang sistem nilai di sekolah?
Kita perlu berpindah dari pendekatan reaktif menuju preventif-humanistik. Sekolah harus menjadi ruang penyembuhan sosial bukan hanya tempat transfer pengetahuan, tetapi tempat belajar mengenali rasa sakit, mendengarkan tanpa menghakimi, dan memulihkan martabat manusia.
Guru bukan sekadar pengajar, tapi penjaga jiwa muda. Teman sebaya bukan sekadar saksi, tapi pelindung moral. Dan sistem pendidikan bukan sekadar struktur birokrasi, tapi ekologi kemanusiaan yang harus memelihara rasa aman psikologis semua individu di dalamnya.
Penutup: dari Bom Menjadi ‘Jembatan’
Setiap tindakan kekerasan ekstrem di sekolah bukan sekadar peristiwa kriminal, melainkan tanda gagalnya sistem sosial membaca penderitaan.
Jika kita hanya fokus menghukum tanpa memahami akar luka, maka kita hanya akan memadamkan api di permukaan sementara bara kebencian tetap menyala di dalam hati anak-anak lain yang juga terluka.
Tugas kita bukan sekadar mencegah ledakan, tapi mencegah luka yang membuat seseorang ingin meledak. Dan itu hanya mungkin jika sekolah berani menata ulang budaya komunikasinya dari diam menjadi dialog, dari penghakiman menjadi empati, dan dari bullying menjadi belonging. (Red)
Catatan Penulis:
Tulisan ini merupakan refleksi kritis terhadap fenomena kekerasan psikososial di dunia pendidikan Indonesia. Penulis tidak membenarkan segala bentuk kekerasan dan mendorong integrasi layanan kesehatan mental, pendidikan karakter, dan kebijakan anti-bullying yang nyata di seluruh sekolah.
*) Yohanes Soares, Aktivis Sosial dan Peneliti Kebijakan Pendidikan dan Masyarakat Daerah Tertinggal; mahasiswa S3 Universitas Dr. Soetomo Surabaya