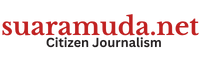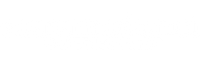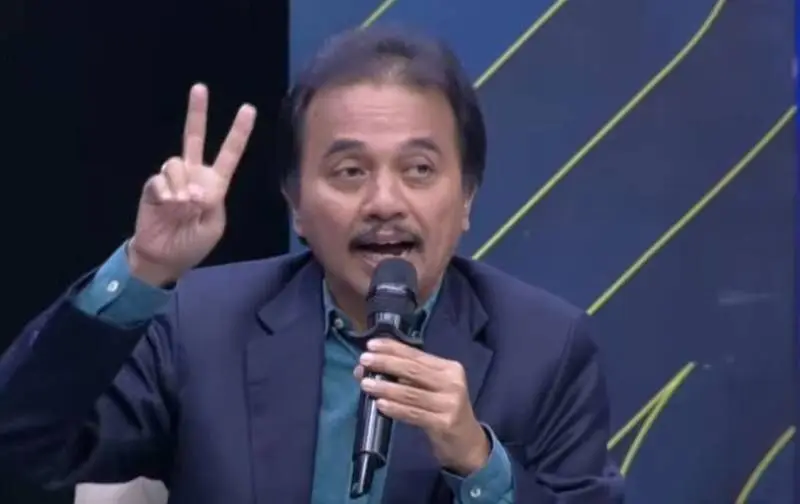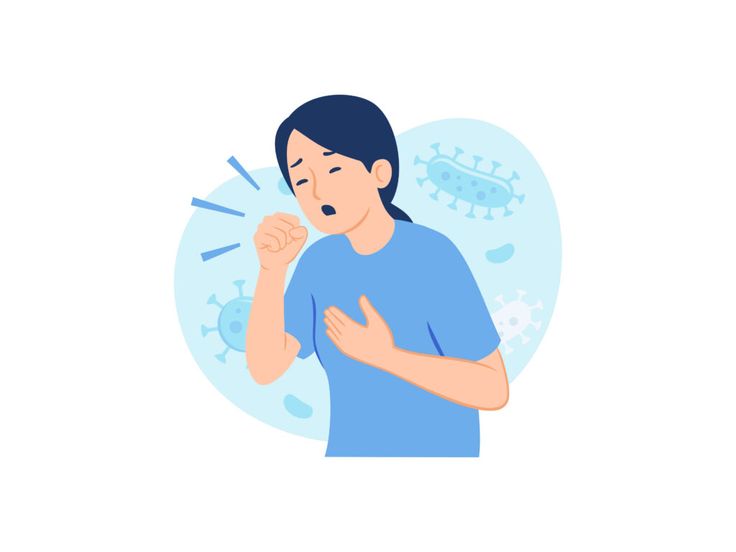

Tubuh, Pekerjaan, dan Pilihan: Perempuan Jawa dalam Cengkeraman Patriarki dan Kapitalisme
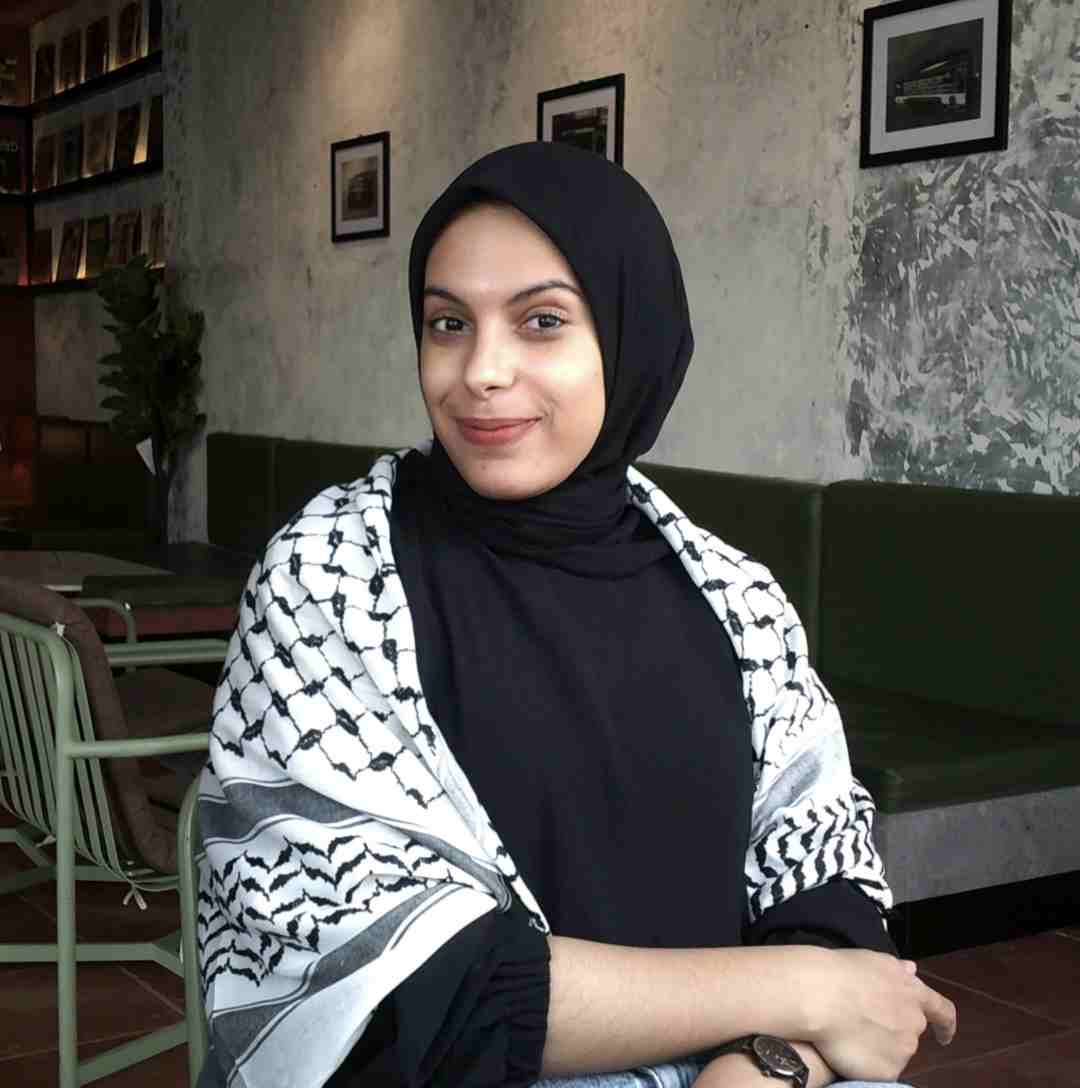

Oleh: Syahr Banu *)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Isu keperempuanan menjadi perbincangan yang hangat di sepanjang sejarah Indonesia, khususnya di Jawa. Dalam sejarahnya, perempuan kerap dimarginalkan karena patriarki berfungsi sebagai alat kapitalisme.
Perempuan harus berada di rumah menunggu suaminya pulang dan mengerjakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Budiman (Budiman, 1985, dalam Setiawan, 2018) bahwa seolah-olah peran perempuan sangatlah sempit yaitu hanya sebatas menikah dan berkeluarga.
Hal ini kemudian memunculkan sebuah anggapan dalam budaya Jawa bahwa pendidikan menjadi hal yang kurang penting bagi perempuan (Yuniarti, 2018). Bahkan anggapan bahwa perempuan tidak boleh berpendidikan juga masih dinormalisasikan pada era ini (Widyaningsih, 2010).
Tantangan dalam merubah paradigma dan perspektif terhadap perempuan sudah diupayakan sejak masa lalu oleh Raden Ajeng Kartini dalam memajukan pendidikan untuk perempuan, khususnya di Kabupaten Jepara.
Namun representasi Kartini tidak digambarkan secara menyeluruh dalam kumpulan surat yang ditulis oleh pengarang Hindia Belanda, sehingga kita hanya mengetahui dedikasi Kartini hanya sebatas dari 87 surat pribadi yang disunting oleh J.H., Abendanon (Carey, 2016).
Banyak bukti sejarah yang membahas bagaimana peran laki-laki memberikan dampak yang positif bagi sekitar, namun peran perempuan belum tersorot karena terbatasnya akses bagi mereka untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti laki-laki.
Dari pandangan sosial, perempuan digambarkan mempunyai badan yang lebih kecil, suara lembut dan kekuatan fisik yang lemah. Serta psikis, yang menggambarkan wanita sebagai sosok yang mudah menangis, lemah lembut dan tidak mempunyai keahlian dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang berat (Salamah & Seprina, 2022).
Perbedaan tersebut menjadi bukti bagaimana norma sosial memandang perempuan sebagai objek yang tidak berdaya dan membutuhkan sosok laki-laki di sepanjang hidupnya.
Secara kedudukan pun, selama masa penjajahan belum ada perubahan yang berarti. Keadaan perempuan pada kala itu juga berdampak pada mendorongnya praktik seperti poligami dan selir. Tragisnya, “konsep” Macak, Masak dan Manak, melekat pada diri perempuan.
Perilaku tersebut justru semakin menutup ruang gerak para perempuan untuk dapat keluar dari lingkungan sekitarnya—terutama terhadap akses pendidikan dan peran publik.
Dalam buku Ki Sigit Sapto Nugroho yang berjudul “Konco Wingking“, disebutkan bahwa wanita ideal pada jaman dulu digambarkan sebagai sosok yang baik hati, hemat, teliti, berhati-hati serta mampu hidup dalam keprihatinan.
Kepemimpinan perempuan dibatasi secara sistematik dengan menempatkan mereka secara simbolik dalam posisi yang dianggap aman sesuai dengan pandangan patriarkal dan kapitalistik. “Babad Dipanegara“, saksi bisu dalam perempuan Jawa memberikan kesan yang baik ke laki-laki yang ingin mempersuntingnya.
Tidak hanya dalam kepemimpinan, perempuan juga dipercaya dalam menunjukkan aktivitas yang biasa dilakukan laki-laki, seperti menunggang kuda, memegang senjata bahkan pelatihan militer lainnya—-pada era Mangkunegara I dimana sekumpulan perempuan mempunyai kelompok prajurit untuk membantu dalam berperang mengalahkan penjajah.
Pada masa pemerintahan Sultan Agung sudah terjadi pula peran perempuan sebagai prajurit namun belum sepenuhnya diresmikan atau belum terbentuk secara khusus pada tahun 1613-1646. (Kumar, 2008).
Ketika terjadi penjajahan di sekitar wilayah Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwana II yang juga merupakan Raja yang anti terhadap orang-orang Barat kemudian membentuk Kelompok Prajurit Perempuan dalam rangka penaklukan tanah Yogyakarta agar terlepas dari belenggu penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Inggris.
Pada masa itu, Sultan Hamengkubuwana II bahkan mengalami 3 kali penurunan tahta, dari 1792-1810, 1811-1812 dan 1826-1828 sebelum akhirnya meninggal dunia (Soebachman, 2016).
Keterlibatan perempuan di sekitar kraton awalnya hanya sebagai pengawal saja, bukan sebagai prajurit. Keinginan Hamengkubuwana II dalam menjadikan perempuan sebagai prajurit kraton karena laki-laki mempunyai sifat yang mudah memberontak.
Pandangan ini menunjukan bias gender yang melihat perempuan sebagai subjek yang penurut dan mudah dikendalikan. Padahal, kaum perempuan Jawa sejatinya mampu melakukan apapun dan kesempatan yang diberikan di bidang militer, ekonomi maupun politik (Yuliarni, dkk, 2020).
Perjuangan perempuan Jawa membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang sama seperti laki-laki dalam melindungi negara, Raja dan bahkan rakyat.
Pandangan bahwa perempuan lebih baik tinggal di rumah karena kapabilitas domestiknya dilanggengkan oleh sistem patriarki, membatasi peran perempuan hanya di ruang privat dan mengabaikan potensinya di ruang publik.
Meski norma patraiarkal membatasi peran perempuan, keterlibatan perempuan pada dunia perang secara aktif seringkali mendapat dukungan dari laki-laki namun tetap dalam kerangka kekuasaan.
Pendidikan menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan perempuan karena dengannya mereka dapat memahami dan mengelola persoalan mendasar seperti pangan, kesehatan, ekonomi, dan pengasuhan anak.
Budaya feodal Jawa masih menganggap perempuan tidak memeliki kebebasan untuk tampil dan menempatkan mereka pada posisi subordinat (Nur Urifatulailiyah, 2017).
Hal ini memperlihatkan bagaimana kebudayaan lokal pun bersinergi dengan sistem patriarki kolonial dan menekan perempuan. Padahal pendidikan adalah hak dasar setiap manusia, namun budaya justru menempatkan perempuan sebagai subjek yang lemah melalui pembatasan akses pendidikan.
Tahun 1799 menjadi momen penting perubahan kekuasaan VOC kepada Hindia Belanda karena kehancuran VOC akibat kas dan hutang. Terciptanya Tanam Paksa di zaman itu membuat pemerintah dipaksa untuk memberikan pendidikan kepada putra-putra Indonesia agar dapat menjaga ekonomi Hindia Belanda tetap stabil.
Oleh karenanya, pendidikan bagi perempuan tidak dibangun sama besarnya dengan pendidikan untuk laki-laki baik dari segi akses maupun tujuan karena pendidikan lebih di arahkan hanya untuk mendukung peran domestik pada sistem kolonial dan patriarkal. Namun pendidikan di masa itu hanya diperuntukkan bagi perempuan kalangan ningrat dan priyayi saja. (Adji, 2018).
Ketidakadilan terhadap perempuan lewat pendidikan ini tidak dapat menjawab posisi mereka sebagai manusia. Maka dari itu, pers maju sebagai jawaban atas berkurangnya peran perempuan dalam berbagai aspek. Inisiatif dimunculkan dari para golongan ningrat seperti RA Kartini yang perduli terhadap nasib dan pendidikan perempuan.
Pada masa kolonial, pers sebagai media penting yang digunakan perempuan elite untuk menyuarakan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Tulisan yang di muat dalam pers adalah bentuk suara abadi yang berbeda dengan orator bersuara lantang mengemukakan ide-idenya atau pandangan terhadap suatu masalah.
Karena norma sosial menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah lembut tentu tidak memilih menjadi orator demi menyadarkan perempuan dari ketertindasan budaya (Nur Urifatulailiyah, 2017).
Pada tatanan hirarki, patriarki tidak hanya berdiri sendiri namun ada sistem kapitalisme yang bekerja sama untuk memposisikan perempuan sebagai pekerja domestik tidak diupah, namun disingkirkan dari pengambilan keputusan. Beban perempuan pun sebanding dengan pekerjaan domestik dalam urusan rumah tangga.
Akibatnya, perempuan menanggung beban ganda (double burden) dalam urusan domestik dan publik. Sebuah konstruksi problematis ketika perempuan hebat dianggap sebagai perempuan dengan peran yang ganda sebagai ibu dan istri.
Inilah refleksi kapitalisme menduduki tingkat teratas mengontrol tatanan hidup perempuan ke level personal. Pilihan semu ini dibentuk oleh sistem dimana perempuan harus memilih antara berkarier atau menjadi ibu sepenuhnya. Kapitalisme membungkus dilema agar perempuan tetap harus memilih dan dikontruksi oleh sistem agama, sosial, dan dominasi laki-laki.
Seperti dicatat Nurul Hidayati (2015), pengaruh kapitalisme dalam upah perempuan dan lelaki menjadi tantangan yang besar bahwa upah perempuan yang lebih tinggi dari laki laki dipersepsikan sebagai ancaman terhadap dominasi laki-laki dalam berumah tangga.
Upah yang didapatkan menjadi indikator kelas sosial yang ada pada masyarakat. Norma sosial menciptakan ketimpangan jodoh, bahwa lelaki miskin tidak cocok bersanding dengan perempuan kaya atau sebaliknya. Tentu hal tersebut efek negatif dari sistem patriarki di mana lelaki dianggap lebih dominan dan akan selalu dianggap seperti itu.
Patriarki justru membuat laki-laki menjadi sosok yang harus dominan dan maskulin. Sedangkan tidak semua laki-laki memiliki sisi dominan secara ekonomi maupun rumah tangga. Terlepas dari realitas mereka sendiri, mereka adalah manusia yang dianggap sosial sebagai sosok yang kuat.
Sejarah perempuan Jawa menunjukan bagaimana patriarki dan kapitalisme mendominasi terhadap tubuh, pekerjaan dan pilihan hidup. Budaya Jawa, sistem kolonial dan pekerjaan membatasi gerak perempuan sebagai subjek yang utuh, karena dibayangi oleh dominasi laki-laki.
Pembacaan ulang terhadap sejarah perempuan menjadi penting dalam mengungkap ketimpangan yang terjadi pada masa lalu dan bagaimana ketimpangan terus diwariskan hingga saat ini. Perempuan terus-menerus terjebak dalam beban simbolik dan struktural yang tidak pernah mereka pilih. (Red)
*) Syahr Banu, pemerhati isu perempuan dan budaya, tinggal di Semarang