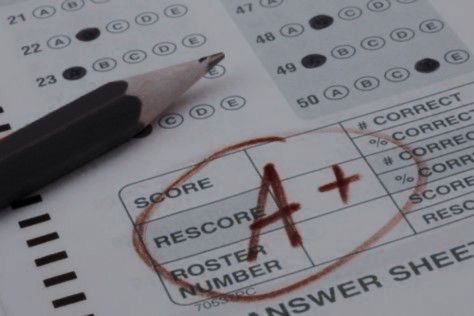Refleksi Kritis HUT Republik Indonesia ke-80


Oleh: Yohanes Soares*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Delapan puluh tahun yang lalu, pada 17 Agustus 1945, bangsa ini berdiri dengan penuh keberanian. Proklamasi dikumandangkan bukan hanya untuk memutus rantai penjajahan, tetapi juga untuk menegakkan martabat manusia Indonesia, menghadirkan keadilan, dan memastikan bahwa kemerdekaan adalah milik semua.
Kini, di tahun 2025, kita kembali memperingati hari yang sakral itu. Namun pertanyaan yang seharusnya menggema di benak kita adalah: apakah kemerdekaan itu sungguh telah kita nikmati, dan jika iya, merdeka untuk siapa?
Indonesia memang telah lama terbebas dari kolonialisme fisik, tetapi wajah penjajahan kini tampil dalam bentuk yang lebih halus: sistem yang menjerat rakyat kecil, kebijakan yang sering menindas, dan kesenjangan yang semakin melebar.
Pajak yang kian membebani, alih-alih menjadi instrumen pemerataan, justru menjadi alat yang mencekik masyarakat bawah. Konglomerat dengan mudah meloloskan diri dari kewajiban melalui celah hukum, sementara rakyat kecil dipaksa menanggung beban negara.
Rekening dorman milik masyarakat miskin diblokir oleh PPATK, seolah-olah mereka adalah pelaku kejahatan, padahal uang itu hanyalah hasil jerih payah yang disimpan seadanya. Bukankah ini sebuah ironi? Bukankah ini menjadikan rakyat korban dari sistem yang katanya demi kepentingan mereka?
Luka itu semakin dalam ketika kita menengok ke ruang-ruang kekuasaan. Pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut bahwa guru jangan berharap gaji dari pemerintah seolah menjadi tamparan keras bagi bangsa ini.
Bagaimana mungkin negara yang berdiri di atas amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa justru mengerdilkan peran guru, sang pilar pendidikan?
Demikian pula dengan ancaman Menteri yang menyatakan bahwa tanah rakyat yang tidak digunakan akan disita. Lagi-lagi, rakyat kecil yang paling terhimpit.
Sementara tanah luas milik korporasi dan pejabat tetap aman terlindungi. Hukum dan kebijakan kembali memperlihatkan wajahnya yang tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Kontras antara rakyat dan pemimpin makin terasa ketika gaya hidup glamor pejabat, baik menteri maupun anggota DPR, dipertontonkan di tengah rakyat yang berjuang untuk bertahan hidup.
Kemerdekaan, yang seharusnya dimaknai dengan kesederhanaan dan pengabdian, kini direduksi menjadi pesta pora, hedonisme, dan pencitraan semu.
Rakyat diminta mengencangkan ikat pinggang, sementara pemimpinnya justru berlomba-lomba memamerkan kekayaan. Apakah inikah wajah kepemimpinan yang kita wariskan di usia 80 tahun kemerdekaan?
Di luar persoalan moralitas elit, refleksi ini juga menyingkap ketimpangan ekonomi yang nyata di bumi nusantara. Pertumbuhan dan kestabilan ekonomi di tiap daerah masih jauh dari merata.
Ada daerah yang berkembang pesat, namun tidak sedikit pula yang tertinggal dan kesulitan menjaga stabilitas perekonomiannya. Kebutuhan dasar seperti bahan pokok dan sumber daya masih sulit dipenuhi, khususnya di wilayah Indonesia timur.
Salah satu penyebab utama adalah distribusi yang timpang, di mana biaya transportasi yang mahal, terutama jalur udara menjadi hambatan serius. Ironisnya, tiket penerbangan domestik kerap kali lebih mahal daripada penerbangan internasional.
Akibatnya, rakyat di daerah terpencil harus membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk kebutuhan sehari-hari dibandingkan saudara mereka di Pulau Jawa.
Padahal, bila konsistensi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga pemerataan pembangunan sungguh dijalankan, ketimpangan ini bisa ditekan. Pertumbuhan ekonomi yang adil di seluruh wilayah akan langsung menunjang kesejahteraan rakyat.
Maka persoalan ini bukan sekadar teknis distribusi, tetapi menyangkut komitmen: apakah pemerintah sungguh serius membangun Indonesia secara utuh, ataukah hanya mementingkan pusat kekuasaan dan daerah-daerah strategis?
Maka tidak berlebihan bila kita menyebut bahwa Indonesia hari ini sedang mengalami krisis moral dan krisis kepemimpinan, sekaligus krisis pemerataan pembangunan.
Delapan puluh tahun seharusnya menjadi usia kematangan bangsa, namun kita masih berkutat pada persoalan lama: korupsi yang merajalela, penyalahgunaan wewenang, jurang pemisah antara kaya dan miskin, serta ketidakadilan antara pusat dan daerah.
Jika kemerdekaan hanya berarti kebebasan segelintir elit untuk hidup berlebihan, sementara mayoritas rakyat bergulat dengan kebutuhan pokok dan daerah-daerah tertentu terus tertinggal, maka sesungguhnya kemerdekaan itu telah kehilangan maknanya.
Namun, refleksi ini tidak boleh berakhir dalam kegelapan. Harapan masih ada, dan harapan itu selalu lahir dari rakyat. Sejarah bangsa ini membuktikan, ketika elit tidak berpihak, rakyatlah yang bergerak. Solidaritas, gotong royong, dan kreativitas adalah modal sejati bangsa Indonesia.
Kemandirian rakyat harus diperkuat: jangan menunggu perubahan dari atas, tetapi menciptakan gerakan dari bawah. Rakyat berhak menuntut pemimpin yang jujur, sederhana, dan berpihak, karena pemimpin sejati adalah mereka yang hidup selaras dengan penderitaan rakyat, bukan yang hidup di atas menara gading kekuasaan.
HUT RI ke-80 ini bukan sekadar seremoni, parade, atau pesta kembang api. Ia adalah momen refleksi nasional, sebuah cermin untuk menilai apakah kita masih setia pada cita-cita proklamasi atau sudah jauh menyimpang.
Delapan puluh tahun lalu, bangsa ini merdeka karena keberanian rakyat melawan penindasan. Delapan puluh tahun kemudian, tantangan kita adalah melawan penindasan dalam wajah baru: keserakahan elit, kebijakan yang timpang, sistem yang tidak adil, serta ketidakmerataan pembangunan yang mengorbankan saudara-saudara kita di daerah.
Jika kita tidak berani mengoreksi arah perjalanan bangsa, kemerdekaan akan tinggal slogan kosong. Tetapi jika rakyat mau bangkit, menegakkan kembali nilai keadilan, gotong royong, pemerataan, dan keberanian, maka makna kemerdekaan itu akan kembali hidup.
Sebab kemerdekaan sejati adalah ketika setiap rakyat merasa dilindungi, dihargai, dan diberi kesempatan yang sama untuk hidup layak, baik di Jakarta maupun di Papua, baik di Jawa maupun di NTT.
Dan pada titik itulah, kemerdekaan akan benar-benar menjadi milik semua, bukan hanya milik segelintir orang.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Merdeka untuk semua! (Red)
*) Yohanes Soares, aktivis sosial dan peneliti kebijakan pendidikan dan masyarakat daerah tertinggal; mahasiswa S3 Universitas Dr. Soetomo Surabaya