

PBB dan Beban Rakyat


Oleh: Yanuar Rachmansyah*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang dikenakan kepada warga atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan.
Dalam konteks otonomi daerah, PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah dialihkan pengelolaannya ke pemerintah kabupaten/ kota sejak tahun 2014, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Artinya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran tarif, nilai jual objek pajak (NJOP), dan kebijakan lainnya yang menyangkut PBB. Namun, dalam praktiknya, kewenangan ini justru kerap menjadi ironi tersendiri.
Di banyak daerah, alih-alih menyesuaikan tarif PBB secara bijak dan bertahap, kebijakan yang diambil justru menyebabkan lonjakan tagihan yang tidak masuk akal dan memberatkan rakyat kecil.
Dua kasus nyata yang menjadi sorotan publik belakangan ini adalah kenaikan signifikan PBB di Kabupaten Pati.
Kasus Solo dan Pati: Antara Pendapatan Daerah dan Beban Masyarakat
Berkaca kasus di Kota Solo tahun 2023 , Pemkot Solo sempat menaikkan NJOP dan tagihan PBB hingga mencapai 200–300 % lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, seperti pada kasus warga Kec. Gilingan yang tagihannya melonjak dari Rp 728.605 menjadi Rp 2.223.364.
Publik bereaksi keras melalui saluran aduan ULAS, DPRD Fraksi PDIP turun tangan, dan akhirnya Wali Kota Gibran (kala itu, red) membatalkan kenaikan itu serta menjanjikan restitusi bagi warga yang sudah membayar sesuai ketetapan baru.
Kini, hal serupa juga terjadi di Kabupaten Pati. Kebijakan Bupati Pati menaikkan PBBP2 hingga 250 % menuai kritik tajam karena dianggap melanggar Perda No. 1/2024 serta prinsip konstitusi dan asas pemerintahan yang baik.
Forum kajian hukum menilai bahwa peningkatan tersebut tidak berdasar kajian mendalam dan tidak didialogkan dengan publik. Padahal, kenaikan PBB di sejumlah kecamatan telah memicu protes warga, terutama dari kalangan petani dan pedagang kecil.
Mereka merasa bahwa beban pajak kini tidak lagi berbanding lurus dengan kemampuan ekonomi mereka. Apalagi, tidak ada jaminan bahwa pelayanan publik membaik seiring dengan meningkatnya pungutan.
Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa meskipun sah secara hukum, kebijakan kenaikan PBB yang dilakukan tanpa pendekatan sosial dan partisipatif justru menciptakan ketimpangan baru di masyarakat. Pemerintah daerah seakan abai terhadap prinsip keadilan sosial dalam pemungutan pajak.
PBB: Fungsi Fiskal vs Fungsi Sosial
Dalam teori perpajakan, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal (sumber penerimaan), tetapi juga sebagai instrumen sosial.
Artinya, pajak harus memperhatikan prinsip keadilan, daya dukung masyarakat, serta keberlanjutan ekonomi lokal.
Jika kebijakan PBB hanya di arahkan untuk mendongkrak PAD tanpa mempertimbangkan aspek kemampuan bayar (ability to pay), maka fungsinya sebagai pajak yang adil patut dipertanyakan.
Sebagai contoh, Pasal 95 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penetapan tarif pajak.
Pemerintah tidak bisa serta-merta menaikkan NJOP atau tarif PBB tanpa mekanisme yang transparan, adil, dan berpihak pada rakyat.
Menata Ulang dengan Prinsip Berkeadilan
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara sepihak dan drastis, sebagaimana terjadi di di Kabupaten Pati sekarang ini (2025) dan berkaca dari Kota Solo pada tahun 2023 menunjukkan pentingnya penataan ulang kebijakan fiskal daerah dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial.
PBB sebagai instrumen penerimaan daerah tidak boleh dijalankan semata demi target pendapatan, melainkan harus mencerminkan kemampuan bayar masyarakat serta memperhatikan dampak sosial-ekonomi dari setiap kebijakan.
Prinsip berkeadilan dalam pengelolaan PBB harus dimulai dengan penerapan regulasi yang sah dan akuntabel, yaitu melalui peraturan daerah (Perda), bukan sekadar keputusan kepala daerah.
Proses legislasi ini harus terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak. Hal ini agar ada ruang kritik, penyesuaian, dan kompromi.
Pada Kasus Kota Solo tahun 2023 , di mana pemerintah akhirnya membatalkan kenaikan setelah tekanan publik, menjadi contoh bahwa keputusan yang tidak berbasis partisipasi cenderung tidak berkelanjutan dan melemahkan legitimasi pemerintah.
Selanjutnya, kebijakan PBB harus mempertimbangkan aspek pemerataan dan proteksi terhadap kelompok rentan.
Masyarakat seperti pensiunan, buruh harian, petani, pelaku UMKM, dan warga lanjut usia yang tinggal di wilayah dengan kenaikan nilai tanah perlu diberikan insentif, keringanan, atau pembebasan pajak.
Hal ini sesuai dengan semangat UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang menegaskan bahwa pajak daerah harus menjamin kepastian hukum dan keadilan.
Harusnya Lebih Bijak
Kasus Solo (2023) menunjukkan bahwa pemimpin daerah yang responsif dapat membatalkan kenaikan yang kontroversial, sedangkan di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa kenaikan tanpa legitimasi hukum dan kajian mendalam dapat berujung pada protes dan potensi gugatan hukum.
Sebaiknya, arah pengelolaan PBB di era sekarang bergerak menuju sistem yang adil, partisipatif, berkeadilan sosial, dan transparan—di mana pajak bukan beban, melainkan kontribusi yang dirasakan manfaatnya oleh warga.
Ke depan, kebijakan PBB perlu di arahkan dengan lebih bijaksana. Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi NJOP secara partisipatif dan transparan.
Bukan hanya berbasis pada harga pasar, tetapi juga memperhitungkan kemampuan bayar masyarakat serta memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti lansia, pensiunan, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak lonjakan nilai tanah akibat pembangunan.
Di samping itu, perlu sekiranya mengembangkan skema insentif atau pembebasan pajak bagi pelaku UMKM atau pemilik lahan produktif yang mendukung ketahanan pangan.
Keadilan fiskal bukan hanya soal angka, tetapi soal rasa keadilan yang dirasakan masyarakat. PBB tidak boleh menjadi instrumen yang justru meminggirkan rakyat dari tanah dan rumahnya sendiri.
Saatnya kebijakan perpajakan di arahkan kembali pada fungsinya yang utama: membangun tanpa menyakiti. Kebijakan PBB yang dilaksanakan secara sepihak tanpa dasar kajian sosial-ekonomi dan tanpa dialog publik justru berpotensi menimbulkan beban tak proporsional bagi rakyat kecil. (Red)
*) Yanuar Rachmansyah, dosen Universitas BPD Semarang dan pengamat kebijakan ekonomi

One thought on “PBB dan Beban Rakyat”
Tinggalkan Balasan








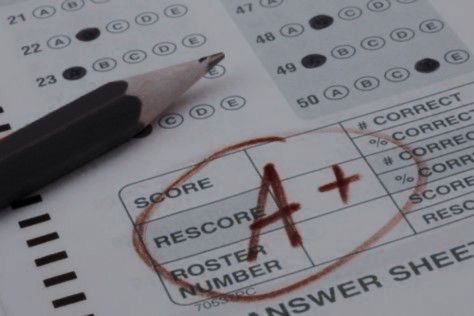











https://m.tribunnews.com/amp/regional/2025/08/12/nenek-69-tahun-di-semarang-kaget-dapat-tagihan-pbb-naik-441-persen