

385 Tahun Kabupaten Bima: Warisan Monarki di Negeri yang Baru Merdeka


SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Tulisan ini berawal dari pertanyaan yang muncul ditengah upaya saya dalam menyusun opini yang berjudul “Pemuda Bima Itu Negarawan” sebagai refleksi menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Tahun 2025 yang ke-80.
Dalam proses mencari inspirasi dan menggali gagasan tentang semangat kebangsaan generasi muda Bima.
Pandangan saya tertuju pada pamflet yang mengumumkan Perayaan Hari Jadi Kabupaten Bima yang ke-385. Spontan saya terdiam dan bertanya dalam hati: Bagaimana mungkin sebuah kabupaten di dalam NKRI bisa lebih tua dari negara itu sendiri?
Pertanyaan sederhana bernada gurauan itu justru menjadi pemicu perenungan serius tentang aspek legalitas dan logika dalam penetapan hari jadi daerah, yang kemudian coba saya tuangkan dalam opini ini.
Pada 5 Juli 2025 lalu, Kabupaten Bima secara resmi telah memperingati hari jadinya yang ke-385. Kenapa ke-385? Keputusan itu didasari pada momentum penobatan Sultan Abdul Kahir di tahun 1640 sebagai raja pertama Kesultanan Bima.
Penetapan ini telah dituangkan dalam peraturan daerah dan dirayakan tiap tahun secara besar-besaran, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
Kesultanan Bima: Sejarah Budaya, Bukan Legalitas Pemerintahan
Tidak dapat disangkal bahwa Bima secara historis memiliki jejak peradaban dan sistem pemerintahan lokal yang panjang sebelum kemerdekaan Indonesia.
Namun, kesultanan yang berdiri tahun 1640 tidak bisa disamakan dengan entitas pemerintahan kabupaten dalam negara republik.
Sistem pemerintahan pada masa kesultanan bersifat monarki teokratik dan tidak memiliki kesinambungan yuridis ke dalam sistem pemerintahan yang lahir pasca-Proklamasi 1945.
Benar bahwa kesultanan Bima berdiri pada abad ke-17 dan memainkan peran penting dalam sejarah kawasan timur Indonesia. Namun, Kesultanan bukanlah Kabupaten dan daerah swapraja bukanlah bentuk pemerintahan otonom dalam bingkai NKRI.
Kesultanan Bima resmi diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia pada 1950 dan sejak itulah kita mengenal entitas bernama Kabupaten Bima seperti hari ini, lengkap dengan perangkat hukum, struktur pemerintahan serta konstitusi nasional.
Lebih jauh, pengakuan terhadap “Hari Jadi Kabupaten Bima” berdasarkan momen penobatan raja atau sultan pertama dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintahan daerah saat ini memiliki legitimasi yang mendahului dan bahkan berdiri terpisah dari Republik Indonesia.
Ini bukan soal adanya upacara bendera dalam perayaan sebagai sikap patriotisme semata, bukan juga banyak daerah yang menetapkan hari jadinya berdasarkan peristiwa sejarah lokal yang lebih awal dari pembentukan administratif (preseden nasional).
Tapi lebih pada kehawatiran potensi yang menimbulkan kerancuan dalam pemahaman publik tentang sejarah kewarganegaraan, identitas hukum dan struktur pemerintahan yang sah.
Menghargai Sejarah, Tapi Tidak Melanggar Logika Administratif
Setiap daerah memiliki hak untuk mengenang sejarahnya. Namun ketika narasi sejarah masuk ke ruang hukum formal seperti penetapan Hari Jadi melalui Peraturan Daerah, maka yang dibutuhkan bukan sekadar rasa bangga, tetapi juga ketelitian dan “kejujuran konstitusional”.
Kabupaten Bima saat ini secara administratif dan hukum dibentuk melalui proses pembentukan daerah pasca kemerdekaan Indonesia. Artinya, sebagai bagian dari Republik Indonesia, kabupaten Bima baru sah berdiri sejak tahun 1950, bukan 1640.
Maka, ketika pemerintah daerah menetapkan dan merayakan hari jadi ke-385 pada tahun 2025, ada yang perlu kita renungkan secara kritis.
Memang benar bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan hari jadi melalui Peraturan Daerah (Perda). Namun, kewenangan ini tetap berada dalam kerangka hukum nasional.
Ketika pemerintah daerah menyatakan bahwa wilayahnya “berusia 385 tahun”, secara yuridis tidak ada dasar hukum yang mengakui keberlangsungan administratif suatu wilayah sejak era kesultanan ke dalam sistem negara republik.
Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai regulasi turunannya tidak mengakomodasi kesinambungan hukum dari entitas pra-kemerdekaan ke dalam sistem pemerintahan daerah saat ini.
Jika hari jadi suatu kabupaten dihitung sejak era kerajaan, maka muncul pertanyaan hukum, apakah pemerintahan kabupaten tersebut eksis sebelum Indonesia merdeka? Jawabannya jelas: tidak.
Maka, klaim usia 385 tahun oleh sebuah kabupaten administratif bersifat ahistoris secara yuridis dan menyesatkan secara konstitusional.
Oleh sebab itu, menafsirkan usia kabupaten Bima sejak tahun 1640, berpotensi menyesatkan publik dan generasi muda. Ini seakan menyamakan kerajaan dengan pemerintahan demokratis, yang jelas sangat berbeda dari sisi hukum, struktur, dan filosofi.
Risiko Distorsi Sejarah dan Kesadaran Konstitusional
Perayaan hari jadi yang mengangkat masa kesultanan sebagai dasar legitimasi pemerintahan daerah beresiko menimbulkan distorsi kesadaran konstitusional di tengah masyarakat.
Hal ini bisa memicu kesalahpahaman seolah-olah daerah tersebut memiliki otonomi asal-usul yang mendahului dan berdiri terpisah dari negara Indonesia.
Dari sudut pandang hukum positif peting untuk ditegaskan, struktur pemerintahan kabupaten Bima sebagai entitas administratif baru diresmikan dan sah terbentuk setelah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 dikeluarkan, yang membentuk Daerah Tingkat II di wilayah Provinsi Nusa Tenggara BaratBarat.
Sejak itulah, Bima memperoleh dasar hukum formal sebagai kabupaten dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Solusi: Pisahkan Sejarah Budaya dan Legitimasi Pemerintahan
Pemerintah kabupaten Bima dan masyarakat tentu berhak merayakan sejarah panjang wilayahnya. Namun perayaan itu seharusnya diletakan dalam konteks budaya dan edukasi sejarah, bukan sebagai usia formal pemerintahan daerah.
Tanpa kejelasan pembatas antara nilai historis dan nilai legal, kita berisiko membangun narasi-narasi romantik masa lalu yang justru berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum modern.
Rasanya penting bagi pemerintah daerah untuk tidak mencampuradukkan antara identitas budaya dengan status hukum beradministrasi. Memperingati sejarah kesultanan Bima boleh dan patut sebagai penghargaan terhadap masa lalu.
Oleh karena itu, Hari jadi administratif Kabupaten Bima seharusnya dihitung sejak ditetapkannya UU pembentukan daerah pada tahun 1958.
Adapun momen 1640 bisa tetap dikenang dan diperingati dalam ranah sejarah lokal sebagai bagian dari warisan budaya yang memperkaya identitas Bima dalam bingkai NKRI.
Usulan Perda Alternatif : Dualisme Hari Penting Daerah
Penulis mengusulkan agar DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima mengkaji ulang Perda tentang Hari Jadi Kabupaten Bima dengan pendekatan yang lebih rasional dan akomodatif terhadap sejarah.
Berikut bentuk alternatif yang lebih jujur dan berimbang menurut penulis. Pertama, Hari Jadi Kabupaten Bima secara administratif ditetapkan 8 Agustus 1950 (berdasarkan UU pembentukan daerah).
Kedua, tanggal 5 Juli 1640 tetap diakui sebagai Hari Lahir Kesultanan Bima, dan dijadikan Hari Sejarah Lokal atau Hari Warisan Budaya Bima, bukan Hari Jadi Kabupaten.
Ketiga, Pemerintah tetap boleh memperingati dua momen ini, tapi dengan pembedaan istilah dan konteks hukum yang tegas.
Dengan langkah ini, kita tidak menghapus sejarah. Kita tetap menghormati leluhur dan warisan Bima, tapi juga tetap jujur pada fakta hukum dan sejarah kenegaraan.
Penutup
“Pikiran bukanlah aib yang harus ditutupi, setiap pikiran harus diungkapkan. Karena, untuk memahami kebenaran terdapat banyak tahapan yang harus di lalui, di saat itu proses adalah pembelajaran dan pada akhirnya menjadi tempat pematangan diri, hingga kita dapat mengetahui mana yang salah dan mana yang benar.”
Bangga terhadap sejarah adalah hal baik. Tetapi pengelolaan sejarah dalam kerangka hukum publik harus cermat dan proporsional, agar tidak menciptakan konflik antara narasi lokal dan sistem hukum nasional.
Sebab dalam negara hukum, semua bentuk pemerintahan harus berdiri atas dasar legalitas yang sah, bukan sekadar romantisme masa lalu. (Red)
*) Penulis: Arief Rachman, seorang pegiat literasi Nusa Tenggara Barat dan aktivis pada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

One thought on “385 Tahun Kabupaten Bima: Warisan Monarki di Negeri yang Baru Merdeka”
Tinggalkan Balasan




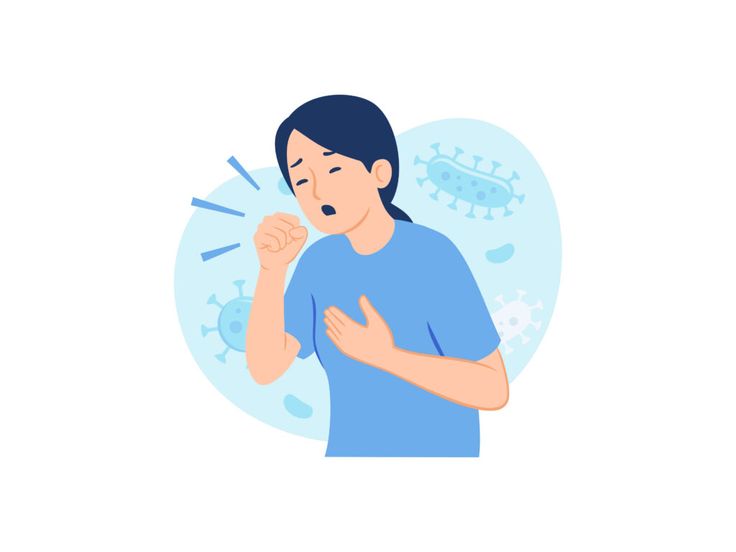




















Keren sekali tulisan semetonku🤟🏻🤘🏻