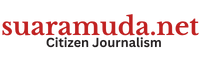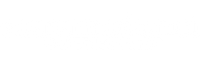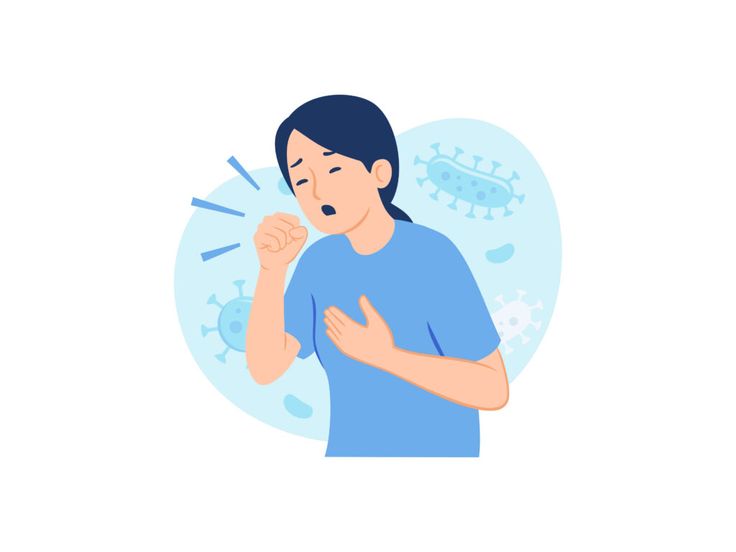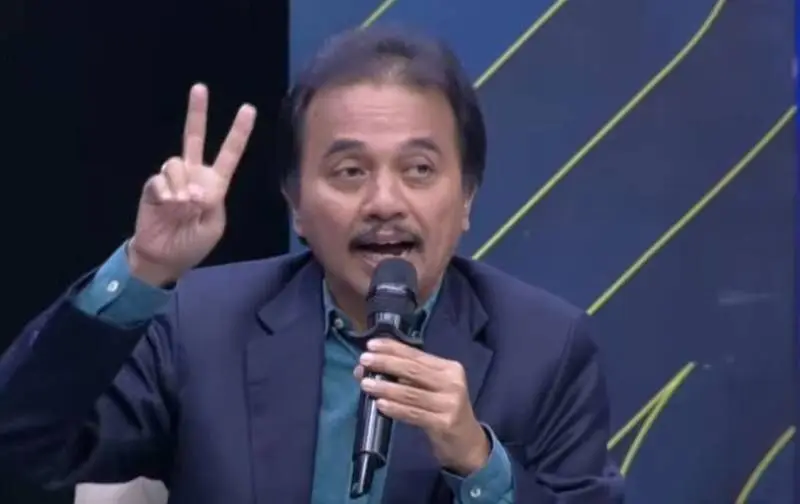Dualisme Perlawanan Trunojoyo: Antara Tindakan Kepahlawan Atau Pemberontakan


Oleh Busairi Yanto*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Mula-mula saya akan mengulang apa yang di ungkapkan Sartono Kartodirdjo, baginya penulisan sejarah Indonesia sentris tidak serta merta membalikkan sejarah masa kolonial. Artinya, mereka yang dianggap melawan pemerintah kolonial belum tentu bisa dijadikan tokoh nasional atau pahlawan begitu saja.
Demikian pula yang dialami Raden Trunojoyo, pengajuan gelar pahlawannya dari 1967 lalu hingga hari ini terus terganjal oleh narasi pemberontak. Tapi apakah narasi pemberontak itu benar adanya ataukah hanya tuduhan serampangan yang bersumber dari sejarah versi kolonial.
Untuk menjawabnya, kita harus terlebih dahulu melihat kondisi sosial dan politik Mataram pada waktu itu. Karena, dengan begitu kita akan mengetahui mengapa Raden Trunojoyo sampai melakukan perlawanan terhadap Mataram dan tentu saja kita akan bisa menilai Trunojoyo layak disebut sebagai pahlawan atau justru pemberontak?
Perlawanan yang dilakukan oleh Raden Trunojoyo tidak terlepas dari satu tokoh kunci yakni raja Amangkurat I, kebijakan-kebijakannya yang dinilai lalim merupakan motivasi utama munculnya perlawanan.
Oleh karenanya kita terlebih dahulu harus menyelidiki bagaimana sistem pemerintahan pada masa Amangkurat I sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada perlawanan yang dilakukan pangeran Trunojoyo.
Berbeda dengan pendahulunya, Sultan Agung, yang bijaksana dan terkenal keras terhadap Belanda (VOC), Amangkurat I justru sebaliknya. Dia adalah raja yang lalim dan kebijakan-kebijakannya pun sangat bertentangan dengan penguasa sebelumnya. Ia bersikap lunak dan banyak menguntungkan VOC.
Sebetulnya sejak awal pengangkatan Amangkurat I sebagai raja sudah cukup problematik dan memunculkan banyak ketidakpuasan dikalangan keluarga kraton karena ternyata Ki Arya Mataram sebelum bergelar Amangkurat I, bukanlah putra tertua Sultan Agung melainkan putranya yang kesepuluh atau anak kedua dari istrinya yang kedua yakni yakni Raden Ayu Wetan. Tapi entah mengapa Sultan Agung memilihnya sebagai raja.
Pada awal pemerintahannya, Amangkurat I sudah menunjukkan sikap sewenang-wenang dan perangai yang kurang baik. Ini sebagaimana digambarkan oleh Ricklefs dalam tulisannya, “program pokok pemerintahnya adalah usaha mengkonsolidasikan kerajaan Mataram, mensentralisasikan administrasi dan keuangan serta menumpas semua perlawanan. Dia ingin mengubah kerajaan yang telah didasarkan oleh Sultan agung pada kekuatan militer dan kemampuan untuk memenangkan atau melaksanakan suatu mufakat menjadi suatu kerajaan yang bersatu dengan sumber-sumber pendapatannya dimonopoli untuk kepentingan raja.”
Disisi lain Amangkurat I adalah raja yang memiliki sifat paranoid, ia banyak menyingkirkan orang-orang yang dinilainya tidak loyal kepadanya.
Banyak pejabat-pejabat kerajaan yang kemudian disingkirkan dengan cara dibunuh karena dinilai tidak setia. Salah satu yang menjadi korban adalah Tumenggung Wiraguna, ia disingkirkan dengan dalih tidak menjalankan tugas dengan baik.
Selain itu Amangkurat I juga dinilai anti Islam karena pada masa pemerintahannya ia banyak menyingkirkan (membunuh) pemuka agama karena ditengarai terlibat dalam pemberontakan Pangeran Alit.
De Graaf mengenai perintah Amangkurat ini menulis dalam bukunya “jangan seorangpun dari apa yang disebut sebagai pemuka agama dalam seluruh penjuru Mataram luput dari pembunuhan.”
Pada masa Amangkurat I, Mataram mulai melunak dengan Belanda dalam hal ini VOC. Kisaran tahun 1646, 1648, 1649 dan 1651 berturut-turut kompeni Belanda mengirimkan utusannya. Dan pada perutusan yang terakhir, Amangkurat I memberikan izin terhadap kompeni Belanda untuk mendirikan ‘Loji’ di semua pelabuhan lautnya—-bahkan raja bersedia menyediakan tanahnya.
Sejak adanya kebijakan ini ruang gerak kompeni menjadi semakin besar dan mereka mulai bertingkah bebas di daerah pesisir. Akibatnya, menimbulkan sikap tidak senang dari pihak-pihak yang anti kompeni.
Untuk menjaga hubungan baik dengan pihak kompeni, Amangkurat I melakukan monopoli perdagangan beras dan melarang rakyatnya untuk melakukan perdagangan keluar Jawa.
Burger menegaskan bahwa pada tahun 1659 raja telah mengadakan kebijaksanaan sebagai berikut : “Raja Mataram telah melarang rakyatnya melakukan perdagangan laut. Raja mengambil alih perdagangan luar negeri untuk dirinya sendiri. Tak seorangpun rakyat diperbolehkan mendapatkan keuntungan dari perdagangan itu. Monopoli raja ditetapkan atas beras. Orang partikelir yang mengekspor beras akan dihukum mati.”
Tentu dengan adanya kebijakan monopoli ini posisi tawar Amangkurat I terhadap VOC menjadi semakin tinggi. Hal itu, karena pada waktu pengadaan pangan VOC yang berpusat di Batavia sangat bergantung pada Mataram.
Sehingga dengan monopoli ini, hanya pihak keraton-lah,—-dalam hal ini Amangkurat I—-yang bisa berhubungan atau berdagang dengan kompeni. Namun akibatnya, rakyat terutama para pedagang menjadi menderita.
Putra Mahkota dalam Pusaran Perlawanan
Menjelang tahun-tahun terakhir meletusnya perlawanan Trunojoyo, Raja Amangkurat I semakin di luar kendali. Banyak tindakan-tindakannya yang merugikan rakyat. Pada waktu itu pula, rakyat dibebankan dengan pajak yang tinggi, diharuskan menyerahkan jiwa dan raganya ketika terjadi perang, serta harus menyerahkan harta bendanya bahkan anak istrinya jika dikehendaki raja.
Setiap orang bisa ditangkap, dipenjara maupun dibunuh beserta keluarganya. Setiap saat rakyat dibayang-bayangi oleh rasa tertekan dan ketakutan akan hukuman mati.
Pada tahun-tahun itu juga hubungan antara Mas Rahmat Sebagai Adipati Anom (putra mahkota) dengan ayahandanya raja Amangkurat I menjadi semakin renggang dan bergulir pada isu penggantian putra mahkota kepada salah satu putra Amangkurat yang lain yakni Pangeran Singasari.
Peristiwa Rara Oyi yang berujung pada dibunuhnya pangeran Pekik (mertua Amangkurat I) beserta 40 orang keluarganya merupakan titik memanasnya hubungan antara Amangkurat I dengan putranya Adipati Anom.
Dalam ‘Serat Trunojoyo‘, diceritakan bahwa Adipati Anom tertarik dengan seorang gadis bernama Rara Oyi, namun ternyata gadis itu akan dipersembahkan kepada ayahandanya yakni Amangkurat I.
Singkat cerita, atas dasar campur tangan Pangeran Pekik, akhirnya Adipati Anom berhasil memperoleh gadis itu. Namun setelah mendengar Rara Oyi diambil Adipati Anom, Raja Amangkurat I menjadi murka dan membunuh mertuanya.
Semenjak peristiwa itu, ‘Babad Tanah Jawi’ menjelaskan bahwa tindakan raja berubah 180 derajat, dia semakin lalim dan sewenang-wenang serta semakin tak terlihat darinya sifat keagungan seorang raja.
Suara tidak senang terhadap Amangkurat I semakin lama kian banter di seantero Mataram. Banyak kerabat keraton dan para bupati yang membujuk Adipati Anom untuk mengambil alih kekuasaan dari ayahandanya—-supaya rakyat Mataram manjadi pulih dan tenteram kembali hidupnya.
Pada awalnya Adipati Anom masih bergeming, hingga akhirnya ia memutuskan untuk bertemu dengan Raden Kajoran yang berujung pada dikenalkannya Adipati Anom dengan menantu Raden Kajoran yakni Raden Trunojoyo.
Peran Kunci Trunojoyo dan Motif Munculnya Perlawanan
Raden Trunojoyo lahir di Desa Pababaran, Kabupaten Sampang pada tahun 1649. Ayahnya bernama Raden Demang Melayakusuma, putra dari Cakraningrat I dari seorang selir. Ibu dari Pangeran Trurnojoyo adalah seorang putri yang masih keturunan Jokotole.
Pada usia tujuh tahun ayah Pangeran Trunojoyo yakni Demang Melayakusuma terbunuh di istana Mataram, yakni pada saat terjadi pemberontakan pangeran Alit.
M.C Ricklefs dalam bukunya “Sejarah Indonesia Modern” mengatakan bahwa cukup banyak alasan bagi Trunojoyo untuk melakukan perlawanan terhadap Amangkurat I, selain karena ayahnya yang dibunuh pada 1656 dan keterancaman jiwanya sendiri dalam persekongkolan jahat istana Mataram saat itu.
Trunojoyo juga menilai bahwa kekuasaan Mataram di Madura dan beberapa wilayah di Jawa merupakan bentuk penjajahan. Anggapan Trunojoyo yang menilai kekuasaan Mataram sebagai bentuk penjajahan rasa-rasanya cukup masuk akal karena selain pada waktu itu Amangkurat I melakukan persekutuan dengan VOC, yang berakibat pada semakin kuat dan meluasnya cengkeraman VOC.
Pada waktu itu, VOC juga banyak mendirikan pos-pos dagang di wilayah kekuasaan Mataram dan dalam banyak literatur menyebutkan bahwa mereka menggunakan pendekatan represif dan militeristik terhadap warga pribumi.
Sejak Madura jatuh ke tangan Mataram pada 1624, setidaknya tak kurang dari 40.000 orang Madura tua ataupun muda dibawa secara paksa oleh Pemerintah Mataram ke daerah-daerah yang jarang penduduknya.
Sedangkan penduduk yang tidak dibawa, mereka dibebani dengan berbagai macam pajak yang cukup tingggi, maka tak ayal jika Pangeran Trunojoyo menilainya sebagai bentuk penjajahan.
Puncaknya pada 1670 saat Adipati Anom bertemu dengan Raden Trunojoyo yang menghasilkan kesepakatan pesekongkolan untuk melakukan pemberontakan terhadap Raja Amangkurat I.
Dengan bermodal kekuatan dari laskar-laskar Madura dan dukungan pasukan Makassar dibawah pimpinan Kraeng Galesong, Raden Trunojoyo mulai melancarkan perlawanan pada 1675 dengan berhasil menduduki berbagai wilayah di Jawa Timur seperti Surabaya, Gresik, Sedayu hingga Lasem.
Puncaknya pada 1677, Kraton Mataram berhasil dikuasai Raden Trunojoyo dan memaksa Raja Amangkurat I untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, Amangkurat I meninggal dunia dan dimakamkan di Tegal Wangi,—-yang sebelum mangkat, dia menunjuk Adipati Anom sebagai gantinya dengan gelar Amangkurat II.
Setelah naik tahta, Amangkurat II justru berbalik memusuhi Trunojoyo dan melancarkan serangan balik. Dengan dukungan dari tentara VOC, perlawanan Pangeran Trunojoyo akhirnya dapat ditumpas, dan Pangeran Trunojoyo sendiri tertangkap lalu dibunuh oleh Amangkurat II.
Dari fakta-fakta sejarah di atas, maka jelas kata ‘pemberontak’ sangat tidak pantas disematkan kepada sosok Pangeran Trunojoyo. Karena sejatinya, ia telah malakukan perlawanan terhadap penjajah dan peminpin lalim yang sewengan-wenang.
Maka dari itu, dugaan kuat mengapa Pangeran Tronojoyo belum mendapatkan gelar pahlawan adalah adanya Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta yang kerap kali dijadikan simbol kekuasaan raja Jawa, sedangkan keduanya merupakan pecahan dari Mataram di masa lalu. (Red)
*) Penulis: Busairi Yanto, adalah mahasiswa asal Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumenep Madura. Ia menempuh S-1 Prodi Akuntansi pada Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, serta aktif dalam organisasi HMI dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Umum.