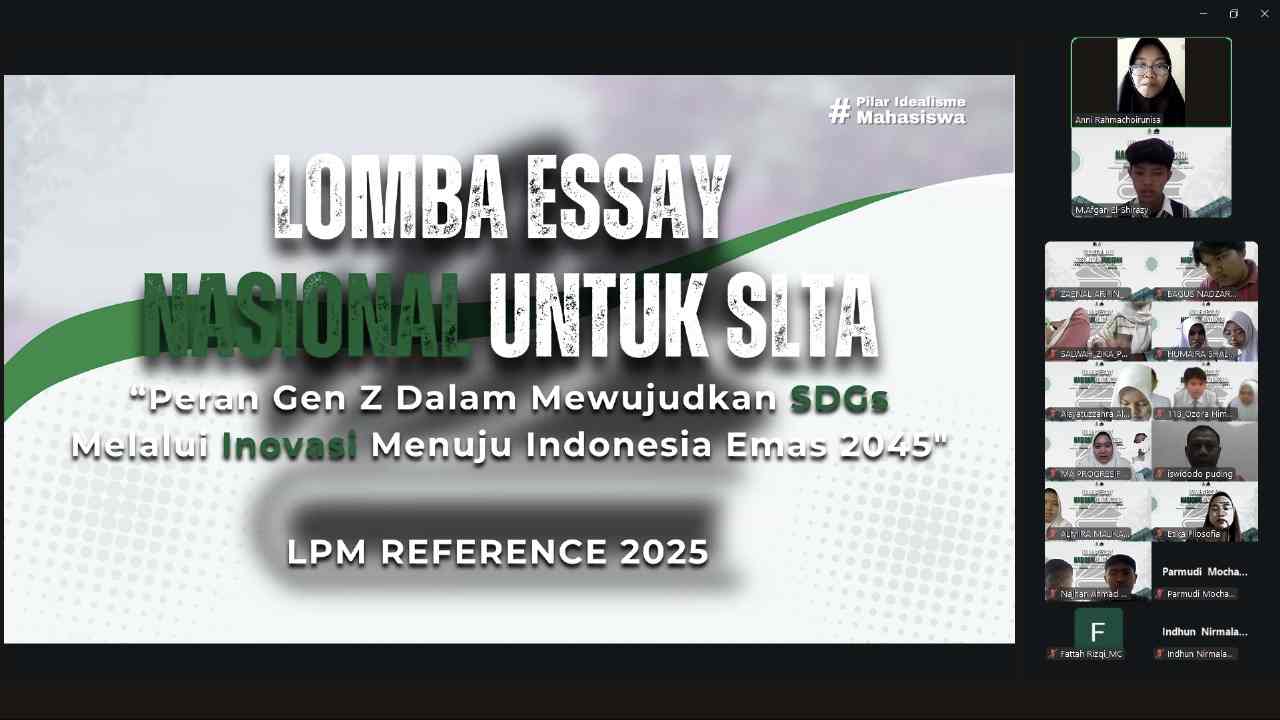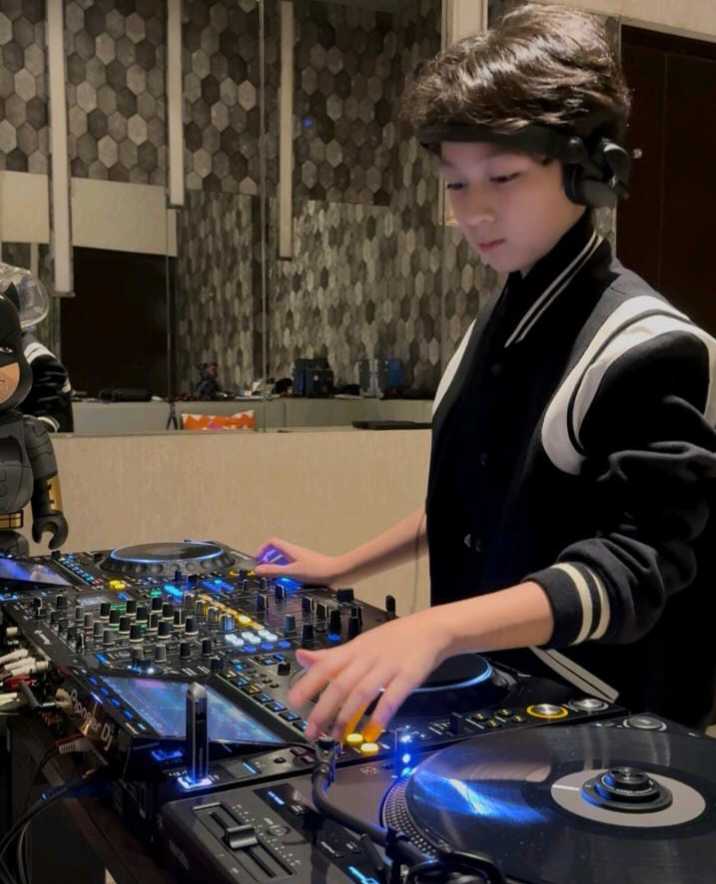Menulis, Tapi untuk Apa? Mencari Makna di Balik Kata yang Tak Lagi Menggetarkan Jiwa


SUARAMUDA.NET, YOGYAKARTA — Setiap Ahad pagi, aku duduk di teras rumah dengan laptop terbuka, segelas teh hangat, dan tumpukan keresahan yang ingin kujadikan tulisan. Ini bukan rutinitas pamer produktivitas, melainkan upaya menyusun ulang kesadaran diri: apakah menulis masih mampu melahirkan perubahan?
Aku adalah kader Muhammadiyah, dan bagiku, menulis bukan sekadar menuangkan kata, tetapi menciptakan kesadaran, menghidupkan ruh dakwah, dan mengajak manusia untuk berpikir. Namun, di tengah derasnya informasi dan konten instan, aku sering bertanya: “Masihkah tulisan kita menyentuh nurani atau sekadar memenuhi kuota unggahan digital?”
Tulisan hari ini banyak yang viral, disukai, dibagikan, bahkan dijadikan kutipan motivasi, tapi tidak sedikit pula yang kehilangan jiwa. Ketika menulis hanya menjadi bagian dari tren, maka ia kehilangan makna.
Di Muhammadiyah, kita diajarkan untuk berpikir rasional, bergerak sistematis, dan mendidik umat. Namun, bagaimana bila aktivitas menulis yang selama ini diagung-agungkan kadernya justru tidak lagi melahirkan kesadaran umat?
Apakah kita hanya pandai menyusun kalimat tapi tak pandai menyentuh hati? Maka, benarlah pernyataan yang mengusikku: “Buktikan dong, kader Muhammadiyah.”
Masalah yang muncul bukan karena kader Muhammadiyah tidak bisa menulis, tapi karena seringkali tulisan-tulisan itu berhenti di permukaan. Ia informatif, tapi tak menggugah.
Ia panjang, tapi tak menghunjam. Bahkan, di saat krisis moral, sosial, dan spiritual seperti hari ini, tulisan kader Muhammadiyah justru menjadi sunyi. Kita seolah lebih sibuk dengan tata bahasa, struktur, dan kelogisan akademik, tapi lupa bahwa dakwah itu harus menyentuh rasa.
Tulisan kita tak menyentuh akar keresahan masyarakat. Tak jarang pula kita terlalu asyik membanggakan jargon-jargon perubahan, tanpa mau membumikan realita umat di lapangan.
Masalah lain adalah alienasi tulisan dari realitas hidup. Literasi kader Muhammadiyah kadang terlalu tinggi dan elitis. Padahal dakwah kultural menuntut kesederhanaan bahasa dan kedalaman makna.
Umat membutuhkan tulisan yang bisa menghidupkan harapan, bukan sekadar artikel jurnal. Jika tulisan hanya bisa dibaca oleh kalangan terbatas, apa bedanya dengan menara gading yang kehilangan jembatan? Di sinilah krisis literasi berbasis kesadaran lahir—menulis bukan untuk mencerahkan, tapi sekadar eksistensi.
Maka, kita butuh paradigma baru dalam menulis: menulis sebagai sarana kesadaran kolektif. Bukan hanya untuk membuktikan bahwa kita kader Muhammadiyah yang mampu merangkai kata, tetapi lebih dari itu—menulis untuk memantik perubahan.
Tulisan yang membangunkan, bukan memanjakan. Tulisan yang menyentil, bukan menghibur. Dalam aktivitas Ahad produktif yang selalu kujalani, aku mencoba menjadikan waktu menulis bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk orang lain yang ingin tercerahkan. Karena sejatinya, dakwah adalah tentang memberi, bukan tampil.
Solusi lain adalah membumikan tradisi literasi Muhammadiyah dalam setiap lini kehidupan. Jangan biarkan menulis hanya menjadi aktivitas lomba atau formalitas organisasi. Literasi harus menjadi gaya hidup kader.
Kita butuh ekosistem menulis yang hidup: forum diskusi, mentoring literasi, publikasi yang mudah diakses dan merakyat. Kader muda harus dilatih bukan hanya untuk menulis yang baik, tapi juga menulis yang menggugah dan membangkitkan kesadaran ideologis ke-Muhammadiyahan. Tujuannya jelas: mencetak kader literat yang juga aktivis perubahan
Dalam implementasinya, aku mencoba menulis setiap hari. Bukan untuk menjadi terkenal, tapi untuk menjaga nalar tetap tajam dan nurani tetap hidup. Setiap tulisan di media sosial, blog pribadi, atau media organisasi adalah upaya kecilku menyemai makna.
Aku menulis tentang isu sosial, agama, pendidikan, dan keresahan remaja. Aku percaya, dakwah hari ini bukan hanya di mimbar masjid, tapi juga di layar ponsel. Ahad produktif bagiku adalah medan jihad literasi. Jika setiap kader melakukan hal kecil ini, perlahan tapi pasti, kita membangun peradaban baru.
Program penulisan kolektif yang bisa dijalankan oleh ortom Muhammadiyah, seperti pelatihan rutin, tantangan literasi mingguan, dan penyebaran tulisan-tulisan kader ke media umum, harus digencarkan.
Tapi ingat, jangan hanya menulis untuk menulis. Harus ada ruh gerakan. Kita bisa mulai dengan mengangkat isu lokal, kisah inspiratif warga, atau realita pendidikan di pelosok. Setiap kata adalah doa, setiap kalimat adalah dakwah. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu.
Kesenjangan besar saat ini adalah antara banyaknya jumlah kader yang pintar menulis, dengan sedikitnya tulisan yang menyadarkan. Ini adalah paradoks.
Kita sering menjadikan aktivitas menulis sebagai bagian dari portfolio, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Kita mengutip KH. Ahmad Dahlan, tapi kita tidak menulis dengan semangat tajdid.
Kita bicara “Islam Berkemajuan”, tapi tulisan kita hanya berhenti pada berita dan informasi. Di sinilah letak kesenjangan itu: tulisan kehilangan ruh perubahan.
Selain itu, banyak kader yang menulis hanya saat dibutuhkan organisasi, bukan karena kesadaran diri. Literasi menjadi kewajiban temporer, bukan nafas perjuangan. Ketika tuntutan selesai, maka menulis pun berhenti.
Kesenjangan antara kapasitas dan komitmen inilah yang membuat geliat literasi kader Muhammadiyah kurang berdampak secara luas. Maka, pertanyaannya kembali: “Untuk apa kamu menulis, dan untuk siapa?”
Aku percaya, tulisan yang kuat tidak dilahirkan dari pikiran semata, tapi dari kesadaran. Aku menulis bukan karena aku hebat, tapi karena aku ingin menjadi bagian kecil dari perubahan.
Di setiap Ahad produktifku, aku ingin melawan kemalasan berpikir, melawan pasifnya jiwa. Aku ingin mengatakan bahwa kader Muhammadiyah tidak hanya bisa berdiskusi, tapi juga menulis dan menggugah. Jika kesadaran itu hidup, maka tulisan akan bernyawa.
Mari buktikan bahwa kita adalah kader yang tidak hanya bergerak di rapat dan mimbar, tapi juga di kata-kata yang hidup dan menyala.
Mari menulis bukan hanya karena tuntutan, tapi karena cinta. Karena pada akhirnya, perubahan besar selalu dimulai dari tulisan kecil yang ditulis dengan kejujuran, keberanian, dan semangat tajdid. Jangan biarkan tulisanmu jadi sunyi, apalagi sia-sia. (Red)
Oleh: Nashrul Mu’minin, Content Writer Yogyakarta