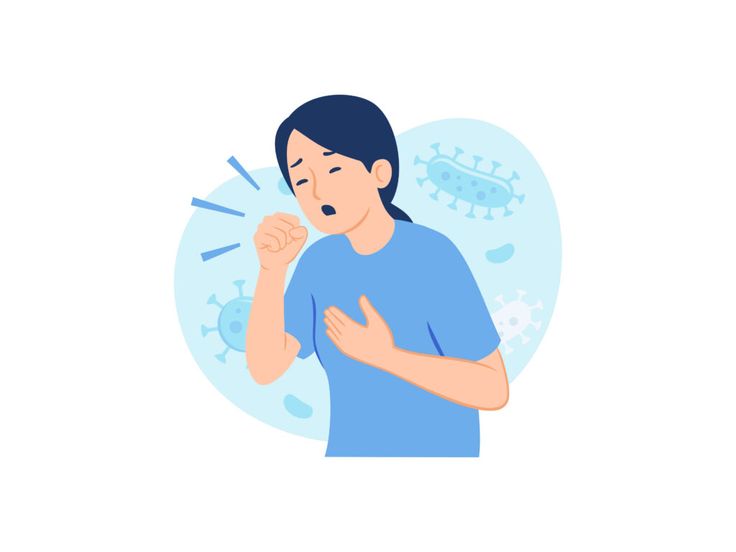

Dilema Kekuasaan Setengah Hati, Derita Rakyat Setengah Mati


Oleh: Sri Radjasa*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Sejak proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia kerap terjerumus dalam sebuah narasi yang berulang berupa retorika pemerintahan baru yang menggembar-gemborkan keberpihakan pada rakyat, namun hakikatnya adalah praktik konsolidasi dan ‘bagi-bagi’ kepentingan di antara elite dan oligarki.
Siklus ini menghasilkan anomali politik di mana setiap transisi kekuasaan nasional nyaris selalu diwarnai konflik dan upaya ‘de-legitimasi’ kebijakan pendahulu.
Ironisnya, alih-alih membangun keberlanjutan, setiap pergantian pemimpin seolah membawa Indonesia kembali ke titik nol, menghabiskan energi politik hanya untuk menyingkirkan ‘kerikil’ yang ditanam rezim sebelumnya.
Filosofi tata kelola negara yang ideal haruslah memegang teguh prinsip Pareto Optimality, dimana kemakmuran setidaknya satu orang meningkat tanpa merugikan orang lain, atau setidaknya memenuhi Kaldor-Hicks Criterion, dimana pihak yang diuntungkan dari sebuah kebijakan mampu mengompensasi kerugian pihak lain, sehingga kesejahteraan sosial agregat meningkat.
Namun, dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, seringkali yang terjadi adalah ‘kemakmuran satu pihak meningkat drastis, sementara kemiskinan pihak lain tak terhindarkan’.
Paradoks Kekayaan Alam dan Cacat Reformasi
Indonesia diberkahi kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah: minyak, batu bara, gas alam, emas, nikel, tembaga, dan berbagai komoditas ekspor bernilai tinggi.
Menurut estimasi konservatif pengamat energi sekelas Kurtubi, nilai total kekayaan SDA Indonesia dapat mencapai angka fantastis, menyentuh Rp 200 ribu triliun.
Secara filosofis, amanat Pasal 33 UUD 1945 jelas, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan modal dasar ini, secara logis, Indonesia seharusnya mampu melunasi utang luar negeri, mengatasi masalah gizi buruk, serta menjamin pendidikan dan pekerjaan yang layak bagi setiap warga negara.
Namun, realitasnya hari ini adalah sebuah paradoks. Era Reformasi, yang diagungkan sebagai tonggak demokrasi dan HAM, ironisnya telah menciptakan tata kelola negara yang dinilai sebagian pihak lebih amburadul.
Liberalisasi kebijakan pengelolaan SDA melalui berbagai undang-undang telah menggelar karpet merah bagi oligarki, investor asing, dan sindikat tambang untuk mengeksploitasi kekayaan alam secara masif.
Kedaulatan negara atas SDA seolah digadaikan, dan rakyat sebagai pemilik sah kedaulatan hanya menjadi subjek yang pasif dalam proses eksploitasi di daerah-daerah kaya sumber daya.
Masalah Moralitas
Biang keladi utama dari anomali ini bukanlah terletak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia atau ketertinggalan teknologi pertambangan. Persoalannya adalah pada moralitas dan kejujuran pemegang kekuasaan.
Dari masa ke masa, sektor pertambangan dan perkebunan telah menjadi ‘bancakan’ (ajang bagi-bagi keuntungan) bagi oknum pejabat negara, aparat penegak hukum, dan aparat keamanan yang berkolaborasi erat dengan oligarki dan pemilik modal.
Penggunaan kekuasaan negara belum pernah secara murni diproyeksikan untuk kemakmuran rakyat, melainkan untuk memperkaya diri dan kelompok.
Tudingan bahwa penguasa negara, sejak awal kemerdekaan, adalah arsitek utama ‘perampokan’ warisan Ibu Pertiwi bukanlah hal yang berlebihan.
Analogi bahwa penguasa ini lebih kejam dari binatang buas yang tidak memangsa anaknya sendiri terasa relevan, mengingat sumber daya yang seharusnya untuk anak cucu justru dikuras habis.
Upaya penindakan kejahatan korporasi, seperti pembentukan Satgas oleh Presiden saat ini, patut diapresiasi.
Akan tetapi, tanpa disertai manajemen berkelanjutan dan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel, upaya penindakan ini berisiko berakhir hanya sebagai ‘ganti pemain’, yakni mengganti pihak yang diizinkan merampok, sementara kejahatan itu sendiri tetap berlangsung.
Apalagi jika penyelesaian kasus besar masih mengedepankan pendekatan kompromi politik.
Pada akhirnya, rakyat hanya disajikan sinetron politik yang menyedihkan, siapapun Presidennya, nasib rakyat tetap tidak berubah sebagai korban dari kekuasaan setengah hati yang gagal menjalankan amanat konstitusi. (Red)
*) Penulis: Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)















