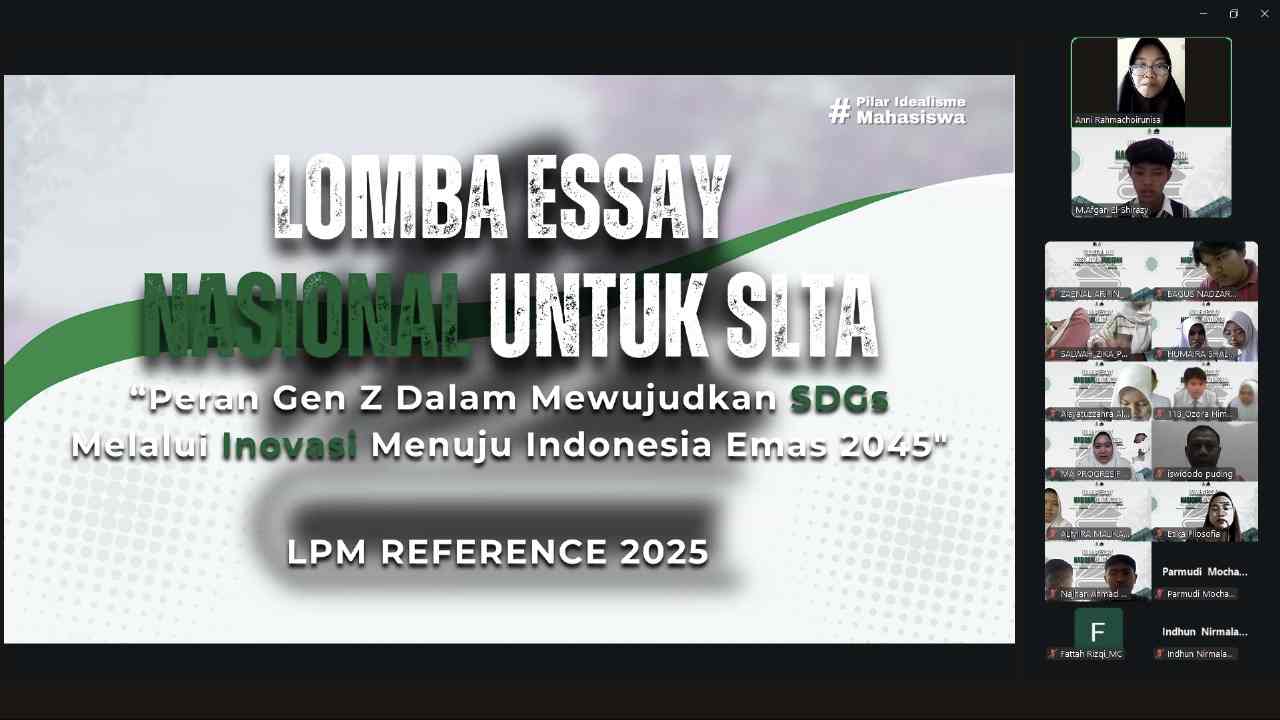Ahmad Muzakki dan Krisis Legitimasi PMII


SUARAMUDA.NET, TULUNGAGUNG — Di sebuah rumah besar bernama PMII, ada banyak pintu yang dulu selalu terbuka. Angin intelektual masuk leluasa, para kader saling bertemu, bercakap, dan membangun mimpi.
Rumah itu berdiri di atas fondasi yang disebut visi dan misi. Fondasi yang sederhana: tempat belajar, tempat berproses, tempat menumbuhkan manusia merdeka.
Namun belakangan, rumah itu tampak sunyi. Pintu-pintu sering tertutup, ruang pertemuan kosong, meja belajar berdebu. Pemilik kunci, Ahmad Muzakki, lebih sibuk berjalan ke luar pagar, bertamu ke rumah-rumah tetangga.
Ia menjalin relasi, tetapi lupa mengajarkan cara membuka kunci bagi penghuni di dalam rumahnya sendiri.
Kader yang menunggu di ruang tamu hanya bisa saling menatap. Mereka mendengar janji tentang “pembatalan pesta lama” dan “rencana pesta baru” yang katanya akan lebih baik.
Tapi, seperti kata Hannah Arendt, kekuasaan sejati lahir dari tindakan bersama. Bila pesta hanya diulang tanpa musyawarah, maka yang tersisa hanyalah dekorasi hampa.
Di balik itu, ada yang lebih mengkhawatirkan. Rumah ini, yang dulu berdiri karena idealisme, kini dipenuhi bayangan tirani kecil.
Kata Plato, pemimpin ideal adalah philosopher king—raja bijak yang mendengar, bukan yang berteriak. Namun di Tulungagung, suara yang terdengar justru keras, arogan, dan sewenang-wenang.
Kondisi ini menyerupai apa yang disebut Kierkegaard sebagai “keputusasaan etis”: ketika rumah besar terus berbicara tentang nilai, tetapi jendela dan pintunya tertutup rapat, tidak ada jalan bagi cahaya masuk.
Sementara Foucault mungkin akan menyebutnya “aturan tubuh”: kader diatur, tapi tidak pernah diajak berpikir.
Maka, apa arti rumah besar jika penghuninya kian merasa asing? Apa arti visi jika ia hanya menjadi slogan di dinding? Apa arti ketua jika ia hanya sibuk dengan dirinya?
Kritik ini bukan sekadar cermin buram untuk Ahmad Muzakki, tetapi juga refleksi bagi seluruh penghuni rumah bernama PMII.
Bila rumah ini ingin kembali hidup, kuncinya ada pada keberanian membuka pintu dialog, menghidupkan kembali meja belajar, dan menyalakan lampu musyawarah.
Sebab tanpa itu semua, rumah ini akan tetap berdiri—tetapi kosong. Dan sejarah akan mencatatnya sebagai rumah megah yang ditinggalkan penghuninya, bukan karena runtuh, melainkan karena dikuasai oleh arogansi. (Red)
Penulis: Ontoseno Ndugal Pergerakkan