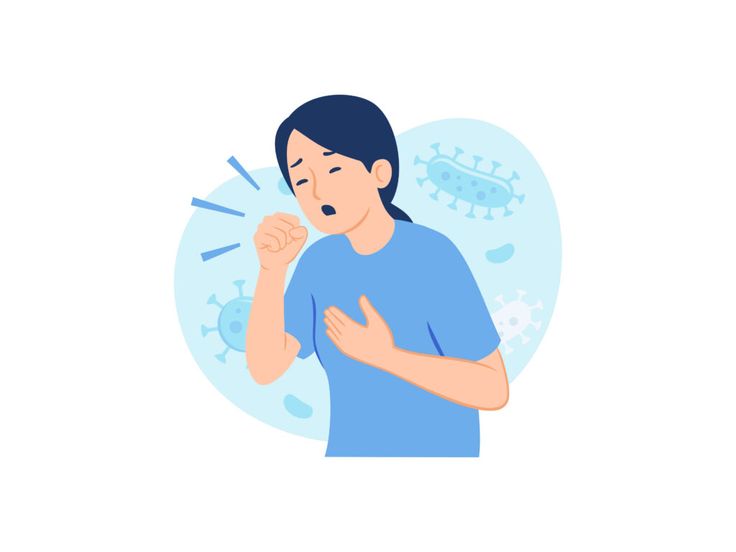

55 Juta untuk Kursi Empuk, Jalan Berlubang Tetap Menganga


Oleh: Yohanes Soares*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG – Ada ironi yang begitu menusuk ketika kita menatap angka-angka tunjangan anggota DPRD NTT. Di atas kertas, Pergub Nomor 22 Tahun 2025 tampak sah, formal, dan administratif.
Tetapi di balik lembaran hukum itu, ada kenyataan pahit: pejabat publik menikmati kemudahan hidup yang nyaris tak terbatas, sementara rakyat di tanah yang sama harus berjuang keras hanya untuk sekadar bertahan hidup.
Inilah paradoks NTT hari ini. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan lebih dari satu juta penduduk miskin, justru memberi fasilitas fantastis bagi elit politiknya.
Fenomena ini bukan sekadar soal salah urus anggaran. Ia adalah cermin retak dari krisis moral, ketidakpekaan, dan kegagalan empati yang sedang menggerogoti demokrasi lokal.
Cermin Ketidakadilan: Kemewahan yang Buta
Tunjangan Ketua DPRD NTT yang mencapai lebih dari Rp55 juta per bulan hanya untuk rumah dan transportasi bukanlah angka netral. Ia adalah simbol ketimpangan.
Ketika dibandingkan dengan kenyataan sebagian besar masyarakat NTT yang masih hidup dengan penghasilan di bawah Rp20 ribu sehari, angka itu terasa seperti ejekan.
Sementara elit bersandar di kursi empuk dengan fasilitas rumah dan kendaraan yang dijamin negara, rakyat di desa harus menyusuri jalan berlubang, menunggu air bersih dari sumur yang kering, dan hidup dalam keterbatasan.
Kemewahan ini bukan hanya menjauhkan elit dari rakyat, tetapi juga memutus ikatan emosional yang seharusnya menjadi fondasi kepemimpinan.
Demokrasi di Titik Nadir: Fungsi yang Terabaikan
Tunjangan besar seharusnya memberi energi dan fokus lebih bagi DPRD untuk menyelesaikan masalah fundamental di NTT. Namun realitas berbicara lain.
• Jalan berlubang yang menghubungkan desa dengan kota tetap terbengkalai.
• Jaringan telekomunikasi di pedalaman tersendat, membuat warga tertinggal di era digital.
• Air bersih, kebutuhan paling dasar, masih menjadi barang mewah.
Lantas, di mana fungsi pengawasan DPRD? Di mana peran legislasi yang seharusnya memastikan anggaran benar-benar berpihak pada rakyat?
Sayangnya, perhatian DPRD lebih sering tertuju pada legitimasi fasilitas pribadi ketimbang memperjuangkan sumur bor, jembatan, atau puskesmas yang layak. Demokrasi pun kehilangan makna: wakil rakyat sibuk melayani diri sendiri, bukan konstituennya.
Luka Kolektif: Sektor Vital yang Terlupakan
Masalah NTT tidak pernah tunggal. Ia membentang di berbagai sektor vital yang saling berkaitan:
1. Pendidikan: sekolah-sekolah yang rusak tak kunjung diperbaiki. Anak-anak dipaksa belajar dalam kondisi tidak layak. Ini bukan sekadar masalah fisik, tetapi pengabaian terhadap masa depan.
2. Kesehatan: puskesmas minim tenaga medis, fasilitas dasar tak memadai. Akses kesehatan menjadi privilese, padahal seharusnya hak setiap warga.
3. Ekonomi rakyat: infrastruktur transportasi yang buruk memutus akses petani dan nelayan ke pasar. Kerja keras mereka terhenti di jalan berlubang.
4. Lingkungan hidup: abrasi pantai, kekeringan, dan degradasi lahan dibiarkan tanpa strategi jangka panjang. Ancaman ini jelas akan menjerat generasi berikutnya.
Semua ini adalah luka kolektif yang terus menganga. Dan ironisnya, tunjangan mewah para wakil rakyat justru menjadi garam yang ditaburkan di atas luka tersebut.
Panggilan untuk Refleksi dan Keberanian Moral
Kritik ini bukan semata-mata soal angka, tetapi soal keberanian moral. Demokrasi tidak akan pernah bertahan jika para pemimpinnya kehilangan empati. Rakyat tidak butuh DPRD yang sibuk mengatur kenyamanan pribadi.
Rakyat butuh pemimpin yang tahu panasnya debu jalan, yang mengerti bagaimana rasanya malam tanpa listrik, yang bisa merasakan getirnya meneguk air payau karena tak ada pilihan lain.
Pertanyaannya kini: apakah para wakil rakyat DPRD NTT akan tetap bertahan di menara gading kemewahan mereka, atau berani turun, menjejak tanah, dan melihat kenyataan rakyat yang sesungguhnya?
Sejarah selalu berpihak pada mereka yang memilih keberanian untuk berpihak pada yang lemah. Dan saat ini, keberanian itu sangat dirindukan di NTT. (Red)
*) Yohanes Soares, aktivis sosial dan peneliti kebijakan pendidikan dan masyarakat daerah tertinggal; mahasiswa S3 Universitas Dr. Soetomo Surabaya















