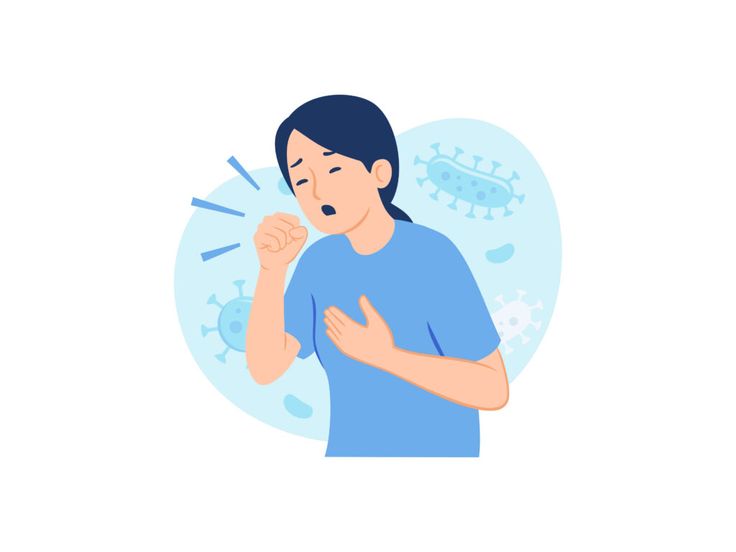

Bubarkan DPR: Sekedar Narasi atau Kenyataan Politik?


Oleh: Krisna Wahyu Yanuar*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Narasi “Bubarkan DPR RI” yang muncul sejak kasus pesta joget di Senayan bukan sekadar letupan spontan di media sosial, melainkan cerminan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Awalnya, momen joget itu hanyalah seremonial biasa dalam sebuah acara menyanyi. Namun framing media sosial bergerak cepat, mengaitkannya dengan naiknya tunjangan DPR.
Publik pun segera menangkap simbol: wakil rakyat menari di atas penderitaan rakyat, Inilah titik api yang digiring algoritma.
Kondisi objektif masyarakat saat ini adalah ekonomi yang kian berat. Harga kebutuhan pokok naik, daya beli menurun, sementara di sisi lain DPR justru menikmati “kenaikan tunjangan”.
Ketimpangan ini memicu rasa marah. Apa yang dilihat publik bukan sekadar joget, melainkan simbol kesenjangan—“kami lapar, kalian berpesta.”
Flexing dan Krisis Komunikasi
Narasi makin diperkuat oleh fenomena flexing pejabat, terutama Ahmad Sahroni yang kerap memamerkan kemewahan.
Disusul dengan krisis komunikasi politik: Hasan Nasbi dengan statement kontroversial, Sudewo dengan sikap elitis, hingga figur publik seperti Uya Kuya yang seolah melegitimasi gaya hidup pejabat. Alih-alih membangun empati, yang muncul justru jarak psikologis antara penguasa dan rakyat.
Menariknya, framing tidak berhenti di DPR. Beberapa akun menggiring kamera ke wajah Gibran, seolah-olah ia tidak pro terhadap DPR.
Narasi ini strategis: memisahkan posisi eksekutif (Prabowo–Gibran) dari legislatif, sekaligus menyiapkan kanal baru bagi kekecewaan rakyat. Tidak lama kemudian muncul hashtag di Tiktok #BantuPrabowoBubarkanDPR Publik pun digiring untuk melihat “harapan” ada pada presiden, bukan parlemen.
Bahaya Bagi Demokrasi
Puncaknya, narasi itu menyeberang dari dunia maya ke dunia nyata. Demonstrasi 25 Agustus 2025 menjadi ruang artikulasi nyata dari kemarahan publik. Apa yang sebelumnya hanya hashtag kini menjelma menjadi gerakan massa.
Namun ada yang perlu diwaspadai. Narasi “Bubarkan DPR” memang terdengar populis, tetapi juga mengandung bahaya bagi demokrasi.
DPR—betapapun korup atau elitisnya—tetaplah lembaga yang menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif. Membubarkan DPR berarti membuka ruang otoritarianisme baru.
Tetapi, yang juga tidak bisa diabaikan: narasi ini lahir dari realitas. Ekonomi sulit, komunikasi pejabat buruk, flexing yang menyakitkan, hingga tunjangan jumbo DPR di tengah krisis. Dengan kata lain, DPR sendiri yang menyalakan bara ketidakpercayaan ini.
Apakah narasi “Bubarkan DPR” hanya amarah sesaat? Atau pertanda dalam bahwa rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada sistem perwakilan?
Yang jelas, momen joget di Senayan bukanlah penyebab utama, hanya percikan. Bahan bakarnya sudah lama menumpuk: kesenjangan sosial, arogansi elit, dan politik yang gagal menyentuh rakyat.
Jika DPR tidak segera berbenah, jangan salahkan publik bila narasi ini terus bergema. Karena dalam imajinasi rakyat, bubarnya DPR mungkin justru dianggap awal dari lahirnya politik yang lebih jujur.
Perspektif akademis memberi kita dua bacaan yakni, narasi ini adalah ekspresi kekecewaan struktural rakyat yang rasional.
Namun ia juga bisa menjadi alat politik hegemonik, dipelihara untuk memperkuat legitimasi eksekutif dengan mengorbankan lembaga legislatif.
Dengan demikian, “Bubarkan DPR” adalah seruan yang ambigu: antara kritik sosial yang sah, dan instrumen politik yang berpotensi melemahkan demokrasi itu sendiri. (Red)
*) Krisna Wahyu Yanuar, Mahasiswa Peminat Isu Sosial Politik













