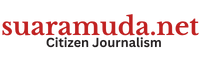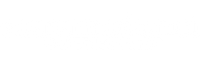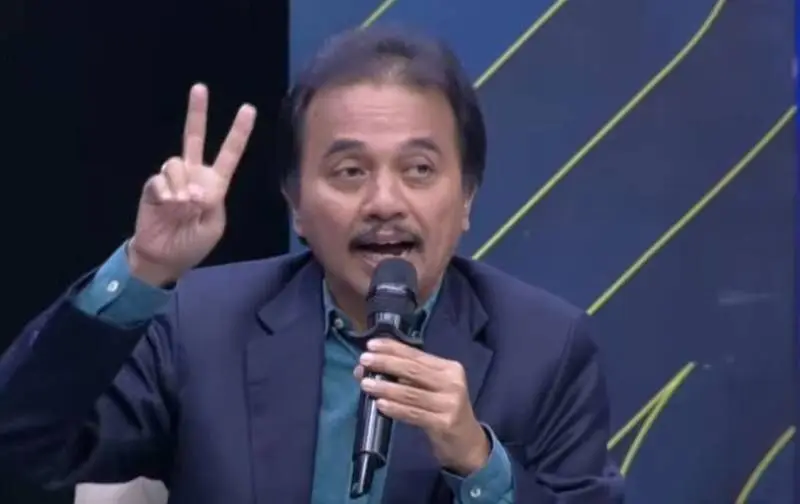Demo 25 Agustus: Krisis Kepercayaan Publik dan Ujian Demokrasi



Oleh: Yohanes Soares *)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Gelombang demonstrasi besar yang mengguncang Gedung DPR RI pada 25 Agustus 2025 menandai babak baru hubungan rakyat dengan institusi negara.
Aksi yang bermula dari tuntutan transparansi legislasi dan penolakan terhadap sejumlah kebijakan kontroversial berakhir ricuh: pos polisi dirusak, transportasi publik lumpuh, dan ratusan demonstran ditangkap. Bahkan, seorang jurnalis dilaporkan mengalami kekerasan di lapangan.
Peristiwa ini bukan sekadar keributan jalanan, melainkan potret akumulasi ketidakpuasan publik yang lama terpendam. Reaksi keras masyarakat terhadap DPR mengirimkan pesan tegas: ada krisis representasi dan kepercayaan yang semakin dalam.
Krisis Kepercayaan terhadap DPR
Demo 25 Agustus memperlihatkan jurang yang makin lebar antara rakyat dan wakilnya. DPR, yang seharusnya menjadi rumah aspirasi publik, justru dianggap sebagai menara gading yang jauh dari denyut rakyat.
Tuduhan yang melekat pun bukan hal baru: proses legislasi yang tertutup, minim transparansi, lemahnya pengawasan, hingga kesan agenda rapat lebih diwarnai kompromi politik daripada keberpihakan kepada masyarakat.
Tidak heran bila politisi senior menyebut aksi ini sebagai “alarm” keras bagi anggota dewan. Alarm tersebut menandai bahwa masyarakat sudah kehabisan saluran artikulasi, sehingga jalanan kembali menjadi ruang politik alternatif.
Fenomena ini sejatinya repetisi sejarah. Dari gerakan mahasiswa 1998, penolakan RUU kontroversial pada 2019, hingga demo 2025, pola yang sama berulang: publik merasa diabaikan sementara kebijakan tetap digulirkan tanpa konsultasi bermakna.
Yang membedakan Agustus ini adalah spektrum kekecewaan yang lebih luas. Bukan hanya mahasiswa, tetapi juga buruh, aktivis, hingga warga urban turut turun ke jalan.
Ketika pos polisi dibakar dan transportasi lumpuh, itu menandai jurang representasi yang mencapai titik kritis. Jika DPR tidak mengambil langkah korektif, lembaga ini berisiko kehilangan legitimasi substantif.
Demokrasi sejati menuntut transparansi, partisipasi publik, serta pengawasan yang berpihak pada kepentingan umum, bukan sekadar prosedur lima tahunan.
Kekerasan, Represi, dan Kebebasan Sipil
Aksi demonstrasi seharusnya menjadi ekspresi demokratis warga negara. Namun, ironinya, ruang demokrasi itu justru ternodai oleh kekerasan baik dari sebagian demonstran maupun aparat.
Laporan media memperlihatkan penggunaan kekuatan berlebihan, termasuk penangkapan massal terhadap lebih dari 370 orang tanpa kejelasan status hukum. Seorang jurnalis Antara bahkan dipukul saat meliput, memperlihatkan bahwa represi merambah hingga pihak yang seharusnya dilindungi.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana negara benar-benar berkomitmen pada kebebasan sipil? Demokrasi bukan hanya soal pemilu dan parlemen, tetapi juga jaminan warga untuk menyampaikan kritik tanpa rasa takut. Sayangnya, ketika kritik dijawab dengan represi, yang tumbuh adalah spiral ketidakpercayaan.
Represi atas nama keamanan kontraproduktif. Stabilitas jangka pendek yang dipaksakan lewat kekerasan hanya melahirkan luka kolektif, memperlebar jarak negara–masyarakat, dan membuka ruang bagi radikalisasi ketidakpuasan. Negara tidak boleh mengorbankan kebebasan sipil demi ketenangan sesaat; dialog dan transparansi seharusnya menjadi kanal utama.
Media Sosial dan “Pengadilan Publik”
Salah satu dimensi penting demo 25 Agustus adalah peran media sosial dalam membingkai peristiwa. Jika dulu publik hanya mengandalkan media arus utama, kini ruang digital menjadi panggung kedua yang sama pentingnya. Tagar trending, video amatir, hingga siaran langsung membawa momen demonstrasi ke layar jutaan orang dalam hitungan detik.
Fenomena ini melahirkan “pengadilan publik digital”. Netizen bukan sekadar penonton, tetapi juga hakim moral yang memberi komentar, kecaman, bahkan legitimasi.
Kekerasan aparat yang terekam kamera ponsel menyebar cepat, sulit dibantah, dan lebih dipercaya dibanding pernyataan resmi pejabat. Retorika politisi pun dengan mudah disulap jadi meme yang mempermalukan mereka di ruang maya.
Dengan begitu, demonstrasi fisik menemukan pasangan barunya dalam demo digital. Aksi yang kecil di lapangan bisa membesar karena narasi viral, sebaliknya aksi besar bisa kehilangan gaung jika gagal menarik simpati netizen. Namun, kecepatan arus informasi juga menimbulkan tantangan berupa disinformasi dan manipulasi konten.
Meski demikian, media sosial membuka ruang demokratisasi informasi yang lebih luas. Wacana publik tidak lagi sepenuhnya dikendalikan media arus utama, melainkan setiap individu kini memiliki mikrofon sendiri. Inilah wajah baru politik Indonesia: tidak hanya berlangsung di ruang institusional, tetapi juga di arena digital yang cair, spontan, dan tak terkendali.
Demokrasi di Persimpangan
Demo 25 Agustus bukan sekadar letupan emosional, melainkan momentum reflektif bagi arah demokrasi Indonesia. Pesan rakyat jelas: mereka merindukan transparansi, partisipasi, dan keberpihakan nyata dari lembaga politik. Dalam demokrasi sejati, mandat rakyat bukan hanya angka di kotak suara, melainkan amanah untuk terus mendengar dan melibatkan publik.
Namun, refleksi ini berlaku untuk dua pihak. Pemerintah dan DPR dituntut terbuka, sementara rakyat juga perlu menjaga agar protes tidak jatuh pada anarki. Demokrasi sehat membutuhkan kritik yang konstruktif, bukan pelampiasan emosi semata. Keseimbangan antara keterbukaan negara dan tanggung jawab publik inilah yang menentukan masa depan demokrasi.
Demo 25 Agustus memberi pelajaran bahwa demokrasi selalu berada di persimpangan: apakah akan tumbuh sehat atau terjebak dalam lingkaran ketidakpercayaan. Jika momentum ini dimaknai dengan bijak, ia bisa menjadi titik balik menuju demokrasi yang lebih matang. Jika diabaikan, yang tersisa hanyalah kemarahan yang berulang.
Penutup
Demo 25 Agustus tidak bisa direduksi sebagai catatan hitam politik 2025. Ia adalah potret jernih dari krisis kepercayaan publik. Jalanan yang dipenuhi teriakan dan poster bukanlah kebisingan tanpa makna, melainkan jeritan kolektif rakyat yang merasa diabaikan.
Momentum ini menuntut elite politik melakukan koreksi mendasar terhadap praktik demokrasi. Demokrasi seharusnya menghadirkan dialog, transparansi, dan partisipasi nyata. Jika alarm ini diabaikan, yang menunggu adalah krisis legitimasi dan pudarnya kepercayaan terhadap negara.
Sejarah memberi pelajaran: ketika suara rakyat terlalu lama diabaikan, yang tersisa adalah jalan buntu penuh gejolak. Karena itu, pilihan ada di tangan elite: menjadikan demo 25 Agustus titik balik perbaikan, atau membiarkannya menjadi awal dari krisis berikutnya. (Red)
*) Yohanes Soares, aktivis sosial dan peneliti kebijakan pendidikan dan masyarakat daerah tertinggal; mahasiswa S3 Universitas Dr. Soetomo Surabaya