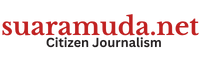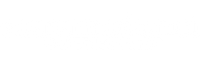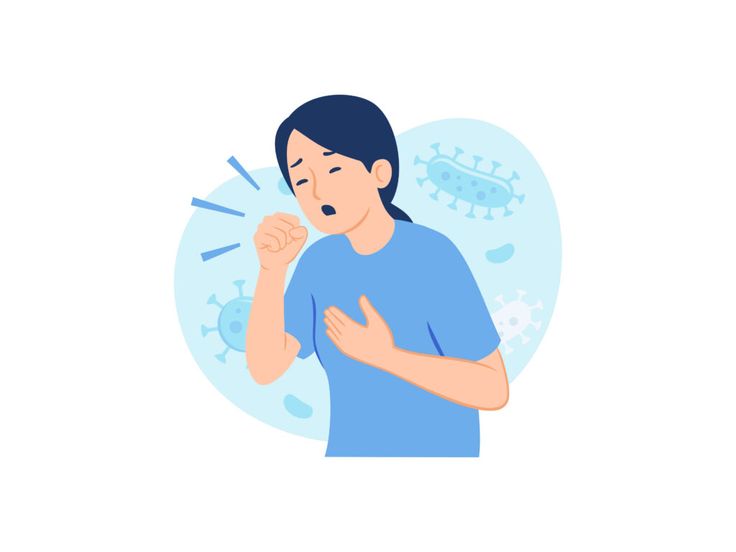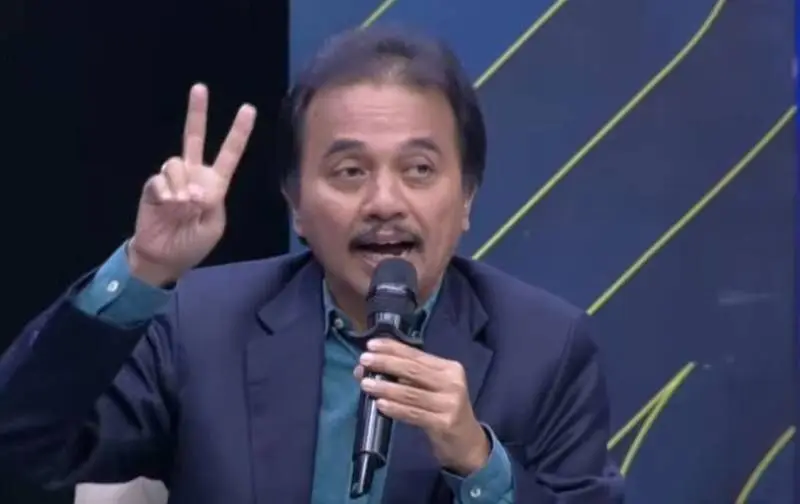PPATK, Rekening Dormant, dan Urgensi Komunikasi yang Mencerahkan: Sebuah Analisis Multidimensional atas Kebijakan Publik


Oleh Yohanes Soares*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belakangan kembali menjadi perhatian publik, menyusul diberlakukannya Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2024 serta munculnya kekhawatiran di masyarakat mengenai pemblokiran rekening “dormant” atau tidak aktif.
Narasi yang berkembang di berbagai kanal media menyiratkan bahwa rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan dapat diblokir oleh PPATK.
Narasi ini, jika dibiarkan tanpa klarifikasi memadai, dapat memicu kepanikan dan ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan yang tengah didorong untuk inklusif dan sehat.
Padahal, bila dicermati secara seksama, semangat kebijakan ini adalah untuk memperkuat sistem anti pencucian uang dan pendanaan terorisme (APU-PPT), serta mendukung pemulihan aset hasil tindak kejahatan keuangan.
Namun niat baik saja tidak cukup. Tanpa komunikasi publik yang jelas, akurat, dan kontekstual, kebijakan yang dirancang untuk melindungi masyarakat justru dapat menjadi sumber keresahan.
Inilah cermin dari persoalan klasik dalam kebijakan publik: antara regulasi yang kompleks dan tantangan komunikasi yang membumi.
Isu rekening dormant sesungguhnya sangat teknis. Kewenangan PPATK untuk melakukan penghentian sementara transaksi bukan berlaku otomatis terhadap seluruh rekening pasif, melainkan hanya terhadap rekening yang terindikasi kuat terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
Namun di ruang publik, pemahaman ini kabur. Kalimat “rekening dormant bisa diblokir PPATK” menyebar secara dangkal, memicu tafsir yang menyesatkan, dan berdampak luas secara sosial, ekonomi, hingga politik.
Secara sosial, kepanikan mengenai potensi pemblokiran rekening mengganggu rasa aman masyarakat terhadap dana simpanan mereka.
Terlebih bagi kelompok rentan seperti warga lanjut usia, masyarakat berpendidikan rendah, atau mereka yang hanya memiliki satu rekening untuk keperluan masa depan.
Kesenjangan literasi keuangan membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak lengkap, bahkan menyesatkan.
Ini menciptakan efek domino: kecemasan kolektif, penarikan dana secara tergesa-gesa, hingga antrean di bank untuk sekadar menanyakan “apakah rekening saya akan diblokir?”
Di ranah ekonomi, dampaknya tidak bisa dipandang sebelah mata. Disinformasi tentang kebijakan PPATK dapat menjadi disinsentif serius terhadap inklusi keuangan.
Masyarakat yang semula mulai percaya kepada sistem perbankan kembali ragu. Keengganan membuka rekening baru atau mempertahankan rekening yang ada akan menjadi ancaman nyata bagi agenda digitalisasi keuangan yang tengah didorong pemerintah.
Tak hanya itu, beban administrasi bank juga meningkat: ratusan bahkan ribuan nasabah menghubungi layanan pelanggan hanya untuk meminta klarifikasi, sementara kebijakan itu sendiri tidak menyasar mereka.
Secara politik, kesimpangsiuran informasi dapat memengaruhi legitimasi kelembagaan dan kredibilitas negara. Ketika sebuah lembaga strategis seperti PPATK dituding “memblokir rekening rakyat kecil”, meski tidak berdasar, kepercayaan terhadap negara bisa terkikis.
Ruang ini sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperkeruh suasana.
Kritik terhadap kebijakan publik adalah hal lumrah dalam demokrasi, namun kritik yang lahir dari ketidaktahuan atau kesalahan informasi justru dapat merusak upaya kolektif membangun tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel.
Lalu, di mana akar permasalahannya?
Komunikasi. Regulasi sebaik apa pun tidak akan efektif jika gagal dijelaskan secara jelas dan mudah dipahami publik. Dalam konteks ini, PPATK tidak cukup hanya mempublikasikan peraturan melalui kanal hukum resmi.
Lembaga ini perlu bertransformasi menjadi institusi yang komunikatif, edukatif, dan responsif terhadap keresahan masyarakat. Komunikasi kebijakan bukan soal penyampaian satu arah, melainkan membangun dialog yang terbuka, empatik, dan berbasis literasi.
Masyarakat berhak tahu bahwa rekening dormant menurut kebijakan perbankan—yang umumnya hanya dikenai biaya administrasi atau ditutup setelah bertahun-tahun tidak aktif—berbeda jauh dengan “penghentian sementara transaksi” oleh PPATK, yang hanya terjadi jika ditemukan indikasi kejahatan keuangan.
Penjelasan seperti ini harus dijabarkan dalam bahasa sederhana, disebarkan lewat berbagai media, dan ditujukan ke segmen masyarakat yang berbeda, dari kota hingga pelosok desa.
Karena itu, PPATK perlu meluncurkan kampanye edukasi publik yang masif dan terstruktur. Edukasi ini bukan hanya berupa siaran pers, tetapi infografik visual, video animasi, siniar (podcast), dan forum diskusi terbuka.
Materi harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat: pendek untuk media sosial, detail untuk media cetak, dan interaktif untuk komunitas lokal.
Kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perbankan, dan bahkan tokoh masyarakat di daerah sangat diperlukan agar komunikasi menyentuh lapisan terbawah.
Selain itu, mekanisme pemblokiran rekening oleh PPATK juga perlu disosialisasikan secara transparan—tentu dengan menjaga kerahasiaan proses hukum.
Penjelasan umum mengenai indikator atau pola transaksi mencurigakan dapat membantu publik memahami bahwa PPATK tidak bertindak sewenang-wenang, melainkan berdasarkan analisis forensik dan intelijen keuangan yang akurat.
Regulasi perlu evaluasi berkala, tak hanya dari sisi efektivitas hukum, tetapi juga dari perspektif sosial dan psikologis.
Survei persepsi publik, analisis sentimen media, serta konsultasi publik adalah instrumen penting untuk mengukur sejauh mana kebijakan dipahami dan diterima masyarakat. Tanpa itu, niat baik regulasi bisa berubah menjadi trauma publik yang sulit dipulihkan.
Akhirnya, harus disadari bahwa kepercayaan adalah aset utama dalam sistem keuangan modern. Ketika kepercayaan itu terganggu, bahkan tindakan paling baik sekalipun bisa dicurigai.
Maka, investasi pada komunikasi yang jujur dan mencerdaskan harus menjadi bagian tak terpisahkan dari desain kebijakan publik, terutama yang menyentuh hak dan rasa aman finansial warga negara.
Dalam dunia kebijakan publik, mencerahkan seringkali lebih kuat dampaknya ketimbang sekadar mengatur. Karena dari pencerahan lahir pemahaman, dan dari pemahaman tumbuh kepercayaan, fondasi dari negara yang stabil dan masyarakat yang berdaya. (Red)
*) Penulis:Yohanes Soares, aktivis sosial dan peneliti kebijakan pendidikan dan masyarakat daerah tertinggal; mahasiswa S3 Universitas Dr. Soetomo Surabaya