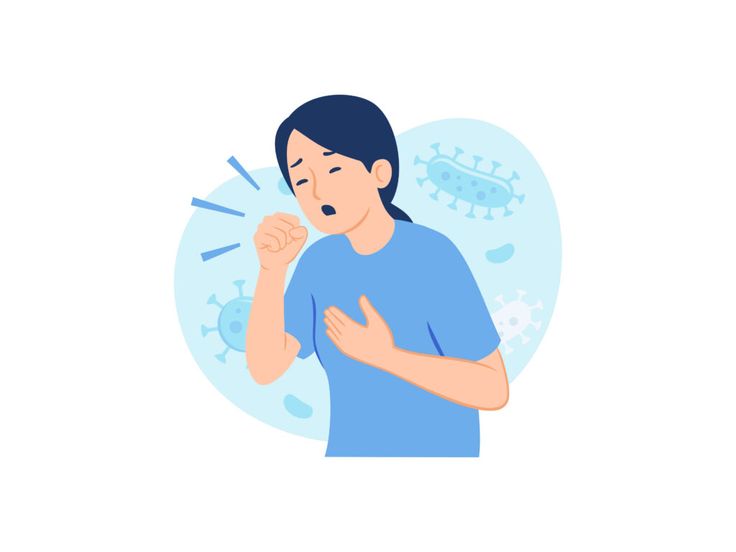Paradoks JKN: Cakupan Tinggi, Akses Kesehatan Masih Jadi Mimpi?


Oleh: Al Muhaemin*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Indonesia kerap membanggakan capaian program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Data resmi mencatat cakupan kepesertaan hampir menyentuh 98% populasi, angka yang tampak luar biasa jika dibandingkan dengan negara lain.
Namun di balik statistik ini, realitas di lapangan memperlihatkan wajah berbeda: jutaan warga tetap tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena status administrasi mereka bermasalah.
Di Dompu, Nusa Tenggara Barat, seorang pasien miskin ditolak rawat inap di RS Pratama Manggelewa dengan alasan tidak gawat darurat dan tidak sesuai prosedur BPJS.
Pasien hanya diberi obat dan dipulangkan. Tahun lalu, di Jambi, seorang pasien bahkan meninggal setelah ditolak IGD RSUD Raden Mattaher karena tidak memiliki BPJS maupun SKTM.
Di Kupang, warga miskin ditolak lantaran SKTM tidak berlaku lagi dan dana talangan sosial daerah telah dihapus. Kasus-kasus ini bukan kebetulan, melainkan potret nyata bahwa hak kesehatan masih terhalang dinding administrasi.
Secara keuangan, JKN juga menghadapi masalah serius. Pada 2024, BPJS Kesehatan mencatat defisit sekitar Rp 9,6 triliun, dengan pendapatan iuran sekitar Rp 165 triliun sementara klaim mencapai Rp 174 triliun.
Ironisnya, meski secara kepesertaan hampir universal, hanya 77–80% peserta yang aktif membayar iuran. Artinya, lebih dari 56 juta jiwa tercatat nonaktif—baik karena menunggak maupun mutasi status administrasi.
Mereka inilah yang paling rentan ditolak ketika sakit, meski namanya tercatat dalam data nasional.
Paradoks ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah kesehatan benar-benar dilihat sebagai hak dasar warga negara, atau sekadar komoditas finansial yang diukur untung rugi?
Rumah sakit memang menghadapi tekanan finansial—klaim yang terlambat cair, biaya operasional yang membengkak—tetapi menjadikan kemiskinan sebagai alasan penolakan pelayanan jelas bertentangan dengan amanat konstitusi.
Apa yang harus dilakukan? Pertama, prinsip emergency first, administration later harus ditegakkan. Pasien gawat darurat wajib ditangani tanpa syarat, sementara urusan administrasi diselesaikan setelahnya melalui koordinasi dengan BPJS dan dinas sosial.
Kedua, pemerintah daerah perlu mengaktifkan kembali Dana Talangan Sosial serta memperbarui data penerima bantuan iuran (PBI) agar kelompok miskin benar-benar terlindungi.
Ketiga, BPJS Kesehatan harus mereformasi sistem iuran, misalnya dengan skema cicilan atau keringanan bagi peserta yang menunggak, agar status nonaktif bisa ditekan.
Terakhir, perlu dibangun budaya pelayanan tanpa diskriminasi melalui pelatihan tenaga medis, SOP yang jelas, dan mekanisme pengaduan yang transparan.
Negara boleh berbangga dengan cakupan JKN yang tinggi, tetapi kebanggaan itu hampa jika di lapangan masih ada pasien miskin yang ditolak rumah sakit.
Paradoks ini harus segera diakhiri. Kesehatan adalah hak, bukan hak istimewa bagi mereka yang mampu membayar. Selama dinding administrasi masih menghalangi pintu rumah sakit, maka cita-cita “Kesehatan untuk Semua” hanyalah ilusi di atas kertas. (Red)
*) Al Muhaemin, Koordinator Kebijakan Publik Forum Komunikasi Aktivis Kesehatan NTB