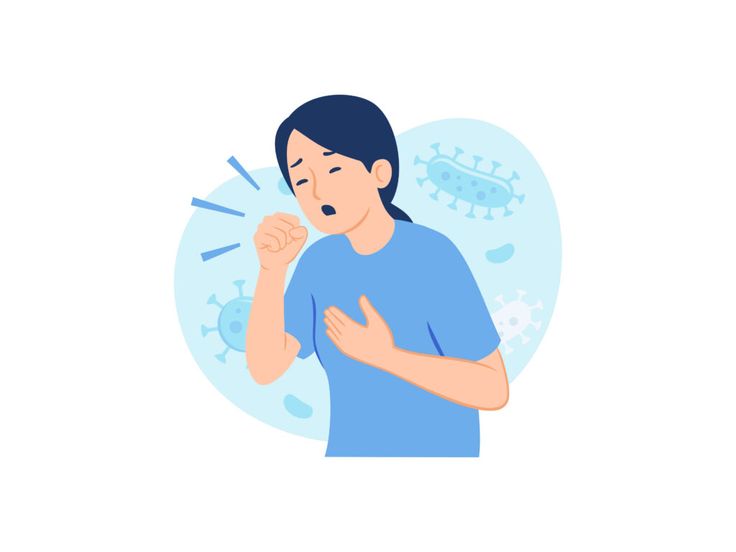Sudewo, Bupati Pajak dari Bumi Pesantenan (Bupati yang Lupa Kekuasaan Datang dari Rakyat)


Oleh: Ali Achmadi*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Saya tertegun. Bukan karena semata mata angka 250 persen itu. Tapi karena kepongahan seorang bupati yang belum genap setahun duduk di kursi empuk sebagai Bupati Pati. Angka bisa dibantah. Tapi narasi tak bisa dibohongi.
“Silakan demo! Jangankan lima ribu, lima puluh ribu pun saya tidak gentar!” Begitu ucap Sudewo, Bupati Pati.
Bukan dalam forum tertutup. Tapi di depan publik. Di hadapan masyarakat yang keberatan. Yang ‘megap-megap’ karena mendadak tanah dan rumahnya dikenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berkali lipat dari sebelumnya.
Saya membayangkan wajah-wajah petani di Gunungwungkal, pedagang kecil di Tayu, sampai guru honorer dan guru madrasah di Sukolilo.
Mereka bukan tak mau bayar pajak. Tapi mereka kaget. Bingung. Gelagepan! Dan ketika ingin bertanya, yang datang bukan jawaban—melainkan tantangan.
PBB adalah pajak yang paling dekat dengan rakyat. Namanya saja “bumi dan bangunan”. Kebanyakan orang punya, semua orang kena. Dan ironisnya: semakin diam rakyat, semakin tega pemerintah menaikkan. Ini bukan hanya soal pajak, ini soal arah kepemimpinan.
Seorang pemimpin sejati tahu bahwa kekuasaan datang dari rakyat, dan untuk rakyat. Ketika suara rakyat tidak didengar, ketika aksi protes dijawab dengan tantangan, maka sesungguhnya yang rusak bukan hanya relasi sosial, tapi juga legitimasi moral.
Kenaikan 250 persen ini bukan sekadar soal angka. Ini soal rasa. Dan keadilan. Apa pertimbangannya? Apa kajiannya? Di mana proses sosialisasinya?
Saya tidak tahu apakah Bupati Sudewo sedang mencoba jadi tokoh utama dalam novel distopia. Tapi gaya kepemimpinannya akhir-akhir ini lebih mirip gubernur militer zaman Orde Baru.
Yang rakyatnya diminta patuh tanpa banyak tanya. Yang kalau keberatan, dijawab: demo saja.
“Tidak boleh ada bargaining,” katanya lagi, merujuk pada perintahnya kepada camat dan kepala desa.
Artinya, rakyat tidak mengeluh, tidak boleh sambat. Tidak boleh mengajukan keberatan. Tidak boleh mengatur ulang zonasi. Pokoknya: harus manut. Titik!
Ini bukan cara memimpin yang beradab. Ini bukan cara memperlakukan rakyat yang sudah susah payah mencoblosnya di pilkada kemarin. Lalu, kenapa ini terjadi?
Ada yang bilang ini demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada yang menyebut ini bagian dari “ketegasan”. Ada pula yang mengaitkan ini dengan gaya Prabowo di pusat—yang katanya tegas dan berani.
Tapi mari kita bedakan antara tegas dan pongah. Tegas itu artinya adil dan konsisten. Pongah itu artinya: keras kepala dan merasa paling benar. Dan sayangnya, di titik ini, Sudewo tampak memilih jalan yang kedua.
Saya membayangkan seandainya Gus Dur masih ‘sugeng’ dan hari ini datang ke Pati, mungkin beliau akan mengajak sang bupati makan nasi gandul. Mungkin sambil bilang: “Wong itu butuh didengarkan, bukan ditantang.”
“Saya pernah jadi pemimpin. Dan saya tahu, semakin tinggi jabatan, seharusnya semakin rendah hati.”
Tapi Sudewo memilih naik jabatan sekaligus naik nada bicara. Entahlah. Saya cuma warga biasa. Yang tak punya panggung. Tapi punya pikiran. Dan perasaan.
Dan melihat hari ini, rakyat Pati merasa dicekik oleh pemimpinnya sendiri. PBB naik 250 persen. Aspirasi tak boleh dinegosiasi. Dan kritik dibalas tantangan untuk demo.
Ini bukan Pati yang dulu saya kenal. Ini bukan bupati yang dulu saya harapkan. Semoga elit-elit Gerindra di pusat—dan terutama Presiden Prabowo—mendengar ini.
Tahu bahwa kadernya di Pati sedang membuat rakyat mengelus dada. Bahwa kadernya bukan sedang mensejahterakan, tapi sedang mencekik.
Kalau tidak, jangan salahkan rakyat kalau di pemilu berikutnya, suara Pati berubah jadi sunyi. Atau lebih parah: jadi sorak-sorai demo, seperti yang diundang sendiri oleh sang bupati.
Sejarah akan mencatat, bukan hanya siapa yang pernah memimpin, tapi juga bagaimana ia memperlakukan rakyatnya. (Red)
*) Ali Achmadi, seorang praktisi pendidikan dan pemerhati masalah sosial, tinggal di Pati, Jawa Tengah