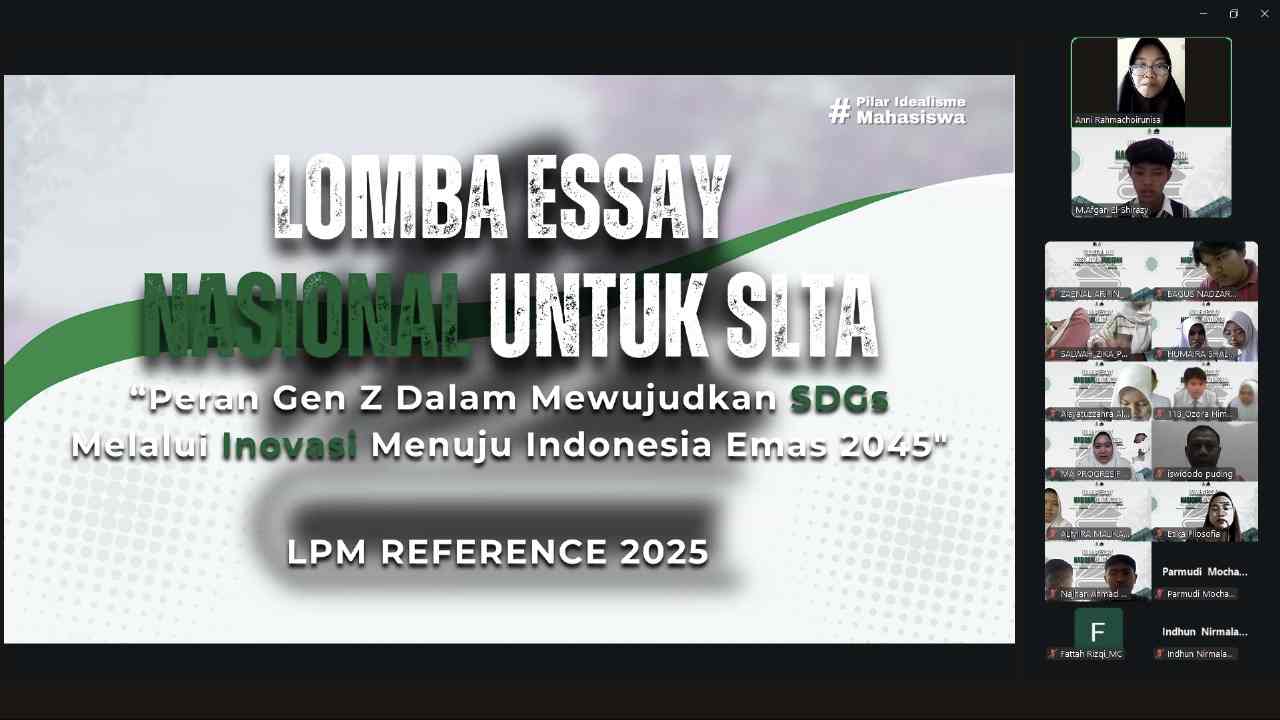Kursi Pedal Jepang dan Sindiran untuk Sistem Kita


SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Ada sebuah kisah ringan namun menohok. Seorang wisatawan Indonesia sedang melancong ke Jepang. Seperti kebanyakan turis, ia terpesona oleh keteraturan dan inovasi di negeri itu.
Di sebuah sudut jalan, ia melihat kursi publik dengan pedal seperti sepeda. Saat pedal itu dikayuh, listrik dihasilkan dan langsung dipakai untuk penerangan jalan.
Sambil duduk, ia berkata dalam hati, “Hebat sekali. Di sini, bahkan saat menunggu, mereka tidak membuang waktu dan tetap produktif.”
Di sampingnya duduk seorang pria Jepang. Percakapan pun dimulai.
“Tak heran Jepang maju,” kata si wisatawan. “Pasti karena orang-orangnya cerdas-cerdas.”
Pria Jepang tersenyum tipis. “Tidak juga,” jawabnya.
“Sebenarnya orang kami sama saja seperti masyarakat Anda. Bedanya, di sini, dari sepuluh orang Jepang, mungkin hanya satu yang benar-benar pintar dan sembilan lainnya biasa-biasa saja, bahkan bodoh.”
Wisatawan itu terdiam, agak heran. Lalu pria Jepang melanjutkan:
“Tetapi kami menempatkan satu orang pintar itu sebagai pemimpin, dan sembilan lainnya cukup mengikuti instruksinya. Di negara Anda,” ia menghela napas, “justru kebalikannya: satu yang bodoh memimpin, dan sembilan yang pintar harus mengikuti instruksinya.”
Hening. Angin musim gugur berdesir di antara pepohonan. Kalimat itu mungkin terdengar keras, bahkan menyinggung. Tetapi bukankah kerap kita temui fenomena serupa?
Bukan hanya di politik, tetapi juga di kantor, organisasi, bahkan komunitas kecil. Sering kali, mereka yang memiliki gagasan segar dan wawasan luas justru berada di bangku penonton, sementara kursi kemudi diduduki oleh mereka yang tidak layak—atau setidaknya, tidak cukup mumpuni.
Jepang bukan tanpa masalah. Mereka pun punya birokrat lamban, politisi bermasalah, dan keputusan publik yang keliru. Namun satu hal yang membedakan adalah sistem mereka relatif mampu meminimalisir kerusakan: menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat.
Di kita? Sistemnya justru sering kali menyaring orang berdasarkan kedekatan, loyalitas semu, atau kepentingan kelompok, bukan kompetensi. Atau bahkan kita memilih pemimpin karena pemberian bansos.
Di kita, sistemnya sering kali seperti saringan terbalik. Yang lolos ke atas bukan yang paling mumpuni, melainkan yang paling pandai berbisik di telinga orang berkuasa, atau yang paling rajin hadir di acara foto bersama.
Akibatnya, sembilan orang pintar menjadi frustrasi, kreativitas terhambat, dan potensi bangsa terkubur di bawah tumpukan keputusan konyol.
Padahal, dari kursi pedal di pinggir jalan itu, ada pelajaran sederhana: kemajuan bukan soal berapa banyak orang pintar yang kita punya, tapi siapa yang memegang kemudi.
Satu orang pintar yang benar-benar memimpin akan membuat sembilan yang biasa-biasa saja ikut berlari. Tapi satu orang bodoh di pucuk pimpinan bisa membuat sembilan orang pintar ikut tersesat … bahkan terseret mundur.
Mungkin sudah saatnya kita membalik kebiasaan. Menempatkan yang cakap di kursi pengemudi. Membiarkan yang belum mumpuni duduk manis di kursi penumpang—atau kalau mau tetap berkontribusi, silakan duduk di kursi pedal. Kayuhlah kencang-kencang. Setidaknya, jalannya akan tetap terang. (Red)
Ali Achmadi, praktisi pendidikan, pemerhati masalah sosial, tinggal di Pati, Jawa Tengah