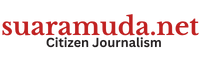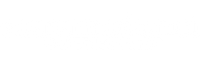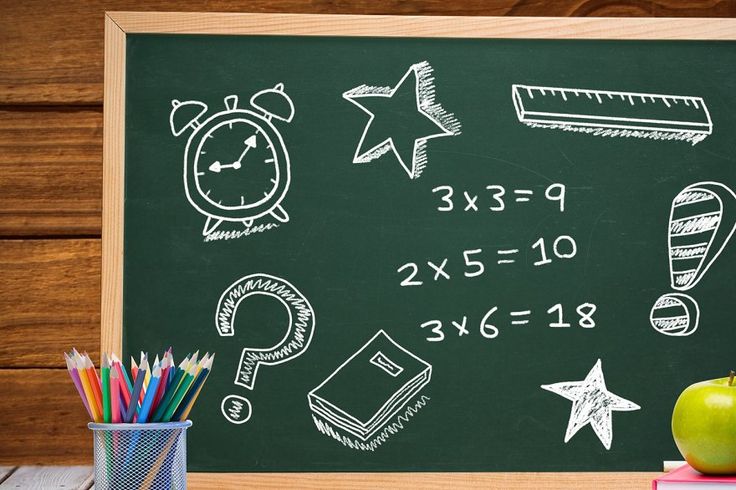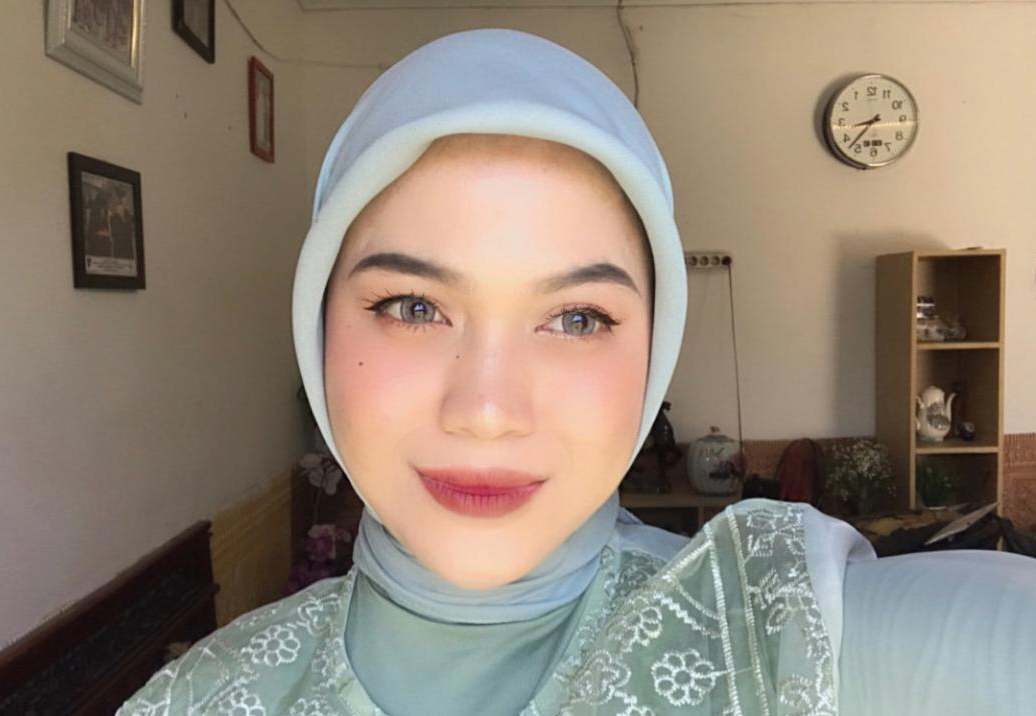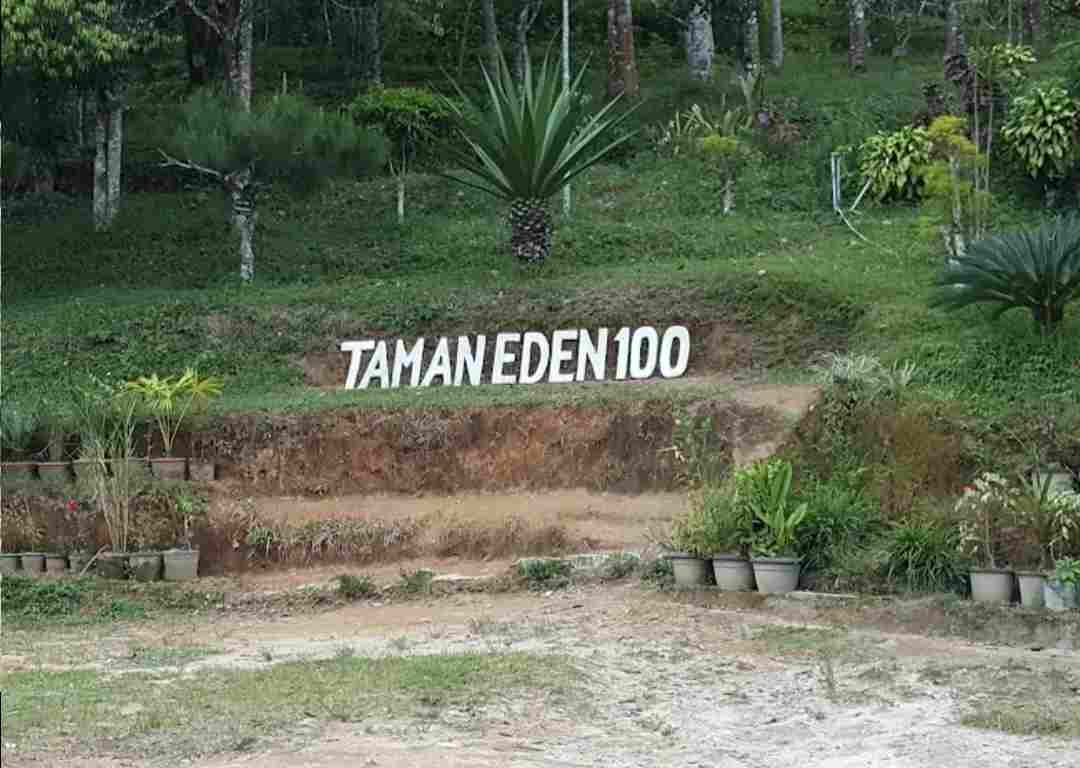Kelas Menengah di Ambang Krisis: Ketimpangan Struktural dan Ancaman terhadap Stabilitas Sosial-Ekonomi Indonesia


Oleh: Raia Malika Wajdi, Najma Yudhi dan Nabilah Ayu Azalia*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Masalah ketenagakerjaan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional Indonesia. Meskipun tingkat pendidikan masyarakat meningkat setiap tahunnya, ketersediaan lapangan pekerjaan belum mampu mengimbangi jumlah lulusan baru yang terus bertambah.
Akibatnya, banyak fresh graduate mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan kompetensinya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 7,28 juta orang per Februari 2025, dengan tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan perguruan tinggi mencapai 5,25% (Liputan6, 2025).
Fenomena ini menunjukan adanya ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Pertumbuhan ekonomi yang belum merata, keterbatasan sektor industri padat karya, serta pergeseran struktur ekonomi menuju digitalisasi menjadi beberapa faktor penyebabnya (Kompas, 2025).
Di sisi lain, banyak fresh graduate belum memiliki keterampilan praktis dan soft skills yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja modern.
Penelitian oleh Natalia dan Putranto (2022) menunjukkan bahwa faktor pelatihan dan pengalaman kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap peluang kerja bagi lulusan baru.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan psikologis. Pengangguran di kalangan terdidik dapat menurunkan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, serta memunculkan ketidakstabilan sosial di masyarakat (UGM, 2025).
Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor industri untuk menciptakan sinergi dalam memperluas lapangan pekerjaan serta menyesuaikan kurikurlum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja yang dinamis.
Perspektif Ekonomi-Politik
Dari perspektif ekonomi-politik, struktur ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada investasi asing dan ekspor komoditas. Pola pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan di pusat-pusat industri seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur membuat kesenjangan regional semakin lebar.
Kompas (2023) mencatat bahwa investasi dan aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah metropolitan, sedangkan daerah pedesaan di luar Jawa tertinggal akibat minimnya pemerataan investasi dan infrastruktur.
Akibatnya, akumulasi modal tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja di daerah (Kompas, 19 Februari 2023).
Ketergantungan pada modal asing membuat ekonomi nasional lebih fokus pada efisiensi dan keuntungan investor daripada penciptaan kerja produktif yang berpihak pada rakyat.
Industrilisasi yang lemah juga kian memperburuk situasi. Penelitian Nababan dan Purba (2023) menunjukkan adanya fenomena “anomali” dan “regresif” di sektor manufaktur-produktivitas industri meningkat, tetapi penyerapan tenaga kerja justru menurun.
Peralihan ke industri padat modal dan otomasi menyebabkan banyak sektor padat karya, seperti tekstil dan sepatu, kehilangan daya saing dan tenaga kerja. Kebijakan industrilisasi selama ini mendorong efisiensi teknologi tanpa mempersiapkan program transisi keahlian bagi pekerja yang terdampak.
Akibatnya, tenaga kerja Indonesia terpinggirkan dari proses modernisasi industri yang seharusnya bisa menjadi pendorong kesejahteraan.
Fenomena ini juga tergambarkan dalam laporan Kompas (2024) tentang tumbangnya industri padat karya yang menciptakan gelombang PHK besar-besaran.
Pemerintah memang memberi insentif besar bagi investor asing melalui tax holiday dan kemudahan berusaha, tetapi belum memiliki strategi jangka panjang untuk memastikan investasi menciptakan lapangan kerja nasional (Kompas, 27 Februari 2024).
Pola ini memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia masih menjadi bagian dari dependent capitalist economy, yakni sistem yang bergantung pada modal dan pasar eksternal tanpa kemandirian struktural dalam rantai nilai global.
Dengan demikian, arah pembangunan Indonesia masih bersifat sentralistrik dan eksklusif. Fokus pada pertumbuhan ekonomi belum diimbangi dengan pemerataan manfaat dan keadilan sosial.
Karena itu, reformasi ekonomi perlu menekankan redistribusi hasil produksi, desentralisasi industri ke luar Jawa, serta perlindungan pekerja dari dampak disrupsi teknologi agar pembangunan lebih adil dan inklusif.
Kondisi ini juga mempengaruhi aspek sosial dan politik di tingkat nasional. Ketidaksetaraan struktural dalam pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang luas pada sektor sosial-politik di Indonesia.
Perbedaan antarwilayah dan kelas sosial menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah, melemahkan kohesi sosial, serta memicu perpecahan politik dan kemungkinan terjadinya konflik antar kelompok di masyarakat.
Meningkatnya jumlah pengangguran yang terdidik dan urbanisasi tanpa adanya dukungan lapangan kerja yang memadai juga menambah tekanan sosial serta mengurangi kepercayaan terhadap efektivitas kebijakan pemerintah.
Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, situasi ini bisa mengancam stabilitas politik nasional dan menghalangi tercapainya pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Untuk keluar dari jebakan struktural dan ancaman middle-income trap, Indonesia harus mengarahkan kebijakan ekonominya ke industrilisasi padat karya dan ekonomi hijau.
BRIN (2024) menyoroti bahwa kelas menengah kini menjadi golongan yang paling rentan karena stagnasi daya beli dan terbatasnya lapangan kerja produktif.
Berita Nasional (2024) menegaskan bahwa peningkatan produktivitas dan diversifikasi sektor di luar Jawa menjadi langkah penting untuk mendorong pemerataan pembangunan. Industrilisasi berbasis tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan dapat memperkuat daya saing sekaligus mengurangi ketimpangan regional.
Selain itu, pembangunan harus memperkuat ekonomi lokal dan UMKM berbasis komunitas sebagai pilar kemandirian ekonomi rakyat.
Kompas (2024) menggambarkan kondisi kelas menengah yang sulit untuk menambah penghasilan, dimana hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa ruang untuk menabung.
Hal ini menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku ekonomi rakyat. Pemerintah harus memperluas akses pembiayaan murah, teknologi, dan pendampingan usaha bagi UMKM agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan dari bawah, bukan hanya oleh kelompok elit atau investor besar.
Dalam bidang ketenagakerjaan, reformasi perlu difokuskan pada peningkatan keterampilan dan perlindungan pekerja, bukan hanya fleksibelitas.
Berita Nasional (2024) menekankan pentingnya reskilling dan upskilling agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar global.
Program pelatihan vokasional, insentif bagi perusahaan pencipta kerja, dan jaminan sosial bagi pekerja, informal menjadi langkah penting memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Akhirnya, negara harus berperan aktif sebagai penggerak utama pemerataan ekonomi. Kompas Biz (2017) menegaskan bahwa pemerataan tidak cukup hanya dengan equality, tetapi harus berlandaskan equity.
Negara perlu mengoptimalkan peran BUMN, proyek padat karya, dan kebijakan fiskal afirmatif untuk daerah tertinggal. Dengan intervensi negara yang kuat, pembangunan dapat diarahkan tidak hanya untuk pertumbuhan, tetapi juga untuk keadilan sosial dan kemandirian ekonomi nasional.
Secara keseluruhan, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia mencerminkan tantangan struktural dalam sistem ekonomi yang masih terpusat, bergantung pada investasi asing, dan belum sepenuhnya mendukung distribusi kesejahteraan masyarakat.
Ketidakseimbangan ekonomi yang meluas telah menyebabkan berbagai masalah sosial dan politik yang rumit, mulai dari meningkatnya jumlah pengangguran yang berpendidikan hingga menurunnya stabilitas sosial.
Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengarahkan kebijakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berfokus pada pembukaan lapangan kerja yang produktif.
Kerja sama antara pemerintah, sektor industri, dan institusi pendidikan menjadi kunci untuk membangun dasar ekonomi nasional yang mandiri, kompetitif, dan mampu menjamin pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. (Red)
*) Penulis: Raia Malika Wajdi, Najma Yudhi dan Nabilah Ayu Azalia, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya