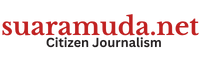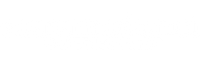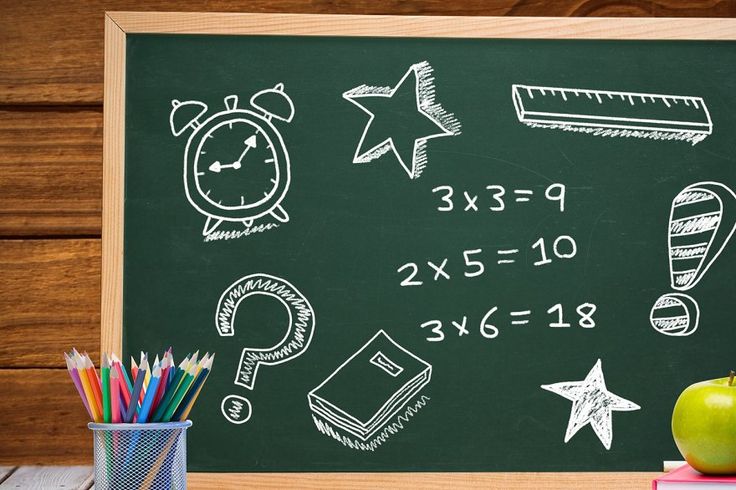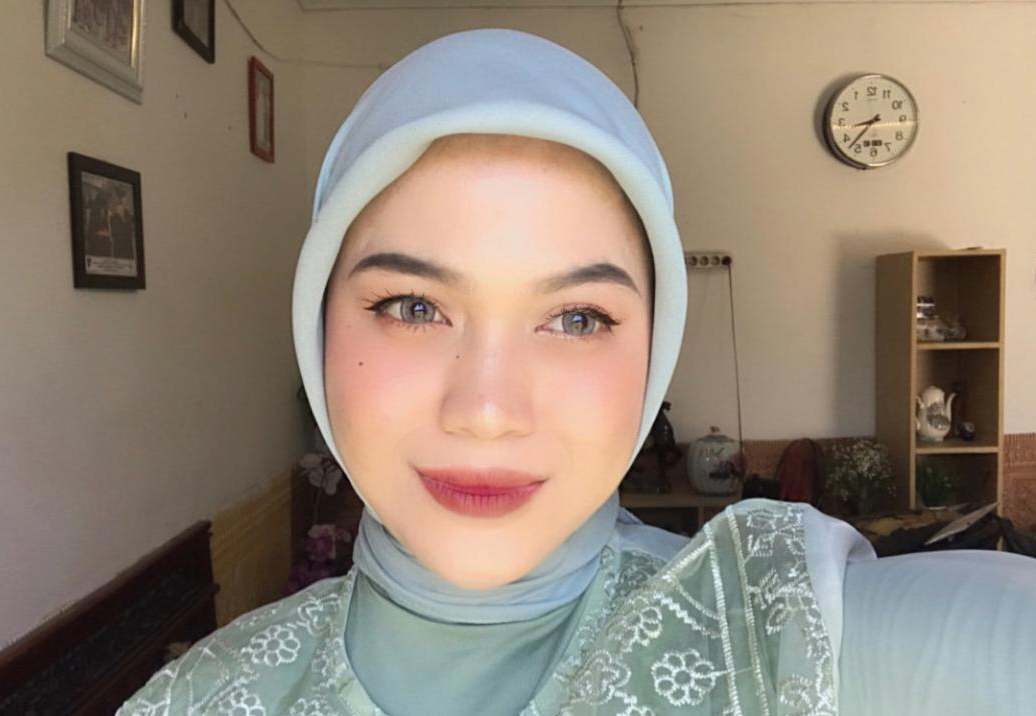Rangkong Terancam Punah: Ketika Tahura Pocut Meurah Intan Gagal Menjaga Rumahnya.


Oleh: Julaiha *)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Tahura Pocut Meurah Intan di Aceh merupakan salah satu kantong biodiversitas paling penting di Sumatra, terutama bagi kelompok burung rangkong (Bucerotidae) yang dikenal sebagai indikator kesehatan ekosistem.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, tekanan ekologis—mulai dari deforestasi ilegal, perburuan hingga fragmentasi habitat mendorong populasi rangkong di kawasan ini menuju kondisi yang mengkhawatirkan.
Burung rangkong selalu digambarkan sebagai “penjaga hutan” atau “penyebar biji terbaik” dalam narasi konservasi. Namun, di kawasan Pocut Meruah Intan, label-label indah itu kini terasa seperti ironi.
Konservasi rangkong tampak berjalan, tetapi realitas lapangan menunjukkan bahwa upaya perlindungan ini masih jauh dari kata berhasil.
Pocut Meruah Intan memiliki potensi ekologis luar biasa sebagai habitat rangkong. Struktur hutan, ketersediaan ceruk pohon besar, hingga keanekaragaman tumbuhan buah menjadikannya wilayah yang ideal bagi berbagai spesies rangkong.
Namun potensi saja tidak pernah cukup. Kemampuan suatu kawasan dalam mempertahankan rangkong ditentukan oleh stabilitas ekologi dan konsistensi perlindungan, dua hal yang kini rapuh di Pocut Meruah Intan.
Salah satu masalah paling mendesak adalah penyusutan pohon-pohon berdiameter besar, tempat rangkong bersarang secara alami. Banyak dari pohon ini ditebang—baik secara legal maupun ilegal—karena dianggap bernilai ekonomi tinggi.
Di sinilah dilema konservasi muncul: bagaimana mungkin kita menuntut rangkong bertahan jika rumah mereka terus dihancurkan? Kita tidak sedang menyelamatkan burung; kita hanya memperlambat kepunahannya.
Rangkong bukan tipe burung yang cepat beradaptasi dengan perubahan drastis. Mereka membutuhkan hutan yang lebat, pohon raksasa, dan ketenangan ekologis.
Sementara itu, Pocut Meruah Intan kini menghadapi tekanan dari pembukaan lahan, pembalakan, dan fragmentasi habitat.
Para pemangku kebijakan sering berkilah bahwa area inti masih aman, tetapi rangkong tidak hidup berdasarkan batas-batas administrasi. Burung ini terbang mengikuti ketersediaan buah, bukan garis peta. Fragmentasi satu petak saja sudah cukup mengganggu pola jelajahnya.
Selain habitat, ancaman lain yang tak kalah memprihatinkan adalah perburuan. Meski undang-undang telah memberi perlindungan penuh, praktik perburuan rangkong masih terjadi dalam bentuk yang lebih terselubung.
Tanduk rangkong gading (hornbill ivory) masih memiliki pasar gelap, sementara dagingnya kadang diburu untuk konsumsi lokal.
Yang menyakitkan adalah kenyataan bahwa nilai ekonominya—baik untuk tanduk maupun daging—tidak sebanding dengan nilai ekologis yang mereka bawa sebagai penyebar biji bagi spesies pohon hutan bernilai tinggi.
Konservasi rangkong di Pocut Meruah Intan juga menderita karena kurangnya integrasi antara penelitian, kebijakan, dan pengelolaan lapangan. Banyak penelitian dilakukan, laporan disusun, tetapi temuan-temuan itu jarang sekali diterjemahkan menjadi kebijakan tegas.
Program edukasi berjalan, tetapi minim evaluasi. Kegiatan survei dilakukan, tetapi tidak menerjemah menjadi pengawasan rutin. Akibatnya? Rangkong tetap terancam, dan konservasi berjalan seperti ritual tahunan tanpa dampak jangka panjang.
Lebih ironis lagi, keterlibatan masyarakat lokal sering hanya menjadi jargon proyek. Padahal masyarakat adalah ujung tombak konservasi. Mereka yang tinggal di pinggir kawasan hutan seharusnya menjadi mitra utama, bukan sekadar penerima sosialisasi.
Ketika masyarakat tidak diberi ruang sebagai penjaga hutan, konservasi hanya menjadi proyek dari atas—lepas dari realitas di bawah. Jika konservasi rangkong di Pocut Meruah Intan ingin keluar dari “zona simbolik” menuju “zona efektif”, maka ada beberapa upaya yang wajib dilakukan.
Pertama, moratorium penebangan pohon besar harus diberlakukan, apa pun status lahannya. Ini harga mati. Tanpa pohon besar, rangkong tidak bisa berkembang biak. Kedua, penguatan patroli berbasis masyarakat harus dilakukan. Bukan sekadar patroli formal, tetapi model partisipatif di mana warga menjadi mata dan telinga pertama dalam mencegah perburuan.
Ketiga, restorasi habitat harus berfokus pada penanaman pohon penghasil buah dan pohon yang berpotensi menjadi sarang dalam jangka panjang. Restorasi tidak bisa hanya menanam bibit murah yang cepat tumbuh tetapi tidak bernilai ekologis untuk rangkong.
Keempat, penegakan hukum tanpa kompromi. Perburuan rangkong harus menjadi prioritas hukum, bukan dianggap sebagai pelanggaran kecil. Jika pelaku hanya diberi peringatan, itu sama saja memberi lampu hijau untuk perburuan berikutnya.
Kelima, kolaborasi jangka panjang antara peneliti, pemerintah, dan masyarakat harus dibangun. Pada akhirnya, rangkong di Pocut Meruah Intan bukan hanya burung karismatik.
Burung rangkong adalah indikator kesehatan hutan dan penentu regenerasi ekosistem. Jika rangkong hilang, itu bukan sekadar hilangnya satu spesies—tetapi hilangnya masa depan hutan itu sendiri. (Red)
*) Penulis: Julaiha, mahasiswa Program Pascasarjana Prodi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara.