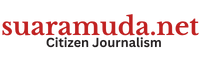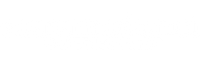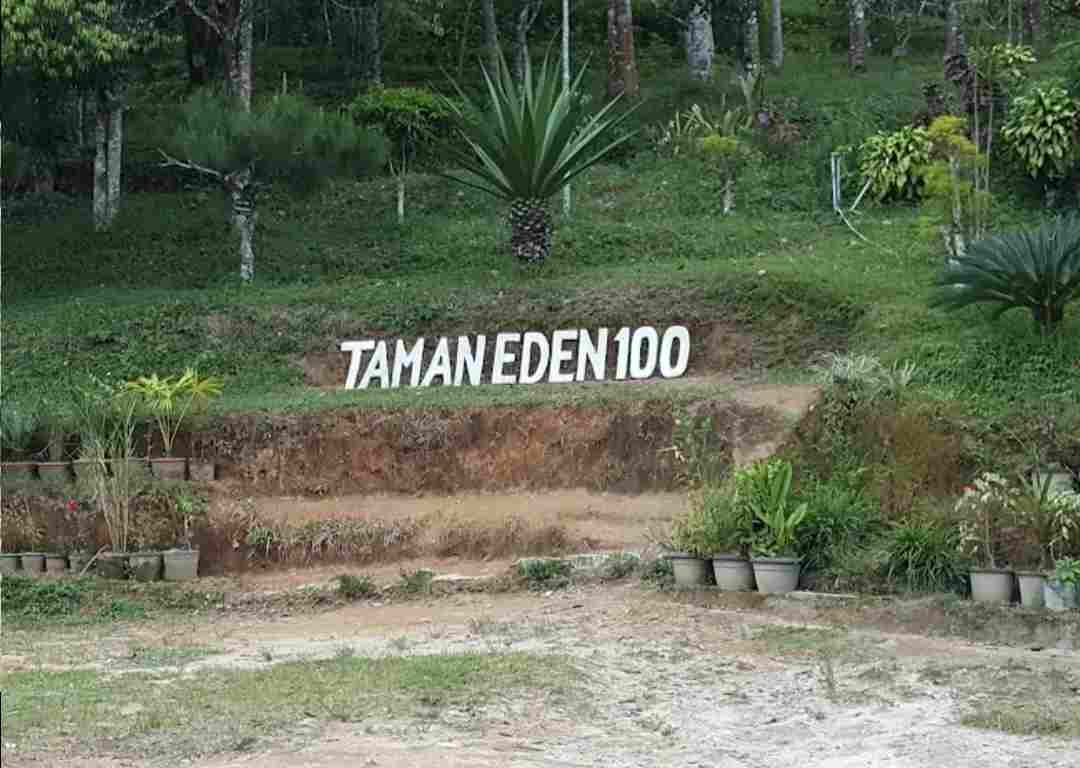Karhutla Sumatera: Krisis Ekologi yang Tak Boleh Terulang Lagi
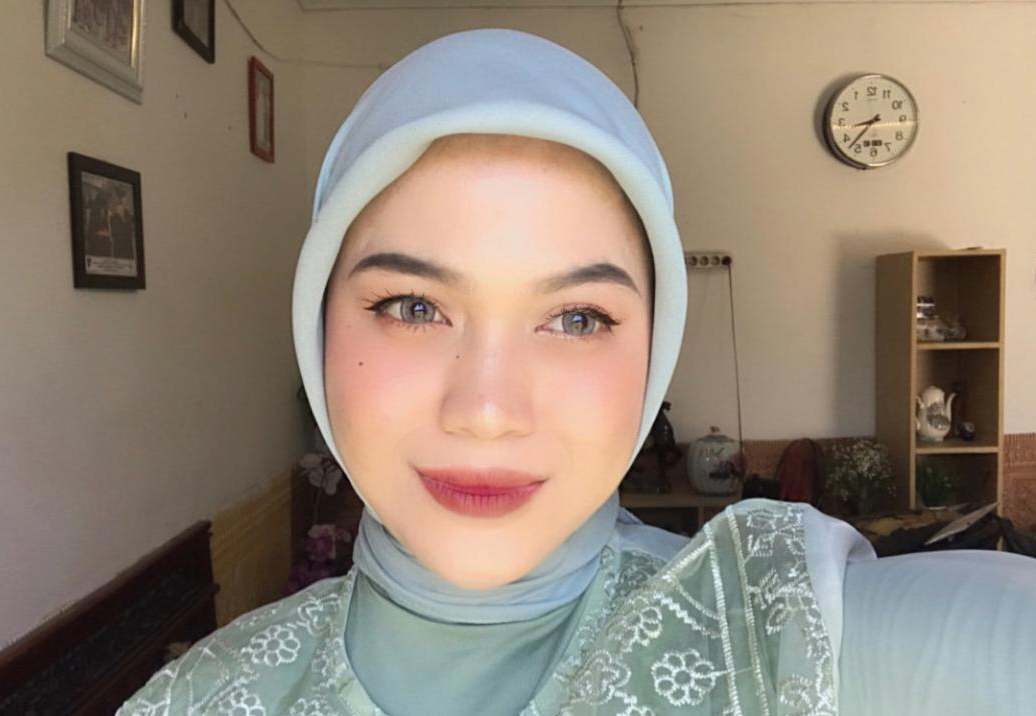

Oleh: Amanda Savira *)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera kembali mencuat sepanjang 2025. Data terbaru menunjukkan ratusan hektar lahan telah hangus terbakar, sebagian besar berada di kawasan gambut dan area penggunaan lain.
Fenomena ini bukan sekadar peristiwa tahunan, melainkan gejala mendalam dari tata kelola lingkungan yang bermasalah. Akar persoalan karhutla bersumber dari kombinasi faktor: praktik pembukaan lahan dengan membakar, lemahnya pengawasan izin, tekanan industri perkebunan, hingga dampak iklim global seperti El Niño yang memperpanjang musim kemarau.
Lahan gambut yang kering berubah menjadi “bahan bakar alami” sehingga api sulit dikendalikan. Akibatnya, yang kita hadapi bukan hanya hilangnya tutupan hutan, tetapi juga krisis ekologis, kesehatan, dan sosial-ekonomi.
Sebagai mahasiswa Pascasarjana Biologi, saya melihat karhutla dari kacamata ekosistem. Api yang membakar hutan bukan hanya merusak pepohonan, melainkan juga menghancurkan mikrobioma tanah yang menopang kesuburan, mempercepat degradasi habitat, dan mengancam keberlangsungan biodiversitas tropis.
Pandangan ini penting karena menegaskan bahwa karhutla bukan sekadar bencana asap, tetapi krisis ekologis yang meninggalkan luka jangka panjang.
Posisi mahasiswa Pascasarjana tidak berhenti pada kritik, tetapi dituntut untuk mengembangkan solusi aplikatif yang bisa menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Solusi karhutla harus ditempuh secara berlapis. Pertama, pencegahan harus menjadi prioritas utama. Praktik pembukaan lahan tanpa bakar harus diperluas, sistem deteksi dini berbasis satelit dan sensor lapangan perlu diperkuat, dan lahan gambut harus dikelola dengan sekat kanal agar tetap basah.
Kedua, rehabilitasi ekosistem perlu dilakukan pasca kebakaran: pemulihan vegetasi asli, penggunaan tanaman pionir, hingga inokulasi mikroba tanah untuk memperbaiki kesuburan.
Ketiga, kolaborasi masyarakat lokal sangat penting. Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan rawan kebakaran harus diberi insentif dan pengetahuan agar menjadi mitra pencegahan, bukan dianggap ancaman.
Terakhir, penguatan regulasi dan riset wajib dijalankan: sanksi tegas untuk pelaku pembakaran lahan, serta dukungan pendanaan bagi riset ekologi tropis dari perguruan tinggi agar bisa diterapkan di lapangan.
Prospek ke depan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kita berani bergeser dari pola pikir reaktif menuju pendekatan preventif berbasis sains.
Jika riset ekologis diberi ruang dalam kebijakan publik, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari siklus karhutla berulang.
Teknologi ramah lingkungan, bioindikator ekosistem, hingga strategi adaptasi iklim bisa menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan lahan yang berkelanjutan.
Karhutla di Sumatera adalah pengingat bahwa hutan bukan sekadar sumber daya ekonomi, tetapi fondasi kehidupan.
Jika akar masalah diatasi, solusi diterapkan dengan konsisten, dan sains dijadikan rujukan utama, maka masa depan hutan tropis Indonesia tidak hanya bisa diselamatkan, tetapi juga diwariskan lebih baik kepada generasi berikutnya. (Red)
*) Penulis: Amanda Savira, mahasiswa Program Pascasarjana Prodi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara