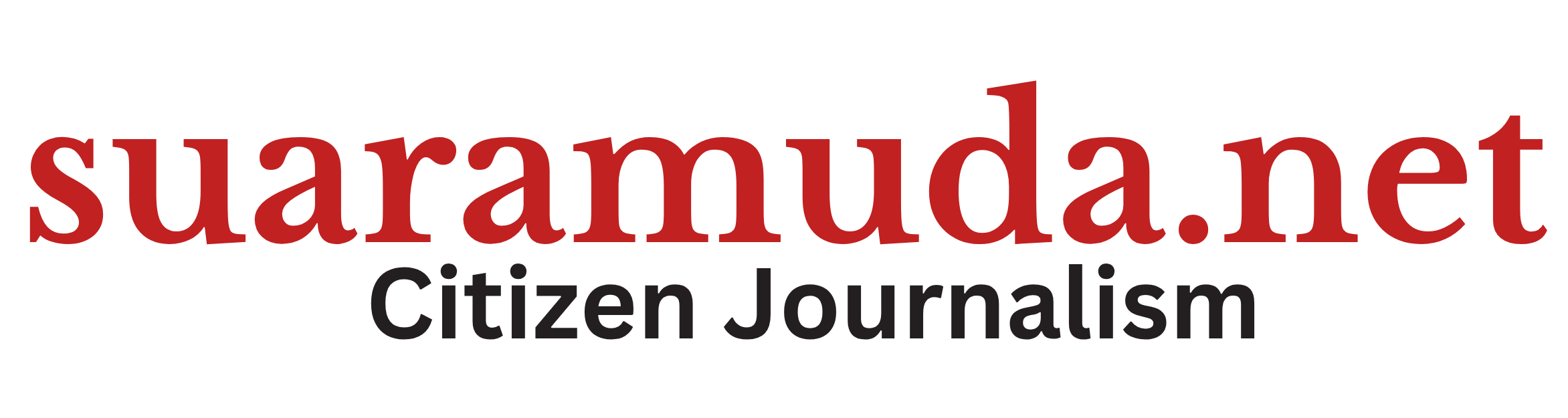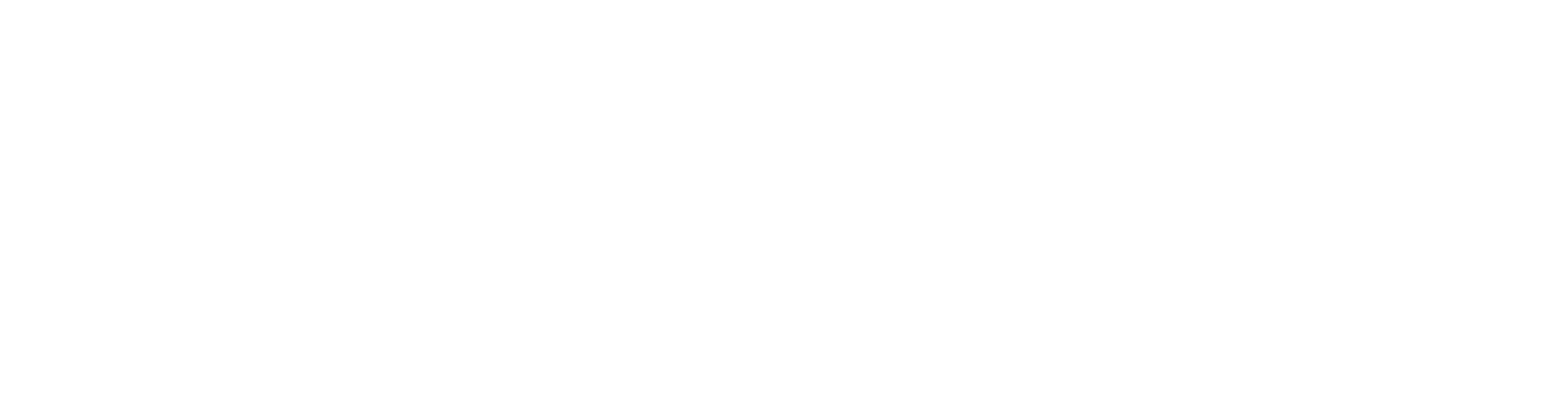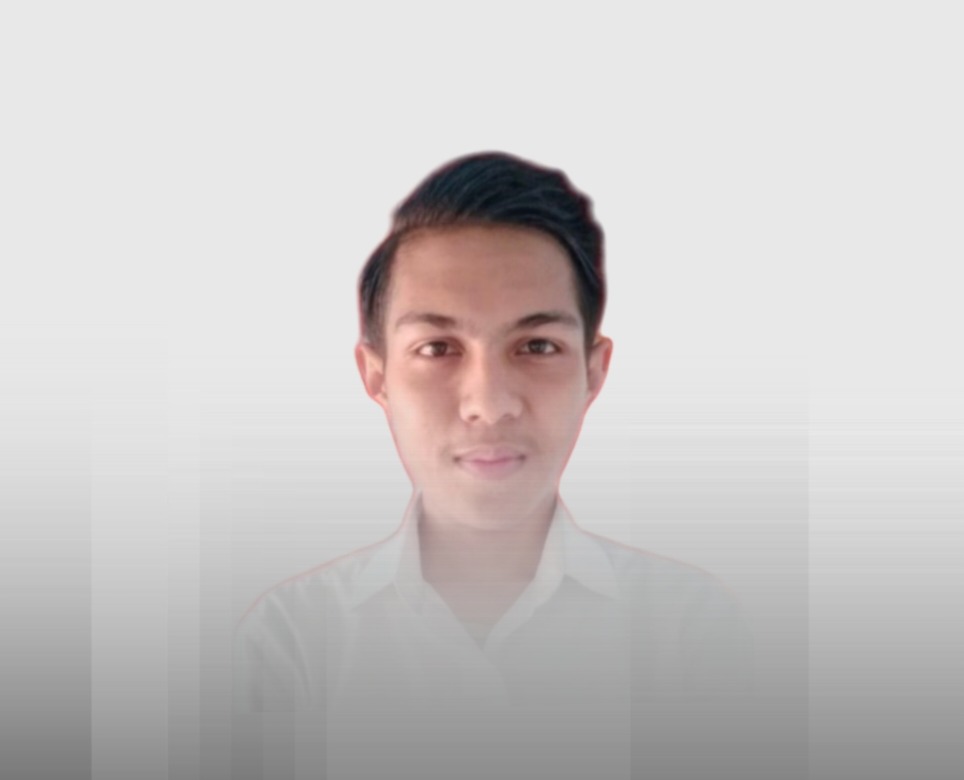Alarm Merah Reformasi Sektor Keamanan: RUU Polri & UU TNI dalam Pusaran Kuasa Negara yang Membeku
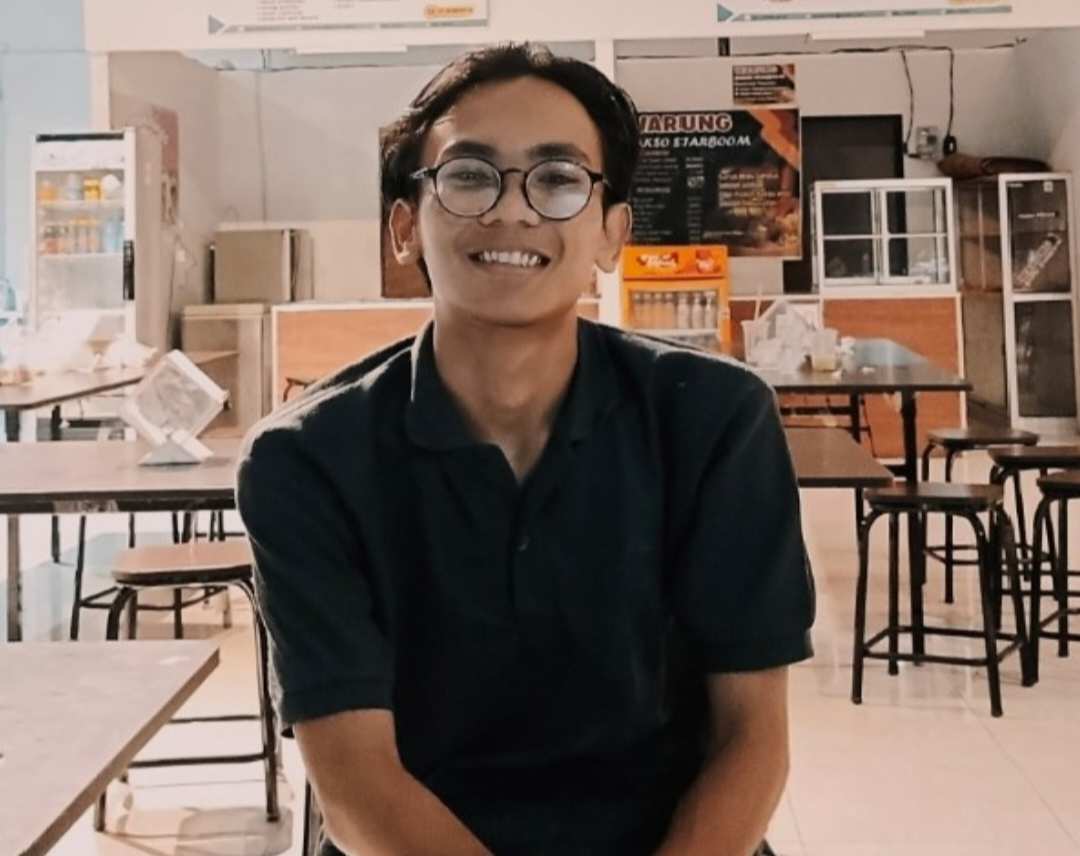
Oleh : Adjie Shaofani Elsayyid *)
SUARAMUDA, SEMARANG — Gema Reformasi 1998, yang meruntuhkan rezim otoriter Orde Baru, membawa mandat suci untuk merombak total arsitektur keamanan negara.
Salah satu pilar utamanya adalah pemisahan tegas antara fungsi pertahanan negara dan fungsi keamanan dalam negeri serta penegakan hukum.
Melalui Ketetapan MPR (Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri), Republik ini berkomitmen menempatkan TNI sebagai alat pertahanan di bawah UU No. 34 Tahun 2004, dan Polri sebagai institusi sipil penjaga kamtibmas dan penegak hukum di bawah UU No. 2 Tahun 2002.
Landasan ini adalah fondasi krusial bagi tegaknya supremasi sipil, negara hukum, dan demokrasi yang sehat.
Namun, lebih dari dua dekade setelah fajar Reformasi menyingsing, kita justru menyaksikan gejala yang mengkhawatirkan: reformasi sektor keamanan tampak membeku, bahkan berisiko ditarik mundur.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Polri yang sarat kontroversi berjalan nyaris senyap, mengusung agenda inflasi kuasa yang berpotensi mengubah Polri menjadi ‘leviathan’ baru.
Pada saat yang sama, UU TNI yang ada, meskipun membatasi peran militer, masih menyisakan ‘zona abu-abu’ melalui klausul Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang rentan ditarik-tarik untuk melegitimasi intervensi militer ke ranah sipil.
Kombinasi mengerikan ini bukan sekadar persoalan teknis legislasi; ia adalah alarm merah yang berbunyi nyaring, menandakan bahaya laten kembalinya Indonesia ke pusaran kuasa negara keamanan (security state) yang represif, di mana hak warga negara diobral murah atas nama stabilitas semu.
RUU Polri: Hasrat Kuasa Tanpa Batas, Menggilas Hak Sipil
Mari kita bedah lebih dalam ambisi yang terkandung dalam RUU Polri ini. Dalih kebutuhan menghadapi kejahatan transnasional, terorisme, dan terutama kejahatan siber, memang tak sepenuhnya salah.
Namun, solusi yang ditawarkan—perluasan kewenangan yang drastis—justru jauh panggang dari api. Kewenangan untuk melakukan ‘patroli siber’, misalnya, adalah istilah manis untuk pengawasan massal tanpa pandang bulu di ruang digital.
Bayangkan algoritma atau bahkan petugas secara aktif memantau percakapan privat, aktivitas media sosial, hingga jejak digital warga atas nama ‘pencegahan’.
Ini adalah serangan langsung terhadap hak privasi yang dijamin konstitusi (Pasal 28G UUD 1945) dan akan menciptakan chilling effect yang membekukan kebebasan berpendapat dan berekspresi (Pasal 28E & 28F UUD 1945).
Kritik terhadap pemerintah, satire politik, atau bahkan diskusi internal aktivis bisa dengan mudah dicap ‘hoaks’, ‘ujaran kebencian’, atau ‘ancaman kamtibmas’ untuk kemudian ditindak.
Apakah ini yang kita inginkan? Ruang digital yang steril dari perbedaan pendapat, diawasi oleh ‘mata-mata’ negara berseragam?
Lebih jauh, perluasan fungsi intelijen keamanan bagi Polri adalah langkah mundur yang mengacaukan arsitektur intelijen negara.
Selain berpotensi tumpang tindih kewenangan secara destruktif dengan Badan Intelijen Negara (BIN) atau Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2011, ini secara fundamental berbahaya.
Fungsi intelijen yang identik dengan operasi klandestin dan pengumpulan informasi sensitif, jika digabungkan dengan kewenangan penegakan hukum (menangkap, menahan, menyidik), akan menciptakan kekuatan koersif yang luar biasa besar di tangan Polri.
Batas antara mengumpulkan informasi untuk ‘pencegahan’ dan menggunakannya untuk ‘menargetkan’ lawan politik atau kelompok kritis menjadi sangat tipis. Ini adalah resep klasik negara otoriter.
Celakanya, dahaga akan kuasa baru ini sama sekali tidak diimbangi oleh penguatan mekanisme akuntabilitas yang berarti. RUU ini tampak seperti lelucon pahit ketika bicara soal pengawasan.
Kita semua tahu bagaimana mekanisme internal seperti Propam seringkali bekerja lamban, tertutup, dan terkesan melindungi korps (esprit de corps yang kebablasan).
Pengaduan masyarakat kerap menemui jalan buntu atau proses berbelit. Lembaga eksternal seperti Kompolnas? Fungsinya lebih mirip penasihat ompong ketimbang pengawas independen yang ditakuti.
Dimana terobosan dalam RUU ini? Dimana penguatan independensi dan kewenangan Kompolnas untuk melakukan investigasi mandiri dan memberikan rekomendasi yang mengikat? Dimana mekanisme perlindungan bagi pelapor (whistleblower) atau korban?
Absennya hal-hal fundamental ini menunjukkan bahwa RUU Polri lebih berfokus pada penambahan kuasa untuk aparat, bukan penambahan perlindungan dan keadilan untuk rakyat.
Ini adalah pengkhianatan terang-terangan terhadap semangat Reformasi yang menghendaki Polri yang profesional, humanis, dan akuntabel. Kultur impunitas yang selama ini mengakar bukannya dicabut, malah berpotensi diberi pupuk baru.
UU TNI: OMSP Sebagai ‘Pintu Belakang’ dan Hantu Dwifungsi
Di sisi lain, sementara UU TNI (UU No. 34/2004) secara normatif membatasi peran TNI pada pertahanan negara, ia menyisakan ‘tumit Achilles’ melalui konsep OMSP.
Daftar 14 jenis OMSP memang mencakup tugas-tugas yang relevan seperti operasi perdamaian dunia atau bantuan kemanusiaan. Namun, beberapa poin lain sangat lentur dan multi-interpretatif.
Tugas “membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan” atau “membantu tugas pemerintahan di daerah” dan “membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang,” jika tidak disertai batasan dan prosedur yang super ketat, bisa menjadi ‘pintu belakang’ bagi militer untuk merambah kembali ke urusan domestik.
Prosedur pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP yang mensyaratkan keputusan politik negara (Presiden dengan persetujuan DPR untuk OMSP terkait perang/ konflik, atau kebijakan Presiden untuk OMSP lainnya) juga tidak sepenuhnya anti peluru terhadap politisasi.
Dalam konstelasi politik tertentu, atau dengan dalih ‘darurat’ yang diciptakan, pengerahan TNI untuk tugas-tugas yang seharusnya menjadi domain sipil atau kepolisian bisa saja terjadi. Kita tidak boleh lupa hantu Dwifungsi ABRI yang pernah mencengkeram Indonesia.
Logika bahwa militer adalah solusi untuk segala masalah, mulai dari terorisme, bencana alam, hingga ‘ketahanan pangan’, adalah warisan berbahaya yang bisa hidup kembali melalui interpretasi OMSP yang serampangan.
Penempatan perwira TNI aktif di jabatan-jabatan sipil, yang sempat surut namun kadang muncul kembali, adalah indikator bahwa godaan untuk melampaui batas konstitusional itu selalu ada.
Rapuhnya Benteng Akuntabilitas Ganda
Situasi menjadi semakin suram ketika kita menyadari bahwa kedua institusi raksasa ini sama-sama memiliki persoalan akuntabilitas kronis.
Jika RUU Polri gagal memperkuat pengawasan sipil terhadap polisi, maka sistem peradilan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana, terutama yang melibatkan korban sipil, juga jauh dari ideal. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer acap kali dikritik karena bersifat tertutup, mengedepankan jiwa korsa, dan sulit memberikan rasa keadilan bagi korban di luar lingkungan militer.
Bertahun-tahun suara publik dan rekomendasi Komnas HAM agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum tak kunjung membuahkan hasil signifikan.
Akibatnya, kita memiliki dua sistem akuntabilitas paralel yang sama-sama rapuh dalam melindungi hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat bersenjata.
Ini menciptakan zona impunitas ganda yang sangat berbahaya bagi supremasi hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 27 UUD 1945).
Supremasi Sipil Terancam, ‘Securitocracy’ Mengintai
Kombinasi dari Polri yang berpotensi menjadi ‘super-body’ minim akuntabilitas dan TNI yang memiliki ‘celah legal’ untuk intervensi domestik adalah ancaman langsung terhadap prinsip fundamental supremasi sipil.
Supremasi sipil bukan sekadar jargon, ia bermakna kontrol efektif institusi sipil yang dipilih secara demokratis (Presiden, DPR) atas kebijakan pertahanan dan keamanan, alokasi anggaran, dan terutama, atas penggunaan kekuatan oleh aparat bersenjata.
Ketika aparat keamanan memiliki kuasa hukum yang membengkak dan akuntabilitas yang lemah, kontrol sipil itu dengan sendirinya akan tergerus.
Logika dan pendekatan keamanan akan semakin mewarnai kebijakan publik, bahkan untuk isu-isu sosial, ekonomi, atau politik murni.
Inilah jalan menuju ‘securitocracy’: sebuah tata kelola negara yang didominasi oleh paradigma, institusi, dan personel keamanan, di mana demokrasi dan hak asasi manusia terpaksa mengalah pada dalih ‘stabilitas’ dan ‘ketertiban’.
Saatnya Rakyat Mengambil Sikap!
Kita tidak bisa lagi bersikap pasif atau sekadar berharap pada elite politik yang mungkin punya agenda tersendiri. Pembahasan RUU Polri dan pengawalan terhadap implementasi UU TNI adalah pertarungan krusial bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Setiap pasal dalam RUU Polri yang mengancam hak sipil dan gagal memperkuat akuntabilitas harus ditolak mentah-mentah. Tuntutan untuk membuka draf RUU secara utuh, melibatkan partisipasi publik yang substantif, dan melakukan kajian mendalam yang independen adalah harga mati.
Pada saat yang sama, kewaspadaan terhadap potensi perluasan peran TNI di luar domain pertahanan melalui OMSP harus terus dijaga.
Setiap upaya pengerahan TNI untuk tugas domestik harus dikritisi secara tajam dan dipastikan hanya dilakukan dalam kondisi darurat sesungguhnya, dengan mandat yang jelas, terbatas, dan di bawah kontrol sipil yang ketat. Desakan untuk mereformasi peradilan militer juga harus terus disuarakan.
Ini adalah panggilan bagi seluruh elemen pro-demokrasi: mahasiswa, buruh, petani, akademisi, aktivis HAM, jurnalis, dan seluruh warga negara yang peduli.
Kita harus membangun aliansi strategis untuk mengawal isu ini, melakukan edukasi publik, advokasi kebijakan, dan jika perlu, mobilisasi massa secara damai. Membiarkan RUU Polri lolos dengan pasal-pasal monsternya dan membiarkan ‘pintu belakang’ OMSP terbuka lebar adalah bunuh diri demokrasi.
Ini bukan lagi soal Polri atau TNI semata, ini soal Indonesia macam apa yang ingin kita wariskan kepada generasi mendatang: sebuah negara hukum demokratis yang menghargai kebebasan, atau sebuah negara keamanan yang membungkam rakyatnya?
Pilihan ada di tangan kita, dan waktu untuk bertindak adalah sekarang, sebelum semuanya terlambat. Jangan biarkan alarm merah ini hanya menjadi suara bising yang kita abaikan. (Red)
*) Adjie Shaofani Elsayyid, mahasiswa S1 Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Mataram