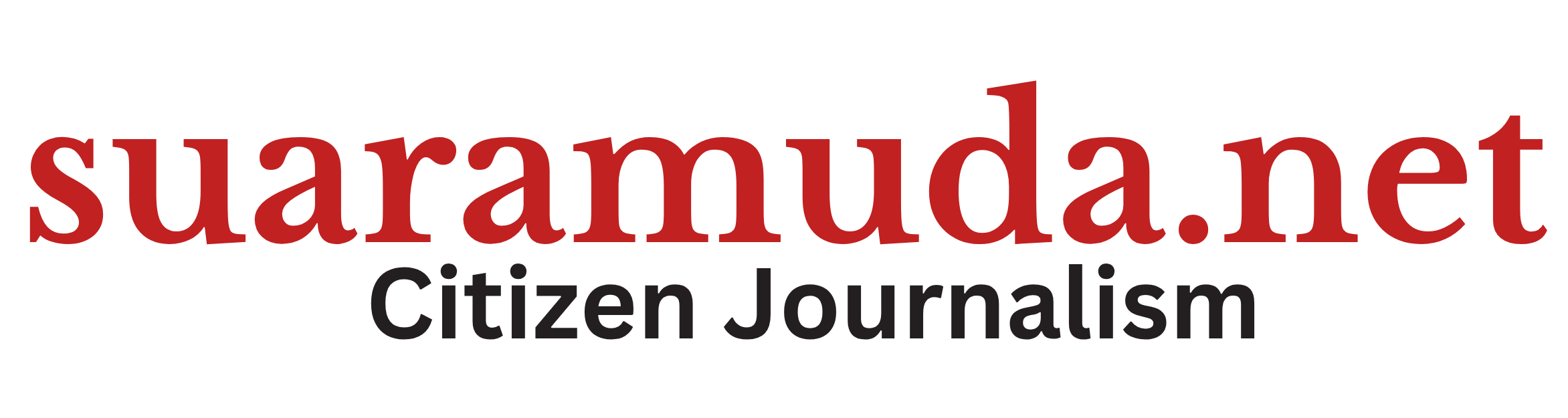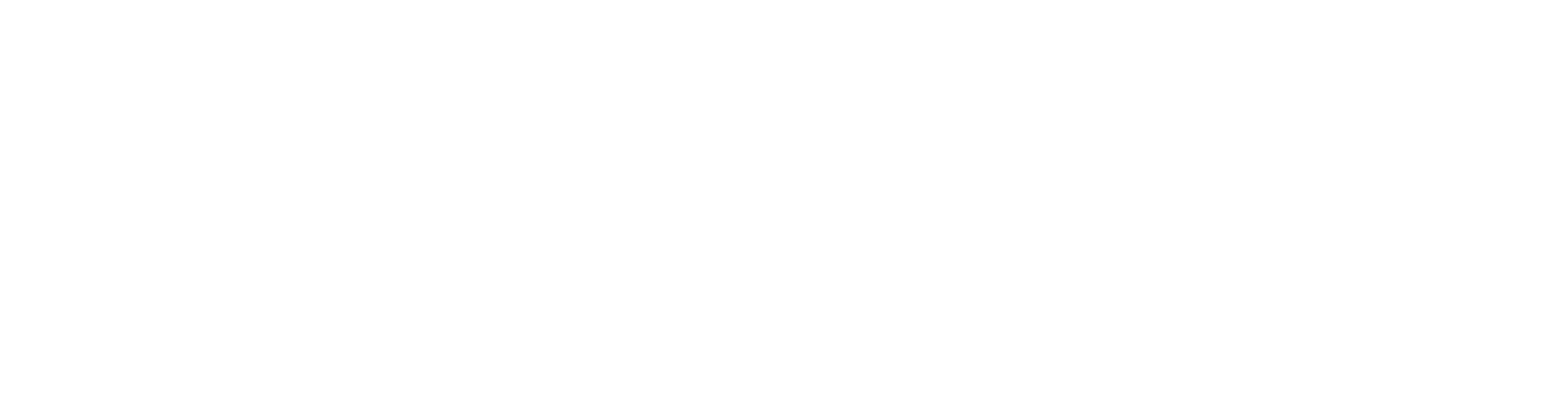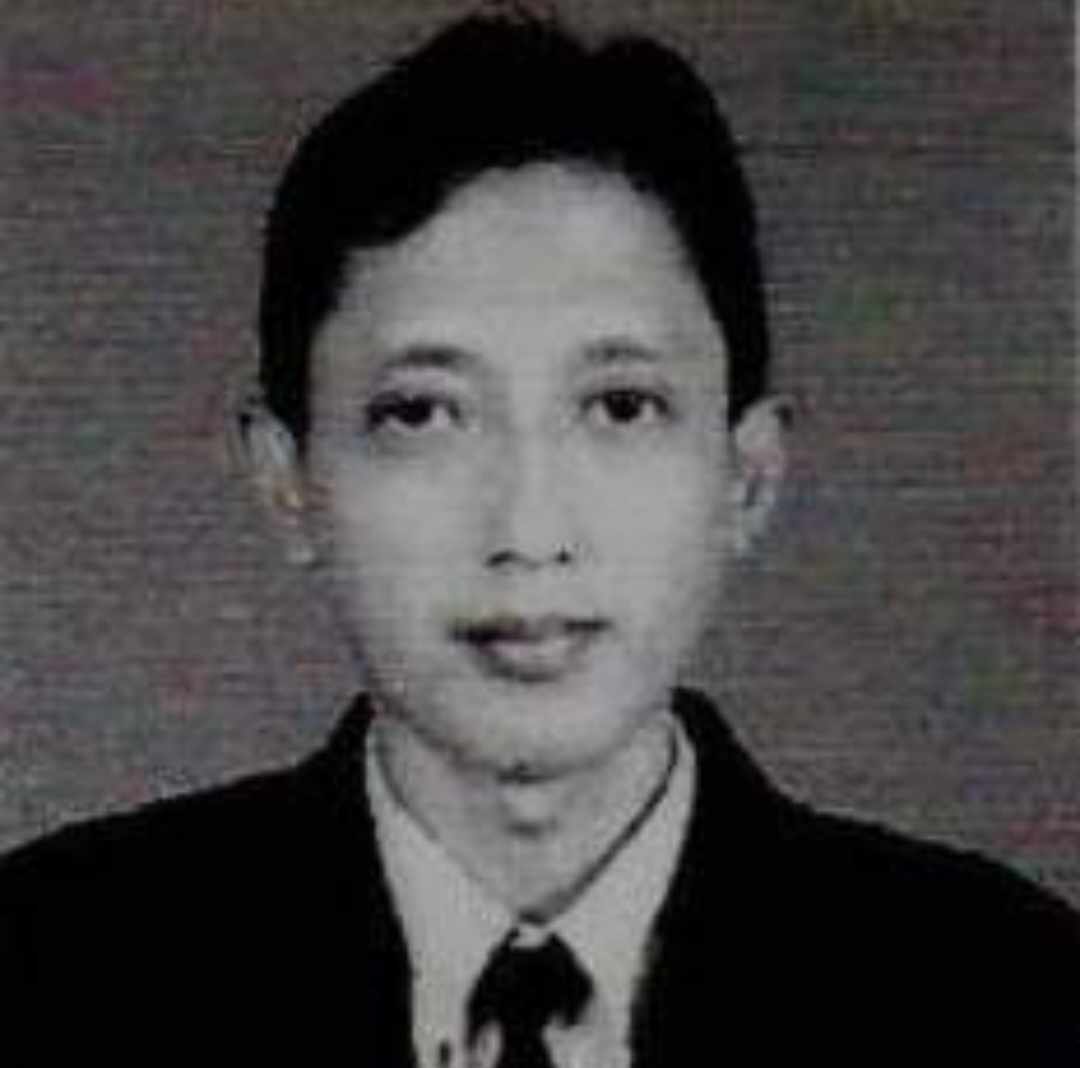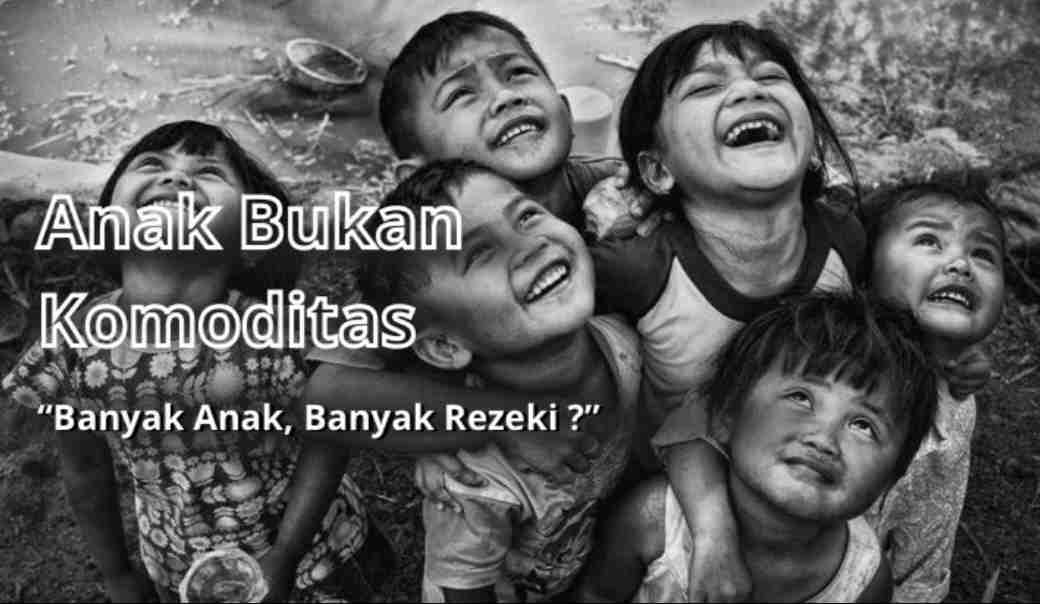
Implikasi Pengembangan Food Estate terhadap Stabilitas dan Keberlanjutan Sistem Ketahanan Pangan Nasional
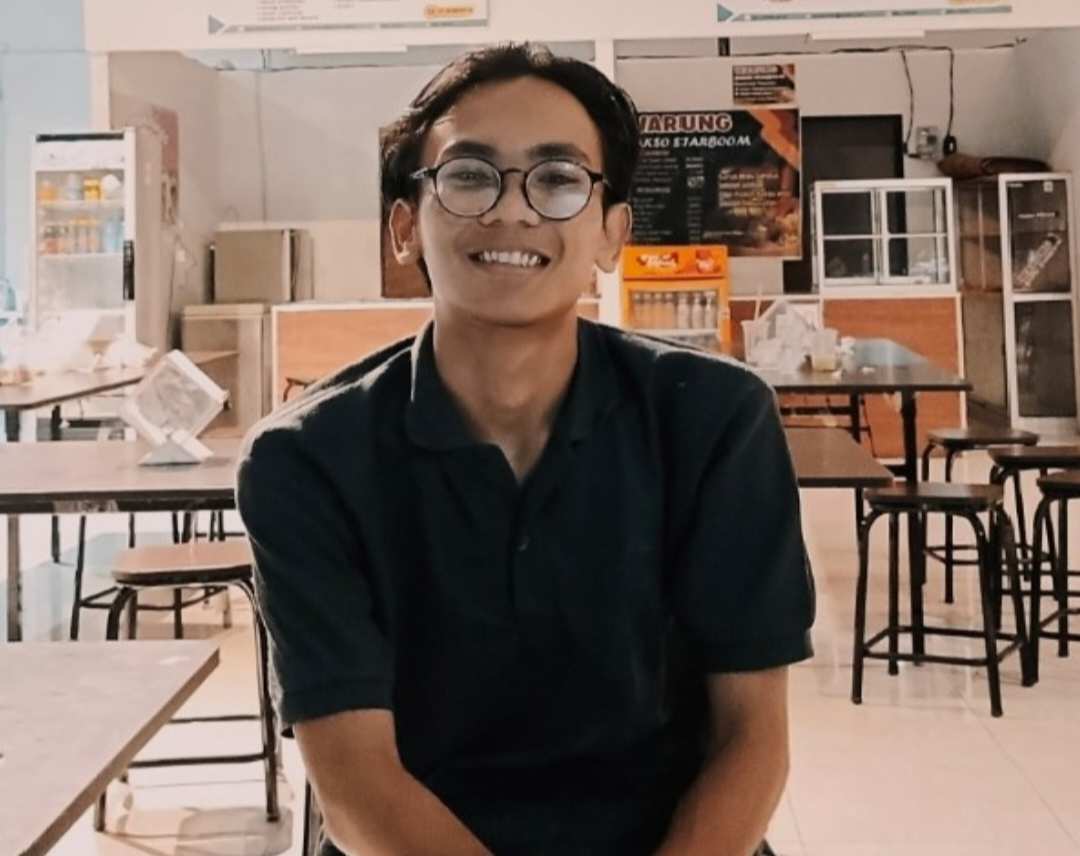
Oleh : Adjie Shaofani Elsayyid *)
SUARAMUDA, SEMARANG — Pengembangan food estate merupakan salah satu kebijakan utama pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah ancaman krisis global.
Dengan konsep kawasan terpadu yang mengintegrasikan kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan dalam skala besar, program ini diharapkan dapat menghadapi tantangan ketahanan pangan nasional.
Namun, di balik ambisi besar tersebut, terdapat berbagai implikasi yang perlu dicermati secara kritis, baik dari sisi stabilitas sistem pangan maupun keberlanjutan lingkungan dan sosial.
Pada tahun 2025, program food estate terus menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan nasional.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, proyek ini mendapatkan perhatian besar dengan alokasi anggaran hingga Rp124,4 triliun untuk mendukung berbagai inisiatif terkait pertanian, perkebunan, dan peternakan terintegrasi.
Namun, meskipun ambisi besar ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor dan menciptakan lumbung pangan nasional, berbagai tantangan serius tetap menghantui pelaksanaannya.
Solusi atau Ilusi?
Program food estate bertujuan untuk menciptakan kawasan pertanian terpadu yang dapat meningkatkan produksi pangan secara signifikan.
Kawasan seperti Merauke di Papua Selatan menjadi salah satu fokus utama, dengan proyek besar seperti pengembangan perkebunan tebu seluas 500.000 hektare, pencetakan sawah baru seluas satu juta hektare, dan optimalisasi lahan dari 40.000 hektare menjadi 100.000 hektare.
Selain itu, pemerintah juga berencana mengintegrasikan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan lahan.
Food estate juga dirancang untuk meningkatkan produksi pangan nasional dengan memanfaatkan lahan-lahan potensial yang selama ini belum optimal.
Sebagai contoh, di Kalimantan Tengah, food estate difokuskan pada tanaman padi, jagung, dan singkong dengan hasil panen mencapai 4,5 ton per hektar—lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 3,8 ton per hektar.
Namun, apakah peningkatan produksi ini benar-benar menjamin stabilitas ketahanan pangan?
Faktanya, peningkatan produksi saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan manajemen distribusi yang baik. Masalah klasik seperti infrastruktur yang buruk dan ketergantungan pada rantai pasok yang panjang masih menjadi hambatan utama.
Ironisnya, meskipun produksi meningkat, harga pangan di tingkat konsumen sering kali tetap tinggi akibat biaya distribusi yang tidak efisien.
Jika pemerintah hanya fokus pada kuantitas tanpa memperhatikan aspek distribusi dan aksesibilitas, maka program ini berpotensi menjadi proyek mahal tanpa dampak nyata bagi masyarakat luas.
Proyek food estate gagal mencapai target produksi yang dijanjikan karena kurangnya kesiapan infrastruktur dan manajemen yang tidak efektif.
Sebagai contoh, konversi lahan gambut untuk pertanian telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang serius, mengancam keanekaragaman hayati dan merugikan masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem tersebut.
Lebih jauh lagi, pendekatan yang digunakan sering kali mengabaikan kebutuhan lokal dan hanya berorientasi pada skala besar.
Hal ini menciptakan risiko bahwa proyek food estate justru menjadi ancaman bagi kemandirian pangan masyarakat lokal, karena mereka kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang sebelumnya menjadi basis kehidupan mereka.
Retorika Hijau atau Realitas Kelam?
Permen LHK No. 24/2020 yang memperbolehkan penggunaan kawasan hutan, termasuk hutan lindung, untuk pembangunan food estate menjadi salah satu kebijakan kontroversial yang berpotensi memperburuk dampak lingkungan dan social.
Kebijakan ini bertentangan dengan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang secara tegas membatasi pemanfaatan hutan lindung untuk kegiatan yang tidak merusak fungsi ekologisnya.
Penggunaan kawasan hutan untuk food estate dapat mempercepat deforestasi, mengancam keanekaragaman hayati, dan merugikan masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem tersebut.
Selain itu, kurangnya penjelasan mengenai proses penetapan kawasan hutan yang dianggap “tidak sepenuhnya berfungsi lindung” menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan menjadi alat eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.
Salah satu kritik tajam terhadap food estate adalah dampaknya terhadap lingkungan. Pembukaan lahan skala besar sering kali mengorbankan ekosistem alami seperti hutan gambut dan lahan adat.
Di Kalimantan Tengah, misalnya, pengembangan food estate telah memicu deforestasi yang signifikan, mengancam keanekaragaman hayati dan mempercepat perubahan iklim.
Padahal, kawasan gambut memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyerap karbon. Konversi lahan gambut untuk proyek food estate telah menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan.
Lahan gambut adalah penyerap karbon alami yang penting bagi mitigasi perubahan iklim. Namun, pembukaan lahan gambut untuk pertanian menyebabkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer, memperburuk krisis iklim global.
Selain itu, penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara masif dalam proyek-proyek ini merusak kualitas tanah serta mencemari sumber air setempat. Ironisnya, pemerintah sering kali mengabaikan dampak lingkungan ini demi mengejar target produksi jangka pendek.
Jika pola ini terus berlanjut, maka program food estate tidak hanya gagal mencapai ketahanan pangan tetapi juga meninggalkan warisan kerusakan ekologi yang sulit diperbaiki.
Pemberdayaan atau Peminggiran?
Food estate sering dipromosikan sebagai program yang akan memberdayakan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu seindah narasi pemerintah. Banyak masyarakat adat yang kehilangan akses terhadap lahan tradisional mereka akibat alih fungsi lahan untuk food estate.
Meskipun pemerintah menjanjikan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan, kenyataannya banyak masyarakat adat yang kehilangan akses terhadap lahan tradisional mereka akibat alih fungsi lahan untuk proyek ini.
Sebagai contoh, di Kabupaten Merauke, sekitar satu juta hektare hutan telah dialihfungsikan menjadi lahan pertanian tanpa persetujuan dari masyarakat adat yang menganggap hutan sebagai bagian integral dari identitas dan kehidupan mereka.
Hal ini menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan, di mana masyarakat adat merasa dirugikan dan terpinggirkan dari keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.
Lebih jauh lagi, pola kerja yang diterapkan dalam food estate cenderung bersifat eksploitatif. Banyak tenaga kerja lokal hanya mendapatkan pekerjaan musiman dengan upah rendah, sementara keuntungan besar diraup oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengelola proyek tersebut.
Proyek food estate di Kalimantan Tengah hanya mencapai 23% dari target produksi yang diharapkan, menunjukkan bahwa tanpa perencanaan dan teknologi yang tepat, proyek ini berisiko gagal.
Selain itu, perubahan pola makan akibat dominasi komoditas tertentu dalam food estate dapat menyebabkan masalah kesehatan dan gizi bagi masyarakat lokal.
Jika pemerintah tidak segera mengatasi ketimpangan ini dan melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek, maka food estate akan berpotensi menjadi alat baru untuk memperdalam ketidakadilan sosial di pedesaan, bukan solusi bagi ketahanan pangan nasional.
Harapan atau Fatamorgana?
Salah satu tujuan utama dari program food estate adalah untuk menstabilkan harga pangan domestik dengan meningkatkan pasokan, namun pencapaian ini tidak semudah yang dibayangkan.
Pasar pangan domestik sangat dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk fluktuasi harga komoditas internasional dan dampak perubahan iklim. Tanpa adanya kebijakan perlindungan harga yang efektif, petani lokal tetap rentan terhadap kerugian akibat harga jual yang rendah.
Misalnya, dalam beberapa kasus, peningkatan produksi dalam skala besar dapat menciptakan overproduksi untuk komoditas tertentu seperti padi atau jagung.
Jika pasar tidak mampu menyerap hasil panen secara optimal, harga akan anjlok di tingkat petani, merugikan mereka dan mengancam keberlanjutan program food estate itu sendiri.
Ketidakpastian pasar akibat kebijakan yang tidak konsisten dan kurangnya dukungan infrastruktur juga berkontribusi pada volatilitas harga pangan.
Misalnya, jika pemerintah tidak menerapkan kebijakan harga minimum atau jaminan pasar bagi petani, mereka akan terus menghadapi risiko kerugian ketika terjadi surplus produksi.
Hal ini bukan hanya merugikan petani tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi konsumen yang bergantung pada stabilitas harga pangan. Implementasi penggunaan lahan efektif juga menjadi persoalan.
Contohnya Food estate di Kalimantan Tengah mengalami masalah serius ketika penanaman jagung dipaksakan di lahan yang sebelumnya ditujukan untuk singkong.
Kementerian Pertanian mengklaim bahwa panen jagung di lokasi tersebut telah berhasil, tetapi realitas di lapangan sering kali bertolak belakang dengan data yang disajikan.
Jika proyek-proyek seperti ini terus berlanjut tanpa evaluasi dan perbaikan yang tepat, maka tujuan untuk menstabilkan harga pangan akan semakin sulit dicapai.
Pemerintah seharusnya merumuskan kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam pengembangan food estate. Ini termasuk penguatan sistem distribusi pangan, peningkatan akses pasar bagi petani kecil, serta penerapan teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi lokal.
Dengan demikian, program food estate dapat benar-benar berfungsi sebagai solusi bagi ketahanan pangan nasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal tanpa mengorbankan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
Pengembangan food estate sering kali terlihat lebih sebagai proyek ambisius daripada solusi nyata bagi ketahanan pangan nasional. Pemerintah tampaknya terlalu sibuk dengan pencitraan politik tanpa benar-benar memahami kompleksitas masalah pangan di Indonesia.
Alih-alih fokus pada solusi jangka panjang seperti reformasi agraria dan penguatan koperasi petani, pemerintah malah memilih jalan pintas melalui proyek-proyek besar yang sarat kontroversi. Lebih ironis lagi adalah kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program ini.
Banyak keputusan strategis terkait lokasi dan pengelolaan food estate dibuat tanpa melibatkan masyarakat lokal secara memadai. Jika pola ini terus berlanjut, maka food estate hanya akan menjadi simbol kegagalan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Jalan Panjang Menuju Ketahanan Pangan
Pangan adalah hidup dan mati suatu bangsa, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya tahun 1952 di Fakultas Pertanian Universitas Indonesia.
Pernyataan ini menegaskan bahwa ketersediaan pangan bukan hanya soal kebutuhan dasar, tetapi juga fondasi keberlangsungan sebuah negara.
Pengembangan food estate memiliki potensi besar untuk memperkuat stabilitas dan keberlanjutan sistem ketahanan pangan nasional.
Namun, potensi ini hanya akan menjadi kenyataan jika pemerintah mampu mengatasi berbagai tantangan yang ada dengan pendekatan holistik dan inklusif.
Program ini membutuhkan perencanaan matang yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang.
Jika pemerintah terus mengabaikan kritik konstruktif dan hanya fokus pada pencapaian jangka pendek, maka food estate berisiko menjadi proyek mercusuar yang megah namun kosong makna bagi rakyat Indonesia.
Ketahanan pangan sejati hanya dapat dicapai melalui kebijakan yang berpihak pada petani kecil, melibatkan masyarakat lokal, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia serta kelestarian alam. Tanpa itu, ambisi besar ini tidak lebih dari sekadar ilusi yang mengorbankan masa depan bangsa.
*) Adjie Shaofani Elsayyid adalah Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Mataram.