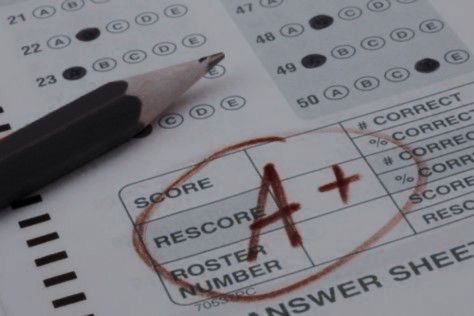Banjir Sumatera: Luka Lingkungan yang Tak Lagi Bisa Disamarkan


Oleh: Yohanes Soares*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan wilayah sekitarnya bukan sekadar peristiwa cuaca ekstrem. Ia adalah narasi panjang tentang bagaimana manusia perlahan mengikis fondasi ekologis yang menopang hidupnya sendiri.
Curah hujan yang setara volume bulanan dalam satu hari hanyalah pemicu terakhir dari akumulasi kerusakan yang dibiarkan menumpuk selama bertahun-tahun.
Ketika hutan kehilangan penyangganya, ketika sungai kehilangan ruangnya, ketika tanah kehilangan kemampuan menyerap air pun kehilangan jalurnya dan memilih jalan paling mudah merusak.
Di antara arus deras itu, gelondongan kayu besar yang hanyut menjadi bukti yang tidak perlu ditafsirkan. Ia bukan sekadar puing-puing yang terbawa banjir, ia adalah fragmen tubuh hutan yang runtuh.
Di lereng-lereng yang dulu hijau dan teduh, kini terbuka bekas-bekas pembukaan lahan, kebun monokultur, dan jalan tanah yang memotong kontur tanpa pengaman.
Hujan deras yang semestinya diserap oleh akar dan lantai hutan justru berbalik menjadi hantaman besar yang menggerus desa-desa di bawahnya. Ketika hulu rusak, hilir menanggung bala.
Daya rusak banjir tidak hanya lahir dari air, tetapi dari keputusan-keputusan manusia yang berdampak jangka panjang. Alih fungsi lahan dilakukan seolah tanah adalah kanvas kosong yang bisa diubah sesuka hati, padahal setiap hektare hutan yang hilang berarti hilangnya satu bagian penting dari sistem hidrologi.
Tanah yang dulu berpori dan menyimpan air kini menjadi permukaan keras yang mempercepat aliran. Eksploitasi berjalan, keuntungan mengalir, tetapi fungsi ekologis yang hilang tak pernah benar-benar dihitung sebagai kerugian.
Di lapisan lain, ada masalah tata ruang yang selama ini dianggap administratif, padahal sangat menentukan keselamatan publik. Kita mendirikan rumah, pasar, dan fasilitas umum di bantaran sungai dan dataran banjir, seolah sungai tidak pernah menuntut kembali ruang alaminya.
Izin-izin terbit tanpa analisis risiko yang memadai, sering kali bertentangan antara satu institusi dan institusi lain, seakan ruang hidup manusia adalah teka-teki yang bisa disusun ulang setiap saat. Ketika bencana datang, semua tampak seperti kecelakaan alam. Padahal jejaknya sangat manusiawi.
Kegagalan pengawasan dan penegakan hukum memperpanjang luka itu. Penebangan liar, izin tambang yang longgar, hingga praktik korporasi yang tak diimbangi kewajiban restorasi membuat ekosistem semakin rapuh.
Ketika sanksi tidak ditegakkan, pasar akan mendorong eksploitasi tanpa henti. Yang membayar bukan pelanggarnya, melainkan warga, mereka yang rumahnya hanyut, sawahnya rusak, dan kehidupannya terhenti sementara mereka tidak pernah mendapat manfaat langsung dari proyek-proyek besar yang merusak ruang hidup mereka.
Di balik semua kerusakan itu, ada wajah-wajah yang menanggung beban paling berat yakni masyarakat adat yang kehilangan lahan ulayat, petani skala kecil yang gagal panen, anak-anak yang harus mengungsi, perempuan yang kehilangan sumber nafkah, buruh harian yang terjebak tanpa penghasilan.
Banjir tidak hanya membawa air, tetapi juga ketidakadilan. Segelintir memperoleh keuntungan dari eksploitasi, tetapi banyak yang membayar mahal kerugiannya.
Jika kita berbicara ekonomi, negara sering sibuk menghitung kerusakan infrastruktur atau gangguan logistik. Padahal biaya tersembunyi jauh lebih besar, hilangnya kesuburan tanah, rusaknya keanekaragaman hayati, meningkatnya penyakit akibat air tercemar, hingga biaya psikologis masyarakat yang traumanya tidak pernah masuk dalam laporan resmi.
Pemulihan teknis mungkin selesai dalam hitungan bulan, tetapi pemulihan sosial dan ekologis bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Ironisnya, di tengah bencana sebesar ini, retorika bencana alam masih sering dipakai. Padahal menyederhanakan peristiwa ini sebagai bencana alam berarti mengaburkan tanggung jawab manusia dan negara. Ini bukan sekadar hujan ekstrem, ini adalah konsekuensi logis dari kebijakan dan kelalaian.
Penundaan penetapan status bencana nasional atau penekanan narasi alam semata hanya menambah panjang jarak antara pengambil kebijakan dan realitas korban.
Di titik inilah kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar yakni bagaimana kita memandang alam? Apakah ia sekadar bahan baku untuk pertumbuhan ekonomi, ataukah ia sistem hidup yang harus dihormati dan dijaga keseimbangannya?
Selama pembangunan masih mengukur kemajuan dari angka ekonomi saja, tanpa memasukkan modal ekologis, maka bencana demi bencana hanya menunggu giliran untuk terjadi.
Karena itu, reformasi ekologis bukan lagi pilihan, tetapi keharusan moral. Moratorium izin eksploitasi di kawasan hulu harus dilakukan hingga ada audit lingkungan yang benar-benar transparan. Rehabilitasi DAS harus menjadi prioritas, bukan proyek simbolik.
Data izin dan penegakan hukum harus dibuka, publik berhak tahu siapa yang merusak ruang hidup mereka. Tata ruang harus dibangun ulang berdasarkan risiko, bukan kepentingan investor. Masyarakat lokal yang paling tahu kondisi ekologis daerahnya harus diberi peran nyata dalam pengelolaan hutan dan sungai.
Infrastruktur hijau bukan jargon, tetapi arah pembangunan baru. Dan yang tak kalah penting, pemulihan perlu dipikirkan sebagai program jangka panjang, bukan sekadar bantuan darurat.
Pada akhirnya, banjir Sumatera adalah cermin. Di dalamnya, kita melihat gambaran paling jujur tentang pilihan pembangunan yang telah kita ambil selama puluhan tahun.
Ini bukan siklus alam semata. Ini adalah potret kegagalan kolektif. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah banjir seperti ini akan terulang, tetapi apakah kita cukup berani mengubah arah sebelum tragedi berikutnya datang.
Jika ada pelajaran paling penting dari banjir ini, mungkin hanya satu, kemajuan sejati bukan diukur dari seberapa cepat kita membangun tetapi dari seberapa tulus kita menjaga kehidupan yang bergantung pada alam. (Red)
*) Penulis: Yohanes Soares, aktivis sosial dan mahasiswa S3 Universitas Dr. Soetomo Surabaya