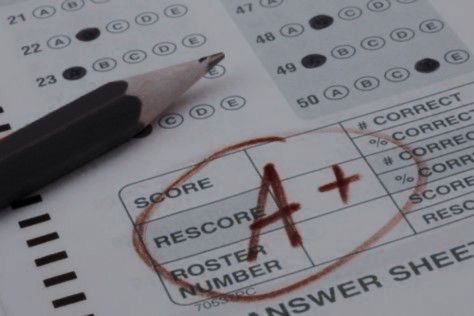Kedaulatan yang Tergadai oleh Ketamakan Penguasa


Oleh: Sri Radjasa*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG— Kedaulatan sebuah negara tidak pernah runtuh sekaligus. Ia retak sedikit demi sedikit, dimulai dari pelapukan nilai yang paling dekat dengan pusat kekuasaan.
Di negeri ini, simbol kenegaraan, jargon persatuan, bahkan seruan mengenai NKRI harga mati, kerap hanya berfungsi sebagai ornamen yang dipamerkan dalam upacara seremonial.
Sementara makna substantifnya yaitu pengabdian pada kepentingan nasional dan perlindungan terhadap rakyat ditinggalkan demi kepentingan sektoral dan selera politik yang makin elitis.
Reformasi yang pernah diusung sebagai momentum peradaban kedua setelah proklamasi, berubah menjadi ruang reproduksi oligarki, tempat kekuasaan tunduk pada modal dan negara perlahan kehilangan orientasi moralnya.
Demokrasi yang semestinya menjadi arena pembentukan kehendak rakyat, justru direduksi menjadi strategi pencitraan dan legitimasi kebijakan yang kerap merugikan kedaulatan ekonomi maupun politik.
Tidak ada contoh yang lebih jelas dari cacat kedaulatan itu selain kisah yang kini bergulir di Morowali, Sulawesi Tengah.
Kawasan ini, yang menyimpan nikel sebagai salah satu sumber daya strategis Indonesia, berubah menjadi panggung pertarungan antara negara yang seharusnya berdaulat dan kepentingan modal asing yang kian dominan.
Morowali Industrial Park (IMIP), sebagai kawasan industri raksasa hasil investasi patungan dengan Tiongkok, memang sering dipromosikan sebagai simbol keberhasilan hilirisasi.
Namun ketika pelabuhan dan bandara yang beroperasi di dalamnya tidak sepenuhnya berada dalam radar pengawasan negara, hilirisasi itu justru tampak sebagai jalan pintas untuk merelakan pintu kedaulatan dibuka sedikit lebih lebar dari seharusnya.
Dalam teori negara modern, bandara dan pelabuhan adalah gerbang kedaulatan. Di sana negara melakukan fungsi-fungsi inti yang tak dapat didelegasikan untuk mengawasi perpindahan orang, mengontrol arus barang strategis, dan memastikan hukum berlaku sama untuk semua entitas, termasuk korporasi raksasa.
Ketika fungsi tersebut absen, atau diambil alih oleh entitas swasta bahkan oleh konsorsium asing, maka kedaulatan tidak lagi bersifat penuh. Ia berubah menjadi kedaulatan yang dipinjamkan, dan pada titik tertentu, digadaikan.
Fakta bahwa Bandara IMIP telah melayani lebih dari 51.000 penumpang per tahun tanpa kehadiran Imigrasi maupun Bea Cukai menjadi sinyal yang terlalu keras untuk diabaikan. Sebuah negara yang absen di pintu gerbangnya sendiri sejatinya telah melepaskan sebagian instrumen penguasaan teritorialnya.
Dalam kondisi seperti ini, potensi pelanggaran bukan lagi isu spekulatif, melainkan konsekuensi struktural. Arus tenaga kerja asing tanpa verifikasi ketat, mobilitas material bernilai tinggi tanpa pencatatan negara, dan akses logistik yang tidak berada dalam kontrol sepenuhnya membuka celah yang nyaris pasti dimanfaatkan.
Celah inilah yang menguat oleh data-data perdagangan yang terekam di International Trade Center (ITC) dan General Customs Administration of China.
Selain Indonesia yang mencatat nihil ekspor bijih nikel sejak pelarangan berlaku pada Januari 2020, data otoritas Tiongkok justru menunjukkan sebaliknya bahwa 3,4 juta ton bijih nikel masuk ke negara tersebut pada 2020, 800 ribu ton pada 2021, 1,1 juta ton pada 2022, dan sekitar 300 ribu ton pada 2023.
Dalam total empat tahun, 5,6 juta ton bijih nikel bernilai sekitar Rp5 triliun tercatat masuk ke China. Ketidaksinkronan data ini bukan sekadar anomali statistik, ia adalah indikasi yang kuat tentang kebocoran kedaulatan, entah melalui jalur pengawasan yang lemah atau praktik yang lebih sistematis dari itu.
Di tengah kebingungan antara data pemerintah dan catatan perdagangan internasional, hilirisasi nikel yang digadang-gadang sebagai pilar kemandirian ekonomi justru terlihat rapuh secara filosofis.
Hilirisasi seharusnya menempatkan negara sebagai inisiator, regulator, dan pengawas utama. Namun ketika negara justru menjadi pengekor, pembangunan industrialisasi kehilangan roh kebangsaannya.
Banyak teknologi pengolahan tetap didominasi tenaga asing, struktur bisnis bertumpu pada perusahaan yang memegang kendali investasi, sementara pemerintah daerah dan pusat sering kali hanya menyaksikan perputaran nilai tambah tanpa menjadi penerima manfaat utama.
Model seperti ini tidak memperkuat kedaulatan, melainkan memindahkan pusat kendali ekonomi ke pihak yang tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap bangsa ini.
Persoalan Morowali, dengan demikian, bukan sekadar soal perizinan atau absennya pengawasan teknis. Ia menyentuh inti persoalan kebangsaan, apakah negara masih menguasai alat-alat strategis untuk menjamin masa depan kolektif rakyatnya?
Ataukah sebagian kewenangan itu telah dialihkan melalui kompromi kekuasaan dan ketamakan birokrasi yang melihat investasi raksasa sebagai jalan pintas untuk mengumpulkan rente?
Dalam kacamata filsafat politik, negara yang tidak hadir di ruang-ruang strategisnya sendiri sedang menghancurkan legitimasi moralnya.
Kedaulatan bukanlah konsep abstrak; ia hadir dalam tindakan konkret baik itu di pelabuhan, di bandara, di kontrol ekspor, di aturan tenaga kerja, dan dalam keputusan untuk menolak godaan rente jangka pendek demi ketahanan bangsa jangka panjang.
Indonesia kini berada pada persimpangan yang menentukan. Hilirisasi tidak dapat dihentikan, dan memang tidak perlu dihentikan. Namun hilirisasi yang mengabaikan kehadiran negara adalah hilirisasi yang kehilangan arah. Dengan kontrol negara yang kuat, hilirisasi dapat menjadi jalan menuju kemandirian industri.
Tanpa kontrol itu, hilirisasi berubah menjadi ekstraksi gaya baru yang dilakukan atas nama pembangunan. Pilihan ada pada pemimpin bangsa, apakah akan menempatkan diri sebagai penjaga kedaulatan, atau justru sebagai perantara yang membantu melicinkan jalan kekuatan asing dalam mengakses kekayaan alam nasional.
Pada akhirnya, kedaulatan adalah soal keberanian moral untuk mengatakan bahwa kepentingan rakyat tidak dapat dinegosiasikan. Ketika penguasa justru tunduk pada godaan kekuasaan dan keuntungan sesaat, maka kedaulatan itu perlahan tergadai.
Sejarah bangsa menunjukkan bahwa godaan seperti itu selalu datang dari luar, tetapi keruntuhannya selalu dimulai dari dalam. Tanpa pembenahan, Morowali hanyalah salah satu dari banyak pintu yang perlahan dibiarkan terbuka, menunggu waktu hingga seluruh rumah besar bernama Indonesia tak lagi benar-benar dikendalikan oleh bangsa itu sendiri. (Red)
*) Penulis: Sri Radjasa, Pemerhati Intelijen