

Saat Nilai Menggeser Nalar
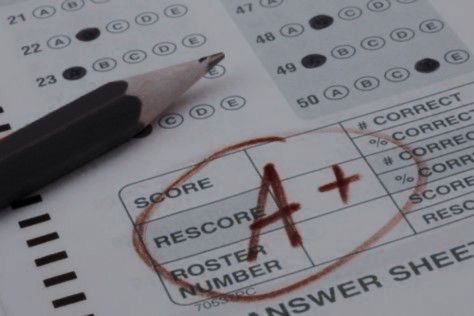

Oleh: Rahmalia Huriyah Roihanah*)
SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Mahasiswa adalah cermin dari semangat intelektual. Generasi yang berpikir, meneliti, dan menimbang realitas dengan nalar. Kampus dianggap sebagai taman kebebasan, tempat pikiran tumbuh dan perdebatan subur.
Namun kini, gambaran itu perlahan memudar. Di banyak perguruan tinggi, suasana intelektual berubah menjadi administratif. Mahasiswa datang, mencatat, mengumpulkan tugas, menunggu nilai, lalu pulang.
Fenomena ini melahirkan sebuah kenyataan di mana nalar sering kalah oleh nilai. Bukan karena tidak ingin berpikir, tetapi karena sistem mendorong mereka untuk mengejar nilai bukan nalar.
Sering kita melihat di ruang kuliah mana pun. Saat dosen memberikan tugas, kebanyakan mahasiswa tidak mempertanyakan makna atau konsepnya, tapi tentang formatnya “berapa halaman Bu”, “font-nya berapa Bu”, “berapa minimal sumber yang harus ada?”.
Apalagi sekarang zaman semakin canggih, ada AI, membuat mahasiswa semakin memilih jalur cepat. Cukup memasukkan perintah, mendapat jawaban, dan selesai, tanpa benar-benar memahami proses berpikir yang seharusnya terjadi.
Nilai bertransformasi menjadi sebuah tujuan, bukan gambaran dari proses pembelajaran itu sendiri. Mahasiswa berusaha bukan untuk memahami, tetapi untuk memenuhi ekspektasi dosen.
Pada titik ini, pendidikan kehilangan esensinya yang paling mendasar yaitu membebaskan individu dari kebohongan. Pendidikan telah berubah menjadi pelatihan untuk mematuhi aturan. Mahasiswa tidak diajarkan untuk berpikir kritis, tetapi untuk menebak apa yang diinginkan oleh sistem.
Sebenarnya, berpikir kritis tidak hanya sekadar kemampuan dalam konteks akademik, tetapi juga merupakan pendekatan dalam menjalani hidup.
Ini adalah keberanian untuk mempertanyakan hal-hal yang telah dianggap sebagai kebenaran, untuk menolak rutinitas tanpa mempertanyakan, dan untuk menemukan perspektif baru terhadap realitas.
Namun, dalam budaya yang mengutamakan nilai, keberanian untuk berpikir kritis sering dianggap sebagai gangguan. Mahasiswa yang terlalu banyak bertanya dikategorikan sok tahu, sedangkan mereka yang memiliki pandangan berbeda dianggap tidak sopan.
Masalah semakin kompleks ketika sistem pendidikan tinggi terlalu menekankan aspek kuantitatif. Nilai, entah dalam bentuk huruf atau angka menjadi tolak ukur tunggal untuk menentukan kualitas seorang mahasiswa.
Lulusan dengan nilai tinggi dipandang lebih unggul, meski belum tentu lebih bernalar. Sistem ini juga menciptakan ketimpangan psikologis.
Mahasiswa berlomba mendapat nilai sempurna bukan karena cinta ilmu tetapi karena takut gagal.
Mereka takut kehilangan beasiswa, takut mengecewakan orang tua, dan takut dianggap bodoh. Maka, tugas pun dikerjakan dengan strategi bukan refleksi. Yang penting rapi, sesuai format, dan aman dari koreksi dosen.
Dosen pun tidak sepenuhnya lepas dari situasi ini. Banyak dosen yang ingin membangun dialog yang hidup, tetapi terjebak tuntutan administratif, akreditasi, laporan, dan penelitian yang serba formal.
Dalam hal ini, penilaian pun dilakukan secara praktis dan cepat. Mahasiswa dinilai bukan dari sejauh mana ia berkembang, tapi dari sejauh mana ia memenuhi rubrik. Hubungan dosen dan mahasiswa kemudian menjadi impersonal. Hanya pembagi tugas dan pemeriksa.
Dampak budaya nilai ini meluas hingga dunia kerja. Banyak perusahaan mengeluhkan lulusan baru yang rajin tetapi tidak kritis, cerdas secara teoritis namun tidak adaptif dalam situasi kompleks.
Mereka terbiasa menjawab, tetapi tidak terbiasa bertanya, mereka pandai mengikuti instruksi, tapi kesulitan berpikir mandiri. Generasi muda pun tumbuh dalam budaya penilaian, bukan pemaknaan.
Padahal, dunia kerja modern menuntut kemampuan berpikir terbuka, bukan sekadar mengulang. Lebih jauh lagi, situasi ini, menciptakan generasi muda yang mudah kehilangan arah.
Untuk memperbaiki keadaan, diperlukan perubahan orientasi dalam sistem penilaian. Kampus harus bergerak dari yang semata kuantitatif menuju yang kualitatif yang menilai proses berpikir, keberanian berargumentasi, dan kreativitas.
Bentuk evaluasi seperti diskusi terbuka, proyek sosial, dan presentasi kritis dapat menjadi alternatif yang mendorong mahasiswa memahami keterkaitan antara teori dan realitas.
Dosen juga perlu dilatih memberikan umpan balik konstruktif, bukan sekadar memberi angka. Kelas harus menjadi ruang interaksi, tempat ide saling bertemu dan diperdebatkan.
Dosen memiliki peran sebagai fasilitator pemikiran. Sementara itu, mahasiswa harus didorong untuk berani bertanya dan menyampaikan pandangan.
Selain itu, kampus perlu menghidupkan kembali budaya literasi. Perpustakaan harus menjadi pusat kegiatan intelektual. Diskusi buku, kajian pemikiran, atau klub membaca dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kebiasaan reflektif.
Membaca bukan hanya menambah wawasan, tetapi melatih kesabaran intelektual dan memperluas empati.
Ketika nilai menggeser nalar, kampus kehilangan rohnya, dan mahasiswa kehilangan jati dirinya. Tapi semua belum terlambat.
Setiap dosen yang memberi ruang dialog, setiap mahasiswa yang berani bertanya, setiap kelas yang menumbuhkan refleksi, semua itu adalah bentuk perlawanan kecil terhadap sistem yang menindas pikiran.
Pendidikan sejati bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling berani berpikir. Nilai bisa hilang, IPK bisa dilupakan, tapi nalar yang hidup akan tetap menjadi cahaya di tengah gelap zaman. (Red)
*) Rahmalia Huriyah Roihanah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Penulis memiliki hobi membaca dan ketertarikan menulis pada isu pendidikan dan budaya akademik, tinggal di Sukoharjo

















