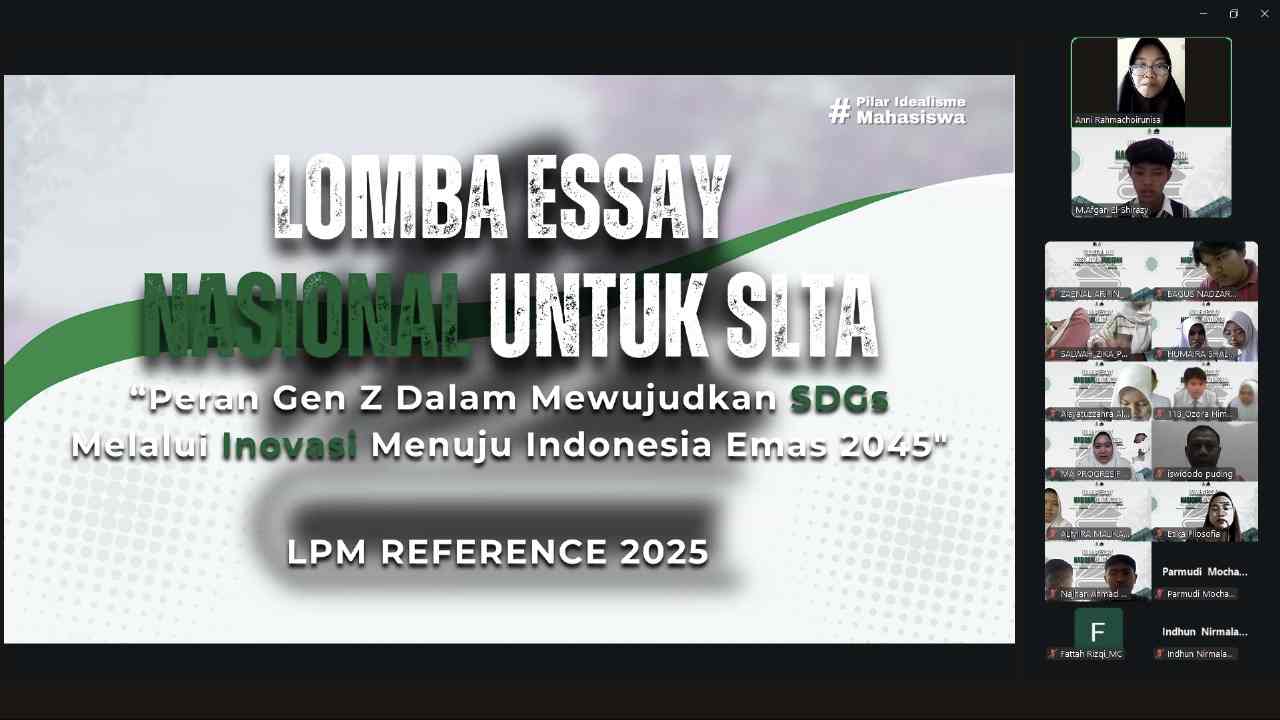Cerpen: Surat Dadakan
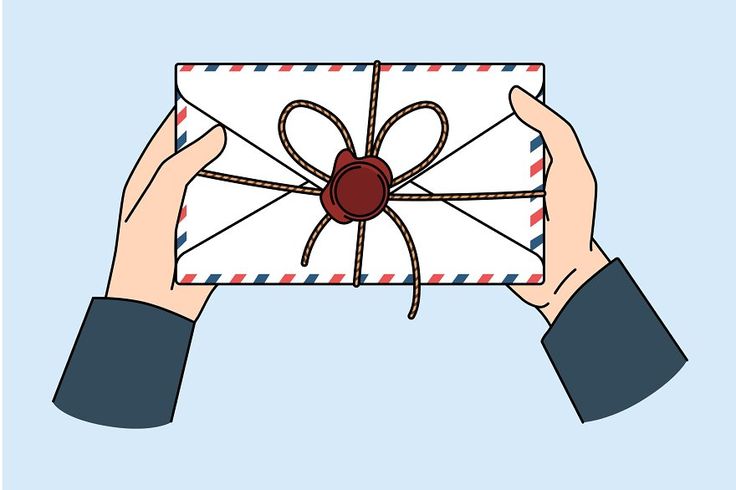

SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Malam itu, suasananya agak sedikit berbeda. Bunyi gesekan gitar para tetangga tak lagi terdengar. Lantunan lagu “nostalgia lama” yang biasanya dikumandangkan seolah hilang ditelan oleh bunyi gemericik air yang menghantam atap rumah tua.
Hujan gerimis menambah kesunyian di sebuah kamar yang sempit. Hening, sepi, dan hanya detak jarum jam yang sedikit menyisakan suara. Bunyinya semakin lambat seiring berlalunya waktu.
Di meja kayu yang sudah usang, sebuah naskah tergeletak berserakan. Di atasnya ada secangkir kopi yang sudah dingin dan sebatang rokok yang tinggal abu.
Sang Tuan, yang tidak pernah dikenal dengan nama; yang hanya dikenal sebagai pria insomnia yang terus berjuang dengan bayang-bayangnya sendiri, duduk di kursi kayu dengan tatapan kosong. Matanya sayup, seolah berharap agar kantuk segera datang menghampirinya.
Ia memandang naskah dan skema yang sudah disusunnya dengan susah payah. Satu per satu huruf, kata, frasa, dan kalimat tercetak rapi, namun seolah ada yang kurang. Setiap kali matanya melihat naskah itu, ia merasa ada sesuatu yang hilang–sebuah esensi yang tak bisa dijelaskan.
Setiap kata yang diuntainya terasa sia-sia, seperti puing-puing yang tak bisa membangun makna utuh. Ia berusaha menemukan kesempurnaan, tetapi yang ditemuinya justru kelelahan. Rasa letih seakan semakin menambah berat di dadanya.
Wajahnya yang lelah seolah mencerminkan gambaran sesorang yang telah lama tersesat dalam perjalanan hidupnya. “Everything is perfect. Semuanya sudah sempurna,” katanya pelan, tetapi tak ada yang mendengar.
Tak ada yang peduli, selain rokok yang sudah mati dan kopi yang telah tak tersentuh lagi.
Teringat olehnya, masa-masa silam, tatkala ia masih muda dan penuh semangat.
Saat dunia terasa lebih bersahabat, ia pernah bermimpi menulis sebuah karya besar. Namun, mimpi itu kini tertutup bayang-bayang hitam yang datang tanpa henti.
Ia mengingat bagaimana dulu ia masih punya harapan, sebelum hidupnya dihantui oleh rasa takut dan kecemasan yang datang tak terduga.
Insomnia itu seperti teman yang tak diundang, selalu hadir tanpa permisi, dan mengikis tiap detik tidur yang seharusnya menjadi haknya. Ia tak lagi bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan.
Namun, entah apa yang merasukinya, setiap kali ia menulis, ia merasa bahwa naskah itu seolah menjadi satu-satunya hal yang memberinya sedikit ketenangan. Tapi, kini, naskah itu terasa kosong, hambar dan tak memberikan apa-apa.
Seolah ia menulis untuk mengisi kekosongan yang tak pernah terisi. Naskah itu, seperti dirinya sendiri, terperangkap dalam ruang yang tak terjangkau oleh waktu dan harapan.
Malam semakin larut, dan akhirnya, ia pun memutuskan untuk beranjak. Tak ada yang tahu ke mana perginya; dan tak ada yang tahu ke mana langkah kaki menuntunya.
Mungkin, ia pergi ke kampung tetangga, menabur bunga di kuburan “Sang Kata” yang telah mendewasakannya, atau mungkin ia pergi ke rumah mertuanya, tempat segala resah bertunduk pasrah.
Atau siapa tahu, ia pergi ke istana negara, berteriak dengan suara paraunya yang kini semakin kecil dan tak berdaya.
Tak ada yang tahu pasti. Tetapi kelihatannya, ia ingin merdeka. Dalam kebuntuan pikirannya, ia mulai membungkus pisau, parang, dan senjata.
Bukan untuk bunuh diri, tetapi untuk membungkam bayang-bayang hitam yang terus mengejeknya.
“Dasar Insomnia! Engkau tak berguna bagi kami,” kata mereka. “Engkau menjadikan kami seolah-olah bayangan yang tak bertuan.”
Malam itu, ia tidak hanya berkutat melawan insomnia, tetapi juga melawan kenangan di masa silam, melawan penyesalan yang datang terlambat, dan melawan dirinya sendiri.
Ketakutan yang selalu mendorongnya untuk berlari, kini membuatnya tersungkur dalam jurang kekosongan yang dalam. “Aku ingin bebas,”katanya.
Tetapi kebebasan seperti apa yang ia harapkan? Apakah kebebasan itu berarti tidur yang nyenyak tanpa gangguan, atau apakah itu kebebasan untuk lepas dari bayang-bayang maut yang terus menghantuinya?
Ia melangkah pergi. Tanpa membawa naskah dan skema yang sudah disusunnya; tanpa peduli akan dunia yang ditinggalkannya. Keesokan harinya, kabar itu datang. Tidak ada lagi suara naskah dan skema yang melengking; tak ada lagi aroma kopi dan rokok yang menyentuh hidung.
Hanya ada keheningan, diikuti suara ejekan dari naskah yang terlupakan, “Dasar Insomnia, untuk apa engkau mengotori kami berdua?”
Lusanya, para sahabat dan kerabatnya datang satu per satu. Ada yang membawa kabar duka, dan ada pula yang membawa kabar suka. Masing-masing mereka punya cerita yang berbeda.
“Ia rebah di tanah sengketa,” kata tetangga A. “Ia mati tertusuk pisau sendiri,” kata si tetangga I. “Kemarin ia sempat bertanya padaku: tidakkah engkau ingin merdeka juga?” kata tetangga yang lain.
Hari-hari berlalu tanpa ada kejelasan. Aku mencari, namun tak menemukan jawaban pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Semua orang datang dengan narasi yang berbeda.
Akhirnya, tiga hari setelah kepergiannya, datang seorang tanpa nama. Bertubuh kekar, berambut gondrong, dan tak kutemukan tanda pengenal pada bajunya. Ia membawa sebuah boks kecil dan surat.
Aku tahu, itu pasti miliknya. Milik pria yang lupa naskah dan skema; milik pria yang selalu dihantui oleh bayangannya sendiri.
Kubuka surat itu dengan hati yang berdebar, seolah mataku tak ingin melihatnya. Tulisannya sederhana, tapi mengandung makna yang mendalam. Ia menulis:
“Tak perlu kau cari lagi aku di luar sana, kawan. Aku sudah merdeka. Merdeka dari segala derita, merdeka dari sindiran Insomnia, dan merdeka dari segala kesusahan. Kini, aku mau pulang. Pulang sebagai petualang yang menang, pulang pada ruang yang penuh raung, pada sunyi yang paling sepi, dan menjadi abadi bersama Sang Sabda yang sudah ada sebelumnya. Sampaikan salamku untuk naskah dan skema yang mungkin masih kecewa di rumah. Beritahu saja pada mereka bahwa Sang Tuan telah aman dalam iman yang mengamini setiap keluh kesahnya di rumah peraduan mertua. Aku sungguh-sungguh merdeka.”
“Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.”
Aku terdiam. Ini adalah surat dadakan, kata pria bertubuh kekar itu. Aku menatap boks kecil yang kini menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Aku menyalakan sebuah lilin di atasnya, seperti yang ia katakan.
“Skema dan naskahmu berjalan sempurna, kawan,” bisikku dalam hati, sebelum menghembuskan asap lilin yang perlahan menghilang bersama angin malam. (Red)
Penulis: Mario Oktavianus Magul, Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta