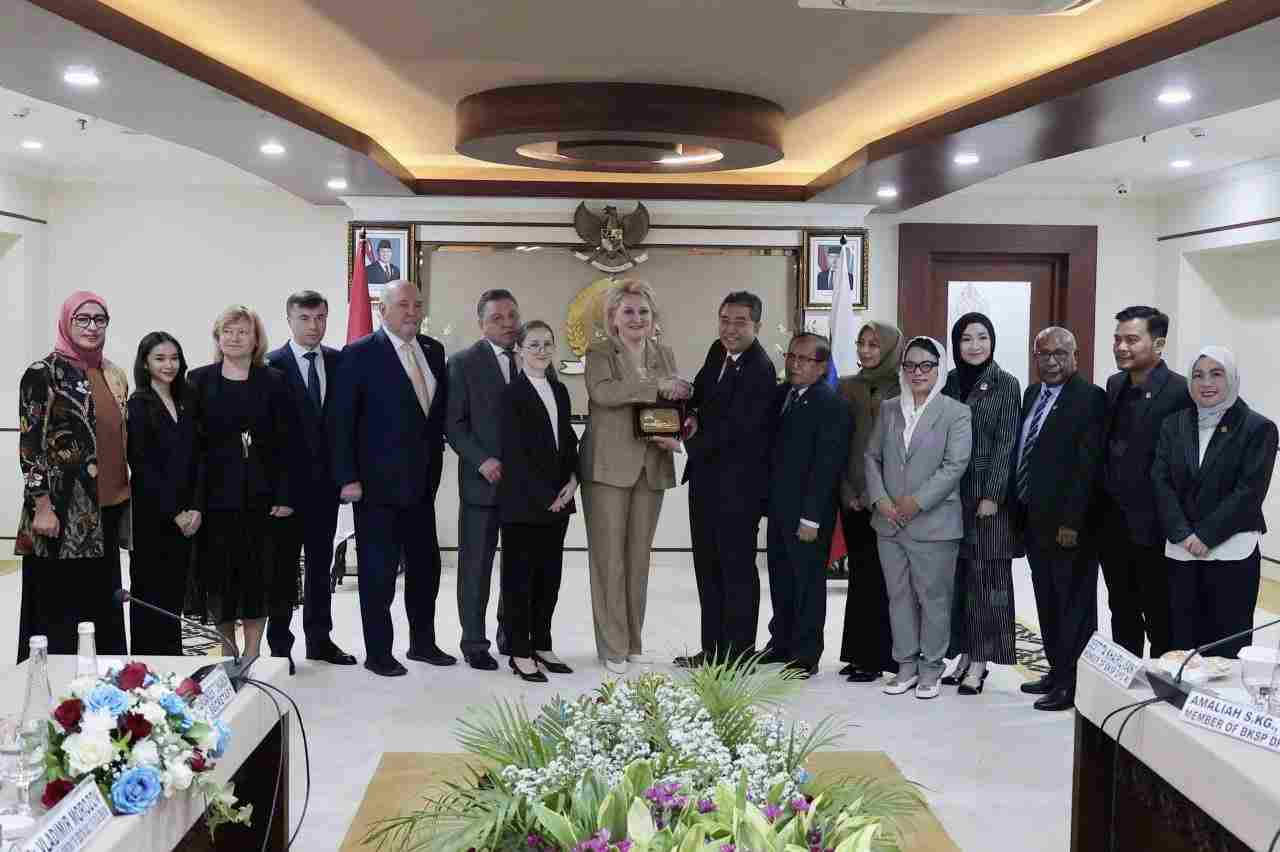Hari Santri: Api Jihad yang Tak Pernah Padam


SUARAMUDA.NET, SEMARANG — Setiap tanggal 22 Oktober, gema takbir dan shalawat menggema di berbagai penjuru negeri. Para santri berbaris rapi, mengenakan sarung dan peci, membawa semangat yang tak lekang oleh waktu: cinta tanah air sebagai bagian dari iman.
Namun di balik gegap gempita peringatan Hari Santri, tersimpan sejarah yang dalam dan nilai-nilai luhur yang membentuk fondasi keindonesiaan itu sendiri.
Jejak Sejarah dari Resolusi Jihad
Sejarah Hari Santri bermula dari peristiwa besar yang terjadi pada Oktober 1945, hanya dua bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Saat itu, pasukan Sekutu bersama NICA (Belanda) berusaha kembali menancapkan kekuasaan kolonialnya di tanah air. Situasi genting ini mengguncang semangat kemerdekaan yang baru saja diraih.
Dalam suasana itulah, para ulama dan kiai dari berbagai daerah berkumpul di Surabaya atas seruan KH. Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama.
Dari pertemuan itu lahirlah Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945, sebuah fatwa monumental yang menegaskan bahwa membela tanah air dari penjajahan adalah kewajiban setiap muslim.
Isi resolusi itu jelas dan tegas: “Berperang menolak dan melawan penjajah itu fardlu ‘ain bagi setiap orang Islam yang berada dalam jarak 94 kilometer dari tempat musuh menyerang.”
Fatwa tersebut tidak hanya membakar semangat juang umat Islam, tetapi juga menegaskan bahwa membela tanah air adalah bagian dari iman dan ibadah.
Dari situlah semangat jihad santri berkobar, memantik lahirnya Pertempuran 10 November 1945 — pertempuran heroik yang kini kita kenal sebagai Hari Pahlawan.
Resolusi Jihad bukan hanya seruan perang dalam arti fisik, tetapi juga panggilan moral: mempertahankan kemerdekaan sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan dan cinta kepada bangsa.
Dengan demikian, 22 Oktober bukan sekadar tanggal, melainkan simbol kebangkitan kesadaran nasional yang berakar dari iman dan pesantren.
Santri dan Nasionalisme yang Bersujud
Banyak yang mengira bahwa nasionalisme dan religiusitas berdiri di dua kutub yang berlawanan. Namun, sejarah santri justru membuktikan sebaliknya.
Dari pesantren-pesantren lahir gagasan tentang nasionalisme yang bersujud, yakni cinta tanah air yang lahir dari kesadaran spiritual.
Bagi santri, Indonesia bukan sekadar wilayah geografis, melainkan amanah Ilahi yang harus dijaga dengan ilmu, amal, dan akhlak.
Semangat ini pernah ditegaskan oleh KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah:
“Jadilah ulama yang berjuang di tengah umat, bukan yang menjauh dari kehidupan. Sebab agama harus menuntun bangsa, bukan meninggalkannya.”
Dalam hal ini, konsep “hubbul wathan minal iman” (cinta tanah air bagian dari iman) bukan hanya slogan, tetapi falsafah hidup yang menjiwai perjuangan mereka — dari medan tempur hingga ruang kelas, dari masjid hingga parlemen.
Santri menolak dikotomi antara dunia dan akhirat. Mereka belajar tafsir dan hadis, tetapi juga memahami politik, sosial, dan ekonomi. Mereka berdoa di masjid, tapi juga turun ke jalan untuk membela rakyat. Mereka berzikir dengan lidah, tapi berpikir dengan nalar.
Santri juga tidak hanya berjuang dengan bambu runcing, tetapi juga dengan pena, doa, dan keteladanan. Mereka menjaga nalar bangsa tetap waras di tengah gempuran ideologi asing dan arus pragmatisme zaman.
Makna Hari Santri di Zaman Kini
Ketika Presiden Joko Widodo menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015, bangsa ini seakan mengukuhkan kembali ikrar sejarah: bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari kekosongan spiritual, melainkan dari darah dan doa para santri yang tak kenal lelah menjaga marwah bangsa.
Namun Hari Santri bukan sekadar seremoni tahunan. Ia adalah pengingat moral kolektif bahwa tugas santri hari ini tak kalah berat dibanding masa lalu.
Musuh zaman kini bukan lagi kolonialisme bersenjata, melainkan penjajahan yang lebih halus: kebodohan, kemiskinan, disinformasi, dan krisis moral.
Menjadi santri di era digital berarti melanjutkan jihad dalam bentuk baru — menegakkan ilmu, menyebarkan toleransi, dan menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah dunia yang mudah terpecah oleh narasi kebencian.
Pesantren dan Masa Depan Indonesia
Pesantren sebagai rahim lahirnya para santri telah membuktikan dirinya sebagai institusi peradaban. Di dalamnya, ilmu agama berpadu dengan nilai kemanusiaan universal.
Dari ruang-ruang pengajian sederhana, lahirlah pemimpin bangsa, ulama, cendekiawan, dan aktivis sosial yang mewarnai perjalanan republik ini.
Kini, pesantren tidak lagi terkungkung dalam tembok tradisi semata. Ia berkembang menjadi pusat inovasi sosial, ekonomi, dan ekologi, melahirkan santri yang tak hanya saleh secara ritual, tapi juga produktif secara intelektual.
Hari Santri, dengan demikian, adalah cermin perubahan dan kontinuitas — bagaimana nilai lama yang luhur tetap hidup dalam wujud baru yang relevan dengan zaman.
Menyalakan Kembali Api Jihad Kebangsaan
Hari Santri mengajarkan bahwa jihad sejati tidak berhenti ketika merdeka telah diraih. Jihad adalah proses tiada henti: memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan menumbuhkan kasih sayang dalam kehidupan berbangsa.
Santri hari ini harus mampu memadukan dzikir dan pikir, kitab dan inovasi, tradisi dan teknologi. Sebab hanya dengan cara itulah, api jihad kebangsaan yang dinyalakan oleh KH. Hasyim Asy’ari dan para ulama terdahulu dapat terus menyala, menerangi jalan Indonesia menuju masa depan yang beradab.
Hari Santri bukan sekadar peringatan, tapi panggilan jiwa.Panggilan untuk kembali meneguhkan nilai-nilai keislaman yang menebar rahmat, dan kebangsaan yang mempersatukan.
Sebab dari pesantren, dari santri, dari doa yang sederhana — lahirlah semangat yang menjaga Indonesia tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. (Red)