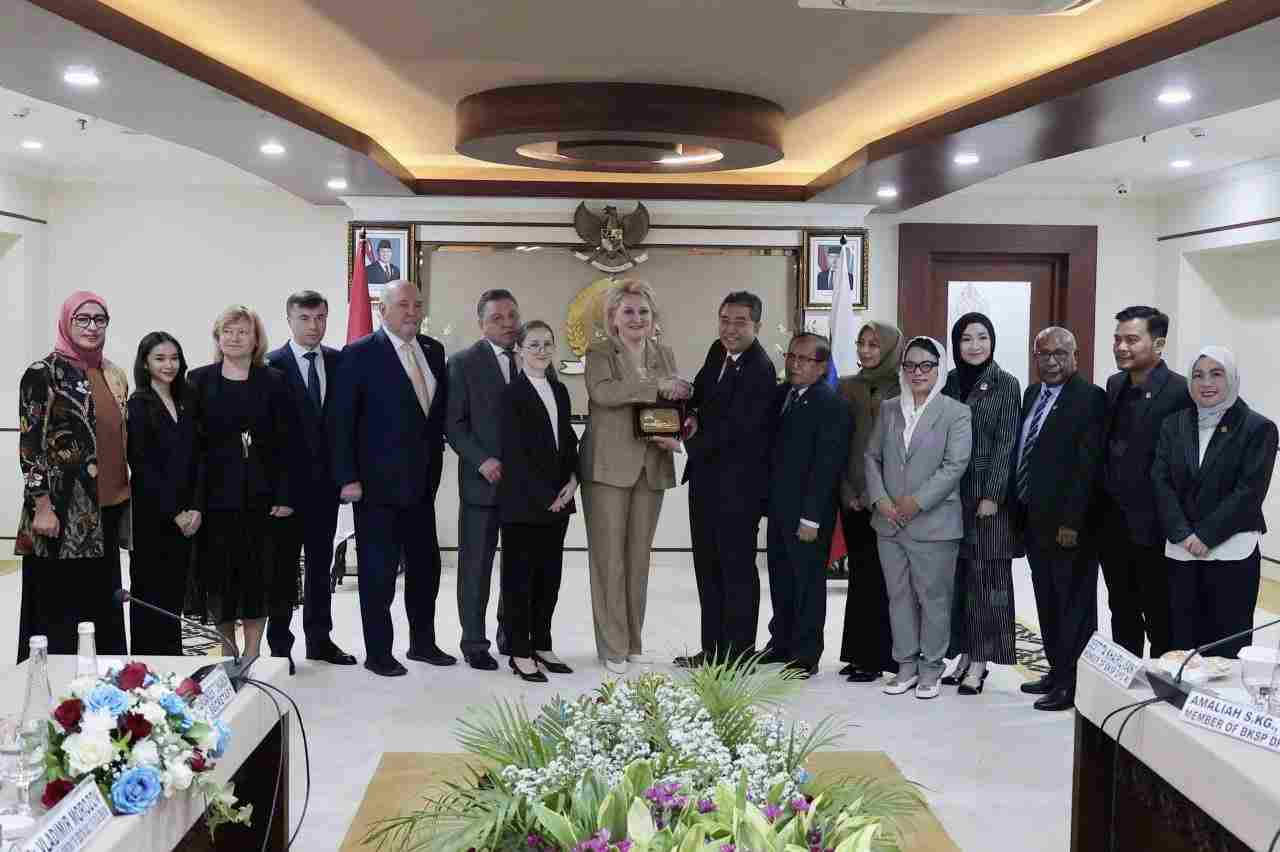China Hadapi Deflasi Ekonomi Ngeri, Akankah Merembet ke Indonesia?


SUARAMUDA, SEMARANG – China terus menghadapi tekanan deflasi yang sulit diatasi. Harga-harga di negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia ini telah mengalami penurunan selama enam kuartal berturut-turut.
Jika tren ini berlanjut hingga satu kuartal lagi, China akan menyamai rekor deflasi terpanjang yang pernah terjadi selama Krisis Keuangan Asia pada akhir 1990-an.
Para pembuat kebijakan di Beijing telah berjanji untuk melakukan langkah-langkah lebih agresif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan menahan penurunan harga.
Komitmen ini disampaikan dengan bahasa yang lebih tegas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seiring persiapan China menghadapi potensi perang dagang dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih.
Apalagi, seperti dilansir Bloomberg (14/12/2024), Presiden terpilih AS tersebut telah bersumpah akan memberlakukan tarif 60% pada ekspor China, kebijakan yang berpotensi menghancurkan perdagangan bilateral kedua negara.
Mengapa China Mengalami Deflasi?
Ketika ekonomi besar seperti AS kembali pulih setelah pandemi Covid-19, harga melonjak akibat permintaan yang tertahan bertemu dengan kekurangan pasokan barang.
Namun, skenario serupa tidak terjadi di China. Daya beli konsumen lemah, dan krisis sektor properti telah menggerus kepercayaan diri masyarakat untuk melakukan pembelian besar.
Regulasi ketat terhadap sektor-sektor dengan gaji tinggi seperti teknologi dan keuangan telah menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemotongan gaji, yang semakin menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja.
Di sisi lain, dorongan kebijakan untuk meningkatkan produksi barang manufaktur dan teknologi tinggi justru menciptakan kelebihan pasokan di tengah permintaan yang rendah, memaksa perusahaan menurunkan harga.
Lantas, Apa Dampak Buruk dari Penurunan Harga?
Harga yang lebih murah mungkin terlihat menguntungkan bagi konsumen pada awalnya, tetapi tidak selalu mendorong mereka untuk segera berbelanja.
Sebaliknya, masyarakat cenderung menunda pembelian barang mahal dengan harapan harga akan turun lebih jauh.
Hal ini bisa memperburuk aktivitas ekonomi, menekan pendapatan, dan memicu penurunan konsumsi yang lebih dalam, menciptakan spiral deflasi.
Deflasi juga meningkatkan tingkat bunga “riil” atau yang disesuaikan dengan inflasi di dalam perekonomian.
Biaya utang yang lebih tinggi membuat perusahaan sulit untuk berinvestasi, sehingga mengurangi permintaan dan memperparah deflasi.
Beberapa ekonom meyakini bahwa deflasi berbasis utang ini dapat memicu resesi atau depresi, karena masyarakat gagal membayar pinjaman mereka dan sistem perbankan menjadi terganggu.
Nah, apakah akankah fenomena deflasi China ini berdampak pada perekonmian Indonesia? Atau, bahkan perekonomian negeri ini mengalami deflasi dengan ‘gayanya’ sendiri? Semoga tidak! (Red)